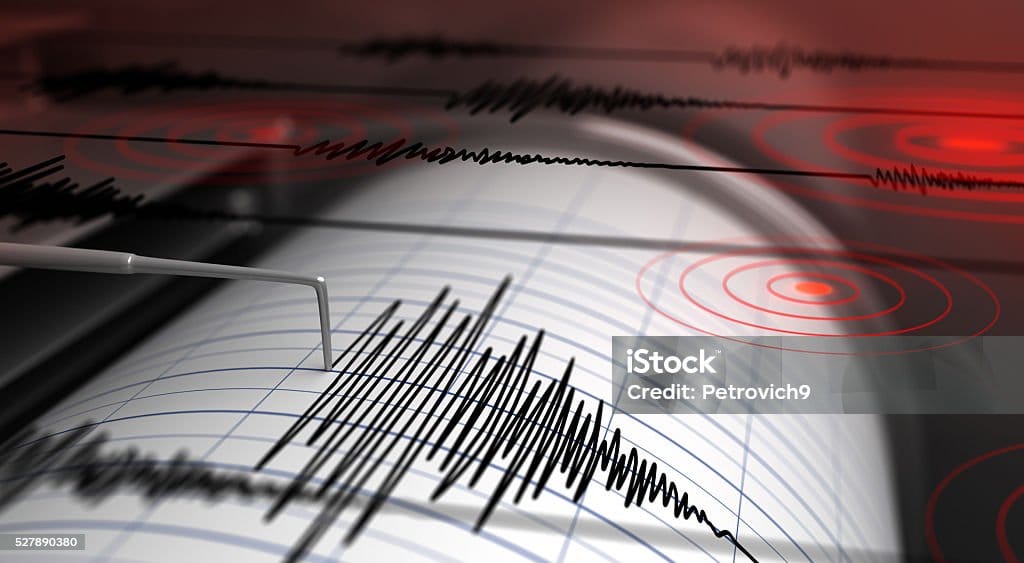Pidato peringatan Hari Kesaktian Pancasila pada 1 Oktober 2025 yang disampaikan oleh Menteri Kebudayaan, dengan mengusung tema “Pancasila Perekat Bangsa Menuju Indonesia Raya”, kembali mengukuhkan narasi resmi negara mengenai kokohnya fondasi ideologis bangsa. Dalam pidatonya, Menteri Fadli Zon menegaskan bahwa Pancasila adalah simpul pengikat bangsa Indonesia, sebuah benteng pertahanan ideologis yang telah teruji dari rongrongan sejarah, khususnya Gerakan 30 September 1965 yang disebut didalangi oleh Partai Komunis Indonesia. Retorika ini menyerukan kebanggaan atas keberhasilan bangsa dalam mempertahankan Pancasila.
Namun, di tengah khidmatnya peringatan dan gemanya narasi heroisme ideologis tersebut, sebuah pertanyaan mendasar muncul dan menantang kesadaran kolektif kita, apakah Kesaktian Pancasila benar-benar masih hidup, atau kini sekadar berdiri sebagai simbol kosong yang terjebak dalam mitos dan formalitas? Pertanyaan ini tidak lahir dari sinisme, melainkan dari perenungan terhadap kenyataan sosial-politik yang kita hadapi hari ini. Ketika kebijakan negara, perilaku elit, dan arah pembangunan kerap bertolak belakang dengan nilai-nilai luhur yang diagungkan setiap awal Oktober, keraguan terhadap makna dan fungsi sejati Pancasila menjadi tak terelakkan.
Untuk memahami mengapa Kesaktian Pancasila perlu dipertanyakan ulang, kita mesti kembali ke akar sejarahnya. Penetapan tanggal 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila melalui Keppres Nomor 153 Tahun 1967 oleh Presiden Soeharto tidak bisa dilepaskan dari konteks politik Orde Baru yang tengah membangun legitimasi kekuasaannya. Sejak awal, peringatan ini dikonstruksi sebagai simbol kemenangan ideologi negara atas ancaman komunisme, dan difungsikan sebagai alat untuk meneguhkan keabsahan rezim yang baru lahir dari kekacauan politik. Narasi yang dibangun dan diwariskan cenderung bersifat tunggal dan monolitik, menyederhanakan peristiwa G30S sebagai upaya kudeta sepihak oleh Partai Komunis Indonesia, seraya mengabaikan kompleksitas sejarah yang lebih luas.
Pandangan alternatif dari sejarawan dan peneliti yang menunjukkan keterlibatan berbagai aktor yang kemudian menjelma dalam krisis multidimensi—mulai dari adanya rivalitas global Perang Dingin, konflik politik domestik, polarisasi ideologi, kegagalan konsensus nasional, hingga krisis sosial-ekonomi—telah lama dimarginalkan dari wacana publik. Dengan mereduksi sejarah menjadi kisah hitam-putih antara “Pancasila yang sakti” dan “komunisme yang jahat,” Orde Baru membakukan satu versi kebenaran yang sulit digugat. Akibatnya, masyarakat terjebak dalam narasi resmi yang tidak memberi ruang bagi kritik historis dan pengakuan terhadap kompleksitas tragedi kemanusiaan yang terjadi setelahnya.
Narasi tunggal dan penyingkiran ingatan
Yang paling tragis dari narasi tunggal ini adalah terpinggirkannya sisi kemanusiaan. Fokus pada pahlawan revolusi yang gugur dalam peristiwa Lubang Buaya menyingkirkan ingatan tentang ratusan ribu hingga jutaan korban pembantaian yang terjadi setelah 1 Oktober 1965. Banyak di antara mereka bahkan tidak pernah menjalani proses hukum, hanya dicap sebagai simpatisan komunis, dan kemudian menjadi korban penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, hingga eksekusi massal. Jika Pancasila dianggap sakti karena berhasil “diselamatkan” dari komunisme, maka bagaimana kita harus memahami kenyataan bahwa dalam proses penyelamatan itu sila ‘kemanusiaan yang adil dan beradab’ justru dikorbankan?
Selama Hari Kesaktian Pancasila terus diperingati sebagai glorifikasi satu versi sejarah dan kemenangan satu pihak atas pihak lain, tanpa ada ruang untuk rekonsiliasi dan pengungkapan kebenaran, maka peringatan tersebut akan selalu menyisakan luka dan gagal menjadi ajang refleksi kebangsaan. Kesaktian yang hanya berdiri di atas peringatan seremonial, tanpa keberanian untuk menyembuhkan luka sejarah, hanyalah simbol kosong yang mempertahankan status quo ketidakadilan.
Lebih jauh, keraguan terhadap makna kesaktian Pancasila tidak hanya berasal dari kegagalan sejarah dalam menghadirkan keadilan, tetapi juga dari kenyataan politik dan sosial-ekonomi kontemporer yang mencerminkan pengkhianatan terhadap nilai-nilai luhur yang terkandung dalam lima sila itu sendiri. Dalam praktiknya, Pancasila semakin tampak seperti dokumen normatif yang agung di atas kertas, namun kehilangan daya hidup dalam keseharian politik dan birokrasi negara.
Sila pertama, ‘Ketuhanan Yang Maha Esa’, semestinya menjadi sumber etika dan akuntabilitas moral bagi setiap penyelenggara negara. Namun, kenyataan berbicara sebaliknya. Maraknya kasus korupsi di berbagai level pemerintahan, bahkan melibatkan pejabat tinggi, politisi, hingga penegak hukum menunjukkan nilai Ketuhanan telah kehilangan maknanya sebagai pengarah tindakan yang bermoral. Koruptor tidak hanya merampas hak rakyat, tetapi juga memperlihatkan ketidakpercayaan terhadap sanksi, baik secara hukum maupun spiritual. Mereka beribadah di depan publik, tetapi menyembah kekuasaan dan uang dalam praktiknya. Fenomena ini merefleksikan sebuah krisis moral mendalam, atau yang bisa disebut sebagai bentuk “ateisme etis” di tengah kehidupan berbangsa.
Sila kedua dan ketiga, ‘Kemanusiaan yang Adil dan Beradab’ serta ‘Persatuan Indonesia’, pun mengalami tantangan serius. Kekerasan berbasis identitas, diskriminasi terhadap kelompok minoritas, kriminalisasi aktivis, budaya impunitas alat-alat negara serta respons negara yang kerap represif terhadap suara-suara dari akar rumput memperlihatkan bahwa keadaban dan persatuan belum menjadi nilai hidup yang dijaga. Ketika aparat keamanan lebih cepat merespons kritik terhadap pemerintah ketimbang keluhan masyarakat tertindas, ketika konflik agraria lebih sering diakhiri dengan penggusuran paksa alih-alih dialog, maka nilai kemanusiaan dan persatuan hanya tinggal slogan.
Lebih ironis lagi, demokrasi permusyawaratan sebagaimana termaktub dalam sila keempat kini mengalami degradasi. Musyawarah dan perwakilan yang seharusnya mencerminkan kebijaksanaan kolektif rakyat telah digantikan oleh dominasi segelintir elit ekonomi dan politik yang mengendalikan proses legislasi secara tertutup. Di balik wacana demokrasi, kita menyaksikan praktik oligarki yang makin mengakar, partai politik berfungsi lebih sebagai mesin kekuasaan daripada sebagai wakil rakyat, sementara kebijakan publik sering lahir dari lobi, bukan dari hasil perdebatan yang partisipatif.
Sementara itu, sila kelima ‘Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia’, yang menjadi tujuan akhir dari seluruh sila, tampak semakin jauh dari kenyataan. Kesenjangan sosial yang terus melebar, konsentrasi kekayaan pada segelintir orang superkaya, dan lemahnya perlindungan terhadap kelompok rentan menjadi bukti kegagalan negara dalam mewujudkan cita-cita keadilan. Dalam kondisi ini, keempat sila sebelumnya Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, dan Kerakyatan secara moral dan fungsional ikut runtuh. Sebab, keadilan sosial bukan sekadar tujuan ideal, melainkan indikator keberhasilan pengamalan semua sila.
Lantas, jika realitas kita begitu jauh dari semangat Pancasila, mengapa kita tetap bersikukuh menyebutnya sebagai dasar negara yang final dan tak tergantikan? Jawabannya tidak terletak pada kemenangan politik di masa lalu, tetapi pada esensi filosofis Pancasila sebagai titik temu identitas bangsa yang plural. Finalitas Pancasila bukan sekadar keputusan konstitusional, melainkan hasil dari proses historis panjang yang melibatkan negosiasi kultural dan ideologis berbagai kelompok masyarakat. Pancasila adalah satu-satunya konsensus yang dapat merangkum keberagaman Indonesia ke dalam kerangka yang tidak memaksakan dominasi satu identitas atas yang lain.
Keberhasilan Pancasila bukan diukur dari kemampuannya menyingkirkan ideologi lawan, tetapi dari kemampuannya menjaga ruang hidup bersama di tengah perbedaan. Ia menjembatani nasionalisme, agama, dan sosialisme ke dalam satu ideologi yang inklusif. Dalam dunia yang kian terpolarisasi, Pancasila tetap relevan karena ia menjanjikan keadilan substantif, keadilan yang tidak sekadar legalistik, tetapi benar-benar dirasakan oleh rakyat dalam kehidupan sehari-hari.
Memaknai ulang Kesaktian Pancasila
Dengan demikian, Kesaktian Pancasila harus dimaknai ulang. Ia bukan lagi soal kekuatan ideologis melawan ancaman fisik dari luar, tetapi tentang kemampuan nilai-nilai Pancasila menginspirasi tindakan etis dan kebijakan yang adil di tengah krisis internal. Pancasila hanya benar-benar sakti jika ia mampu memandu negara untuk menegakkan keadilan, merawat kemanusiaan, memperkuat persatuan, dan menolak penyalahgunaan kekuasaan.
Revitalisasi kesaktian Pancasila harus dimulai dari keberanian membuka ruang pengakuan dan penyelesaian sejarah kelam bangsa. Tragedi 1965 tidak bisa terus-menerus ditutupi oleh narasi resmi yang mengabaikan korban sipil. Negara harus mengakui dan bertanggung jawab atas pelanggaran HAM masa lalu sebagai bagian dari komitmen terhadap sila Kemanusiaan. Tanpa rekonsiliasi yang jujur, keadaban hanya akan menjadi topeng belaka.
Langkah berikutnya adalah reformasi moral di tubuh birokrasi dan elite politik. Penegakan hukum terhadap korupsi harus dilakukan tanpa pandang bulu, tidak hanya untuk efek jera, tetapi juga untuk mengembalikan kepercayaan publik pada negara. Ketuhanan tidak boleh berhenti di pidato, melainkan harus menjadi sumber akuntabilitas etis dalam setiap kebijakan.
Akhirnya, negara harus berpihak secara nyata pada sila kelima. Keadilan sosial bukan sekadar retorika dalam pidato kenegaraan, melainkan prinsip operasional dalam pengambilan keputusan, dari reformasi pajak hingga alokasi anggaran, dari distribusi tanah hingga jaminan sosial. Musyawarah dan representasi harus dikembalikan maknanya, bukan sebagai prosedur formal, tetapi sebagai jalan untuk meraih mufakat yang adil dan partisipatif.
Kesaktian Pancasila, dengan demikian, bukan mitos yang diperingati setiap tahun. Ia adalah proyek kebangsaan yang harus dihidupi dalam tindakan nyata. Jika Pancasila tidak mampu menumbuhkan rasa takut pada Tuhan dalam hati para koruptor, tidak mampu menghentikan kekerasan alat negara atas rakyatnya, dan tidak mampu menjamin keadilan sosial bagi seluruh rakyat, maka bukan ideologinya yang harus dipersalahkan. Yang layak dipertanyakan adalah para pelaksana negara yang telah mereduksi ideologi luhur ini menjadi alat politik, formalitas seremonial, dan jargon kosong.
Tantangan kita hari ini bukan mempertahankan Pancasila dari ancaman luar, tetapi membuktikan bahwa Pancasila tetap sakti untuk melawan kehancuran moral, oligarki kekuasaan, dan ketidakadilan sistemik yang bersemayam di tubuh bangsa sendiri. Dan hanya ketika keadilan benar-benar menjadi kenyataan yang dirasakan setiap warga, barulah kita bisa berkata: Pancasila benar-benar sakti. Bukan karena Keputusan Presiden, melainkan karena hidup dalam kesadaran dan tindakan seluruh rakyat Indonesia.