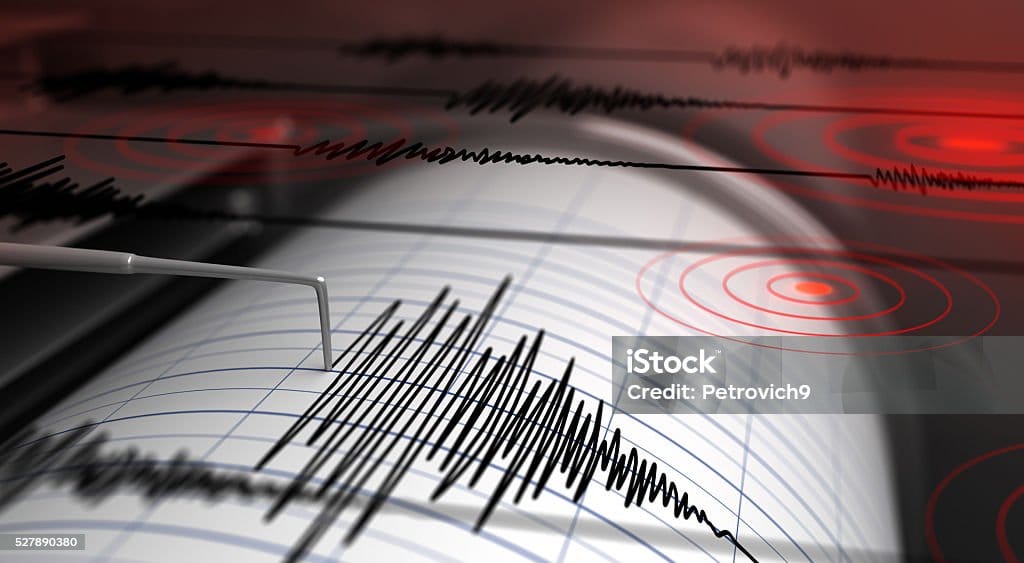Untuk membiayai ambisi dan menjaga kedudukannya, penguasa sering kali menggunakan dua senjata paling purba dalam sejarah manusia: rasa takut dan kendali (fear and control). Di tangan para tiran, ketakutan tidak berhenti sebagai alat represi, tapi juga komoditas politik yang disebarluaskan.
Sementara itu, kendali bukan hanya terletak pada regulasi hukum dan aparat, melainkan juga terdapat pada ketentuan-tak-langsung mengenai siapa boleh bicara, berekspresi, menuliskan sejarah, hingga simbol apa yang boleh dikibarkan.
Dalam konteks belakangan ini, bendera bajak laut Topi Jerami (Mugiwara) dari jagat fiksi manga-anime One Piece berubah menjadi ancaman yang dianggap serius oleh pemerintah. Dan, agaknya, pemerintah mulai menggunakan dua senjata purba pada pembuka tulisan ini untuk menangani sehelai bendera.
Bila kita cermati, peristiwa viralnya jolly roger kru topi jerami One Piece ini setidaknya menyodorkan dua fakta menarik. Pertama, banyak masyarakat sipil yang merasa terhubung sekaligus tergerak berpartisipasi mengibarkannya di bulan kemerdekaan RI ke-80 ini.
Tidak sedikit warga melakukannya sebagai bentuk protes sosial atas pemerintahan yang mereka anggap rusak, korup, dan menindas. Kedua, pemerintah yang terlalu reaktif hingga di level paranoia. Ini tampak pada sejumlah reaksi para pejabat publik.
Mantan kepala BIN yang kini menjabat Menko Polkam, Budi Gunawan, menyebutnya sebagai provokasi; Firman Soebagyo, anggota DPR Partai Golkar menilainya “bagian dari makar” dan harus ditindak tegas; hingga Sufmi Dasco Ahmad selaku Wakil Ketua DPR yang menuding “ada upaya pecah belah bangsa”. Semua itu hanya karena sehelai kain hitam dengan gambar tengkorak bertopi jerami yang nyengir.
Potret pemerintah yang reaktif dan paranoid semacam itu pada dasarnya telah banyak tergelar dan berulang kali muncul dalam sejarah. Tak terhitung para penguasa yang takut pada warganya hanya karena simbol. Kaisar Qin Shi Huang (Ying Zheng) dari Dinasti Qin (247 – 221 SM), misalnya, dalam catatan Sima Qian berjudul Shiji, pernah menitahkan pembakaran seluruh pustaka dan mengubur hidup-hidup ratusan cendekiawan yang tak sejalan dengannya.
Di Jerman era Nazi, perpustakaan Babilonia, hingga gubuk pustaka sekte Hasyasyin di lembah Alamut pun pernah hangus dan raib untuk selamanya akibat ulah penguasa lalim dan penjajah bengis. Di Indonesia era Orde Baru, sikap reaktif pemerintah yang menebar rasa takut (karena mereka juga takut dan paranoid) itu tercermin pada nasib buku-buku Pramoedya Ananta Toer yang dilarang hingga dibakar habis.
Praktik bibliosida, pemusnahan buku dan manusia semacam itu, telah banyak hadir di sekujur tubuh masa lalu. Sebagiannya terhimpun di buku Penghancuran Buku dari Masa ke Masa karya Fernando Baez. Dan di jagat One Piece, hal demikian Eiichiro Oda sampaikan lewat Tragedi Ohara. Di sinilah gema dunia fiksi merangsek masuk hingga ke alam sosial secara konkret.
Kekuatan meme
Dari semula mendapat julukan sarkas “kartun bajak laut”, kini simbol dalam One Piece menjelma meme—dalam definisi Richard Dawkins dalam The Selfish Gene (1976). Meme bukan sekadar lelucon visual yang viral (baca: menular), melainkan suatu unit budaya yang bereplikasi dalam kesadaran kolektif dan merambat ke banyak kepala. Ia bergerak cepat, menembus sensor, melintasi batas negara, ras, agama, hingga kelas sosial.
Meme punya daya kekuatan untuk menyampaikan “rasa geram yang terpendam”. Ia sanggup mewakili jerit batin publik tanpa pidato, mengibarkan protes sopir truk yang kecewa terhadap pungli, kasus-kasus korupsi, hingga kecurangan berantai di kalangan elite pemerintah.
Hal yang sama juga terjadi pada topeng Dali dari La Casa de Papel (mewarnai aksi-aksi demonstrasi), mural semangka untuk solidaritas terhadap Palestina, dan kini terjadi pada bendera bajak laut. Dan generasi muda yang merupakan mayoritas dari demografi Indonesia berhasil menjadi pionir dalam menyulap ikon budaya pop menjadi senjata politik.
Ironi pun terjadi: generasi yang dianggap apatis, mager, Indonesia cemas dan burnout yang terbenam oleh paparan TikTok kini berduyun-duyun ingin mengibarkan bendera yang membuat negara bergidik panik dan berkeringat waswas. Walhasil, gayung bersambut, keresahan terpendam ini pun menjangkau hingga melibatkan banyak generasi, lintas usia.
Tak heran bila dalam kajian kontemporer tentang kepemudaan, rasa geram dan harapan justru menjadi dua suntikan energi politik yang saling melengkapi. Dalam buku Young People and the Politics of Outrage and Hope (Editor: Peter Kelly dkk., 2018) menunjukkan bagaimana generasi muda di seluruh dunia—dari Athena sampai Jakarta—menyuarakan kegeraman mereka dengan cara baru yang tidak melulu lewat partai atau parlemen, melainkan melalui seni, simbol, hingga meme.
Mereka menggambar, memproduksi konten audiovisual, carousel tentang tengkorak bertopi jerami, dan menyebarkannya ribuan kali secara kreatif. Yang mereka tawarkan bukanlah lelucon, melainkan suatu pesan: bahwa ada sesuatu yang busuk, dan mereka tahu persis di mana titik pusatnya.
Pemerintah yang paranoid
Namun, kenapa negara dan pemerintah kita separanoid itu? Mungkin karena mereka sadar: simbol dapat mengoyak legitimasi lebih cepat ketimbang riset. Humor dan satire dapat melucuti kekuasaan, menjadikan mereka tampak konyol dalam sekedipan mata. Dan, satu lagi, pemerintah yang otoriter tak pernah benar-benar takut pada data—toh, mereka sendiri sanggup dan punya segala fasilitas dan biaya untuk memanipulasinya (ingat data BPS soal kemiskinan? Atau proyek penulisan ulang sejarah nasional?).
Hanya saja, ada yang tak sanggup mereka kendalikan dengan rasa takut: mereka gentar pada makna. Dalam sistem politik yang terlalu berbakat dalam mencipta “ilusi kebersatuan” dan “keharmonisan palsu”, kehadiran simbol alternatif beserta maknanya yang dipahami banyak orang adalah sebuah mimpi buruk.
Apalagi jika simbol itu bersifat jenaka, komikal, kebak parodi sekaligus menyiratkan tawa getir yang sarat ironi. Tak kaget jika dalam daftar panjang sejarah represi, penguasa lebih sering panik melihat gambar dan mural ketimbang mendengar argumentasi atau bahkan agitasi konfrontatif yang bersifat langsung.
Perihal reaksi paranoidnya, ada gagasan menarik dari Peter Sarosi, dari Serikat Kebebasan Sipil Hongaria. Di tahun 2017, ia sempat menyodokkan analisa pedas bahwa banyak pemerintah dunia saat ini sedang terjangkiti sebuah wabah global baru bernama “Paranoid Government Disorder” (PGD).
Ia menulis bahwa “pemerintah yang paranoid berani memperluas kendali dan pengawasannya sekaligus mengurangi hak-hak individu. Mereka pikir mereka dalam bahaya dan mencari tanda-tanda dan aneka ancaman yang membahayakan, yang secara potensi mereka tidak mempertimbangkan bukti-bukti lain (yang boleh jadi menampik hal itu).”
Di sinilah bias itu semakin menguat. Paranoia menjadi kepanikan reaktif yang dapat membuat mereka menelurkan kebijakan dan aksi-aksi represif yang menerabas hukum. (Bukankah panorama semacam itu sudah begitu marak belakangan ini?)
Lebih lanjut, bagi Sarosi, PGD adalah sebuah gangguan mental kolektif yang ditandai dengan paranoia negara beserta pemerintahnya yang punya suatu kecurigaan meluas dan bertahan lama, serta ketidakpercayaan yang digeneralisir terhadap masyarakat sipil. Di tahap inilah pemerintah mulai mendemonisasi warga biasa—hanya karena gempa kepanikan yang merambat di kepala mereka sendiri.
Pemerintahan semacam ini tengah mengalami delusi. Mereka gagal paham dan tak cukup cerdas untuk sanggup membedakan mana aksi damai dari kelompok tertentu dan mana upaya yang “memecah belah bangsa”. Protes simbolik yang damai sering kali malah mereka tuduh sebagai permusuhan dan penghinaan. Hal yang mirisnya sedang menjangkit pemerintah kita hari ini. Hanya karena sehelai kain dari “kartun bajak laut” impor dari Jepang!
Seorang netizen bilang, “hal gini diseriusin, giliran kasus-kasus serius dan demonstrasi penolakan warga malah dibecandain, nggak diurusin.” Dan seperti itulah wajah demokrasi tanah air kita di bulan Agustus kali ini. Sialnya, paranoid pemerintah di atas masih berlanjut.
Jika pemerintah dunia di jagat One Piece mendayagunakan Buster Call untuk membasmi semua musuh-musuh yang mereka anggap berbahaya, kini apakah pemerintah kita sedang meneladani pola yang sama? Bedanya mungkin tipis: dari Buster Call diubah menjadi Buzzer Call.
Cara fiksi bekerja
Rasanya sangat aneh. Di negeri ini, di mana kebenaran bisa diputarbalikkan, fiksi terkadang justru terasa lebih jujur, lebih bermoral. Dan simbol bendera bajak laut itu sendiri tak lain mirip dengan cara sastra bekerja: suatu taktik untuk mengatakan kebenaran, lewat kebohongan, dunia rekaan (fiksi). Ketika realitas mulai redup dan kehilangan makna, marwah, dan martabat, fiksi datang menagih tanggung jawab.
Namun, rupa-rupanya, di negeri ini, simbol keresahan bisa membuat penguasa marah, sekalipun ia berasal dari alam fiksi antah-berantah. Ketika banyak orang menjadikan One Piece itu sebagai titik temu dan ruang diskusi ilmu pengetahuan, sebagaimana terjadi dua kali Forum Going Ohara di Yogyakarta, pemerintah malah kebakaran jenggot dan mulai senewen, berang, dan melarang-larangnya.
Satu hal yang pemerintah lupa, sesuatu yang dilarang-larang justru sering kali menimbulkan dorongan misterius nan besar untuk semakin dilakukan. Apalagi jika larangan itu muncul dengan tanpa dasar sama sekali. Di samping itu, di balik simbol jolly roger dengan tengkorak kecil bertopi jerami yang tampak nyengir itu, tersimpan jutaan kemarahan yang belum selesai. Bila tidak ditangani secara tepat, ledakannya bisa mengarah ke para penguasa itu sendiri. Awas salah pendekatan! []