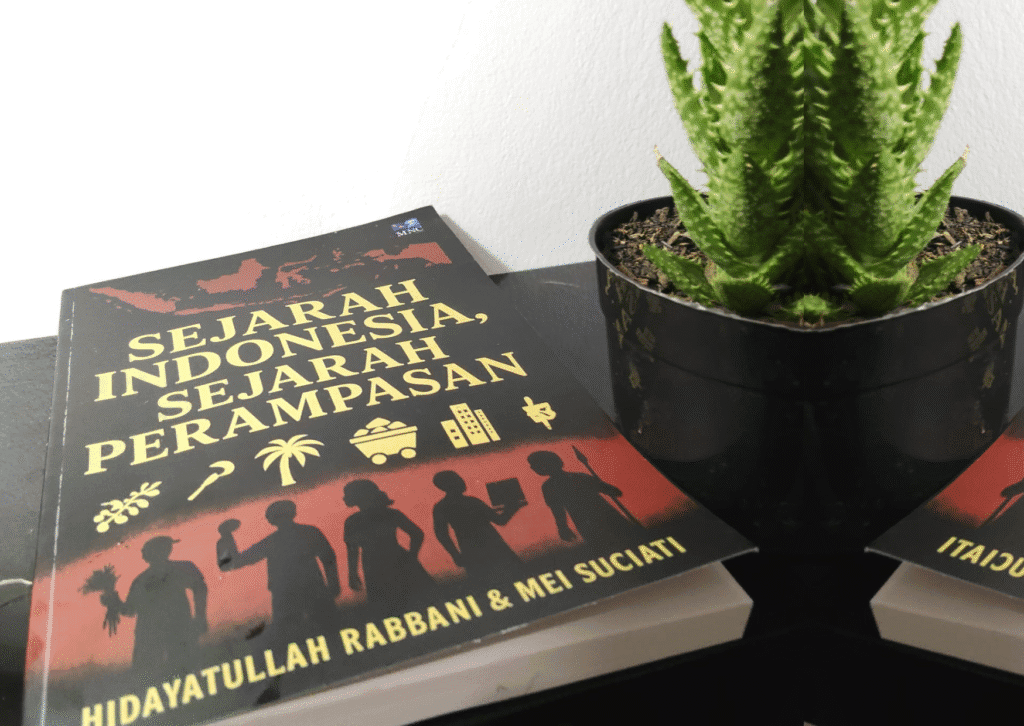SAYA, agaknya, memang ditakdirkan untuk terus menjadi manusia nomaden. Pernikahan, yang saya kira akan membuat saya menetap di satu tempat, justru memperjauh jarak perpindahan dari tempat tinggal lama ke tempat tinggal baru, rata-rata tiap dua tahun sekali. Hal ini terkait dengan tuntutan pekerjaan istri. Dan saya, berupaya menjadi suami yang baik serta terbantu dengan pekerjaan sebagai penulis penuh waktu yang relatif lentur soal lokasi kerja, pada akhirnya membuntuti ke mana pun istri pindah kerja.
Berpindah dari satu tempat ke tempat lain bukanlah hal mudah. Selalu muncul kecemasan tiap kali masa itu tiba. Kecemasan-kecemasan itu dibangun dari, misalnya, bagaimana kami mesti menyesuaikan diri dengan makanan, cuaca, air, dan seterusnya di tempat tinggal baru yang tentu saja berbeda dari tempat tinggal lama. Kami juga dirundung kesedihan lantaran mesti berpisah dengan teman-teman lama di tempat yang bakal kami tinggalkan. Dua tahun bukanlah waktu yang cukup panjang untuk membangun sebuah hubungan mendalam dengan orang asing, namun juga bukan waktu yang singkat untuk merasa terikat.
Ketika keluarga kecil kami mesti meninggalkan Yogyakarta untuk hijrah ke Samarinda pada awal 2022, kecemasan serupa namun dengan kadar yang lebih tinggi menjangkiti kami. Samarinda adalah tempat yang sepenuhnya asing, terutama bagi saya. Selama ini, saya hanya berpindah dari satu kota ke kota lain di Pulau Jawa. Dan ini adalah pertama kalinya saya akan menginjakkan kaki, bukan hanya sebagai turis, melainkan sebagai warga—setidaknya selama dua tahun—di luar pulau di mana saya lahir dan tumbuh. Saya tidak tahu apa-apa tentang cara hidup masyarakat, bahasa lokal, dan lain sebagainya. Saya bahkan tak punya satu pun kenalan di kota ini.
Namun kami pindah. Bagaimana pun kami pindah. Pengalaman berpindah-pindah kota selama ini membantu kami menyesuaikan diri dengan cepat menyangkut makanan, cuaca, kondisi air, dan membangun jaringan pertemanan. Namun, tentu saja ada satu dua kejutan, seperti selazimnya warga pendatang di satu tempat baru.
Sekali waktu, kira-kira satu setengah minggu setelah resmi menjadi warga Samarinda, seorang kenalan baru mengajak saya jalan-jalan keliling kota. Itu sekitar pukul tujuh malam. Cuaca cerah dan sedikit gerah. Langit bersih dengan bintang-bintang berkelipan. Tak ada tanda-tanda hujan. Orientasi saya soal arah dan ingatan tentang jalan buruk sekali. Saya tidak ingat sedang melintas di jalan apa, namun saya ingat betul ketika “genangan” air mendadak muncul menghadang jalan kami. Ya, “genangan” dalam tanda petik. Teman baru saya menyebutnya genangan, sementara saya jelas-jelas tidak bisa tidak menyebutnya sebagai banjir. Air setinggi betis meluber di jalan raya. Dan para pengguna jalan melintas dengan santai.
“Bagaimana bisa ada banjir di cuaca bagus seperti ini?” saya ingat, itu kalimat yang saya serukan saat itu.
Teman baru saya, menjawab dengan satu kalimat tanya, “Ikam hanyarkah di Samarinda?”

***
Ikam hanyarkah di Samarinda? dalam bahasa Indonesia kurang lebih berarti kamu baru ya di Samarinda? Dalam konteks percakapan antara saya dan teman baru saya, bukan berarti teman saya tidak tahu bahwa saya memang baru di Samarinda. Namun, pada waktu itu, saya menjawab dengan pasti, “Iya, saya baru di Samarinda.” Dan teman saya tertawa.
Di kemudian hari, saya tahu bahwa kalimat ikam hanyarkah di Samarinda? adalah kalimat template, jawaban standar yang digunakan untuk merespon pertanyaan-pertanyaan atau keluhan-keluhan menyangkut hal-hal yang umum terjadi di Samarinda. Kalimat itu mengandaikan jika si penanya atau si pengeluh adalah orang baru di Samarinda sehingga keheranan dengan fenomena-fenoma biasa yang terjadi di Samarinda.
Baca juga : Kapan Kita Layak meng-“cancel” Seseorang Maupun Karyanya Akibat Perilaku Tercela?
Ketika saya membicarakan harga makanan di Samarinda yang mencapai dua kali lipat harga makanan yang sama di Jogja, orang akan menyahut, ikam hanyarkah di Samarinda?
Ketika saya kaget mengetahui di rumah teman saya panas terik sementara di rumah saya yang berjarak dua kilometer saja hujan deras luar biasa, orang akan bertanya, ikam hanyarkah di Samarinda?
Ketika saya terpukau menyaksikan kapal wisata besar membelah Sungai Mahakam, orang akan berkomentar, ikam hanyarkah di Samarinda?
Dan seterusnya. Dan sebagainya.
***
Kalimat tersebut, yang seringkali diucapkan dengan tertawa dan karenanya terdengar seperti (dan hanya seperti) olok-olok, terbukti mangkus melunakkan benturan-benturan yang terjadi di diri saya terkait hal-hal baru yang saya temui. Kalimat itu membantu saya menyesuaikan diri dengan lebih cepat dan tidak gampang kagetan.
Namun, segera terbukti bahwa kalimat itu juga merupakan pisau bermata dua.
Sekali waktu, saya sedang diburu tenggat tulisan. Cuaca panas betul hari itu. Saya duduk di depan laptop bertelanjang dada dan hanya mengenakan kolor pendek. Saya menyalakan kipas angin kencang-kencang. Dan persis begitu saya mulai menggerakkan jari di papan ketik laptop, listrik mati. Itu adalah untuk kesekian kali saya mengalami listrik mati di Samarinda, satu peristiwa yang jarang sekali terjadi di tempat tinggal lama saya di Yogyakarta atau Surabaya. Hari itu, cuaca panas membuat saya tidak bisa mengetik dengan tenang, terlebih daya laptop saya tersisa kurang dari setengah. Tanpa bantuan angin dari kipas, saya memutuskan pergi ke kamar mandi untuk mengguyur kepala. Kesialan tak kenal hari. Air PDAM mati pula pada saat yang bersamaan.
Alih-alih memaksa diri mengejar tenggat, kekesalan yang bertumpuk justru mendorong saya membikin cerita di Instagram dan WhatsApp dengan isi yang serupa, yakni sebuah pertanyaan yang kurang lebih redaksinya berbunyi seperti ini: bagaimana mungkin di sebuah provinsi yang dibelah sungai-sungai raksasa, yang tanahnya dikeruk tiap hari demi ribuan ton batu bara, listrik dan air mati adalah kejadian sehari-hari?
Tak sampai satu jam, beberapa pesan masuk dengan isi yang nyaris serupa: ikam hanyarkah di Samarinda?
Kali itu, saya tidak tertawa atau tersenyum kecut sebagaimana biasa setiap kali mendapatkan jawaban yang serupa. Kekesalan saya justru bertambah dan itu membikin saya uring-uringan sendiri. Kalimat tersebut, pada titik ini, bukan lagi melunakkan benturan-benturan dalam diri saya, melainkan lebih menjadi semacam upaya normalisasi dari sesuatu yang menurut saya tidak betul.
Baca juga : Orangutan Kurus yang Viral di Kutai Timur: Induk Dievakuasi, Anaknya dalam Pencarian
Sebagai penulis (atau penyair), kejadian itu mendorong (atau memaksa) saya memikirkan ulang bagaimana bahasa bekerja. Segera setelahnya, saya menghubungi beberapa kenalan dan bertanya semenjak kapan kalimat ikam hanyarkah di Samarinda? ini digunakan orang. Tak ada jawaban lain selain dari dulu memang sudah seperti itu.
Lantaran tak mendapat jawaban yang memuaskan, saya mencoba melakukan analisis mandiri dengan modal watak kepengarangan yang kebetulan mendekam dalam diri saya. Oleh karena ini adalah analisis mandiri tanpa melibatkan riset mendalam, besar kemungkinan keliru. Samarinda, sejauh yang saya tahu, adalah sebuah kawasan dengan banyak kisah ajaib: Cerita tentang bayi tenggelam yang diantar seekor buaya ke tepian sungai, seorang pemuda yang mengalami kecelakaan motor setelah menolak mencicip makanan yang ditawarkan kepadanya, banjir tanpa hujan seperti yang saya singgung di atas, makanan baru masak yang tiba-tiba basi setelah dibawa melintas hutan tanpa disertai dedaunan segar yang baru dipetik, dan lain sebagainya.
Kalimat ikam hanyarkah di Samarinda? barangkali berguna, pada awalnya, untuk menerima segala keajaiban tersebut, melembutkannya, menjadikannya bagian dari sebuah realitas sehari-hari. Kalimat itu adalah sebentuk negosiasi untuk berdamai dengan peristiwa dan kondisi yang ada.
Namun, pada akhirnya, penggunaannya meluas. Ia digunakan untuk menormalisasi hal-hal yang seharusnya tidak terjadi. Banjir yang seringkali melanda kota ini—apalagi ketika hujan—mungkin saja disebabkan oleh tata kota yang tidak benar. Listrik dan air mati mungkin saja disebabkan oleh para pengelola yang tidak becus. Kebakaran yang acap muncul mungkin saja disebabkan oleh kesalahan manusia dan bukannya takdir. Dan, itu semua bukanlah sesuatu yang harus diterima begitu saja. Itu semua, menurut saya, adalah sesuatu yang mesti dicari pemecahannya, dan bukannya dianggap sebagai bagian dari satu keajaiban semisal kasus bayi tenggelam yang dibawa seekor buaya ke tepian dan berusaha diterima begitu saja dengan berbagai macam pemakluman.
Atau mungkin, kalimat itu lahir dari semacam keputusasaan. Hari-hari banjir selama puluhan tahun yang tak kunjung menemukan solusinya, misalnya, pada akhirnya memaksa warga untuk berdamai, untuk menganggapnya sebagai sesuatu yang wajar. Capek menghadapi kenyataan jika ribuan hektar lahan dan hutan yang rusak demi batu bara namun terus-terusan mengalami listrik mati mendorong orang untuk menerimanya sebagai suatu kenormalan. Apa yang mungkin dikerjakan manusia yang tak berdaya selain menerima apa adanya?
Tentu saja analisis asal-asalan saya bisa salah. Mungkin juga kalimat itu lahir untuk alasan-alasan atau sebab yang lain. Namun, bahwa hari ini kalimat itu digunakan sebagai normalisasi hal-hal yang tidak seharusnya terjadi adalah fakta. Kalimat itu, dalam tingkatan tertentu, membuat kita tumpul dan tidak kritis menuntut hak yang seharusnya bisa dipenuhi oleh negara. Saya, tentu saja tidak mengatakan bahwa negara—dalam hal ini pemerintah Samarinda—tidak melaksanakan kewajibannya dalam perkara memenuhi hak-hak warganya.
Itu sesuatu yang sudah menjadi tugas mereka dan masyarakat membayar pajak untuk itu, dan catatan ini memang tidak berpretensi untuk membicarakan masalah tersebut lebih jauh. Namun, mental masyarakat yang dibentuk baik secara sadar atau tidak oleh kalimat ikam hanyarkah di Samarinda? seharusnya juga tidak lantas melemah dan melupakan hak-hak mereka sendiri. Keputusasaan menghadapi banjir yang terjadi sehari-hari tidak lantas menjadi pembenaran bahwa banjir memang boleh terjadi.
Saya kira, ketumpulan dan ketidak-kritisan itu menyebabkan lahirnya mental dan sikap nriman. Masyarakat dengan mental nriman secara otomatis akan menerima segala sesuatu, sesulit apa pun, setertindas apa pun, sebagai sesuatu yang terterima, tidak perlu digugat, tidak perlu dipertanyakan, dan cenderung mensyukuri apa pun kondisi yang dihadapi.
Bahasa, dalam hal ini, ikut andil dalam terus terjadinya listrik mati, air mati, banjir, kebakaran, dan seterusnya yang merupakan masalah sehari-hari Samarinda. Bahasa seperti ini, saya kira, adalah bahasa yang perlu dirombak, direvitalisasi, dijejakkan lagi sehingga menjadi bahasa yang lebih menggugah dan berpihak kepada pemenuhan hak masyarakat. Banjir harus dikembalikan kepada banjir, yakni sesuatu yang mengganggu dan seharusnya tidak ada, alih-alih sebagai suatu kewajaran. Listrik dan air mati harus dikembalikan sebagai listrik dan air mati yang mengganggu, bukan listrik dan air mati sebagai suatu kewajaran. Kebakaran harus dikembalikan sebagai kebakaran yang mengerikan, bukan sebagai suatu kewajaran.
Tentu patut kita renungkan bagaimana bila bahasa (atau kalimat ikam hanyarkah di Samarinda?) ini terus menerus kita gunakan sebagaimana ia digunakan hari ini, yakni untuk menormalisasi segala sesuatu yang seharusnya tidak terjadi. Para pemangku kepentingan, misalnya, bisa menggunakannya untuk mencari pembenaran apa pun yang mereka lakukan, yang sebenarnya untuk kepentingan mereka sendiri, alih-alih kepentingan masyarakat yang lebih luas.
Sungguh, saya tidak bisa membayangkan bila misalnya, suatu hari, akan ada seorang ibu yang datang ke kantor gubernur dengan berurai air mata mengadukan anaknya yang mati tenggelam di bekas lubang tambang dan seseorang dengan enteng menyeletuk: ikam hanyarkah di Samarinda?
Ikam bisakah membayangkan?