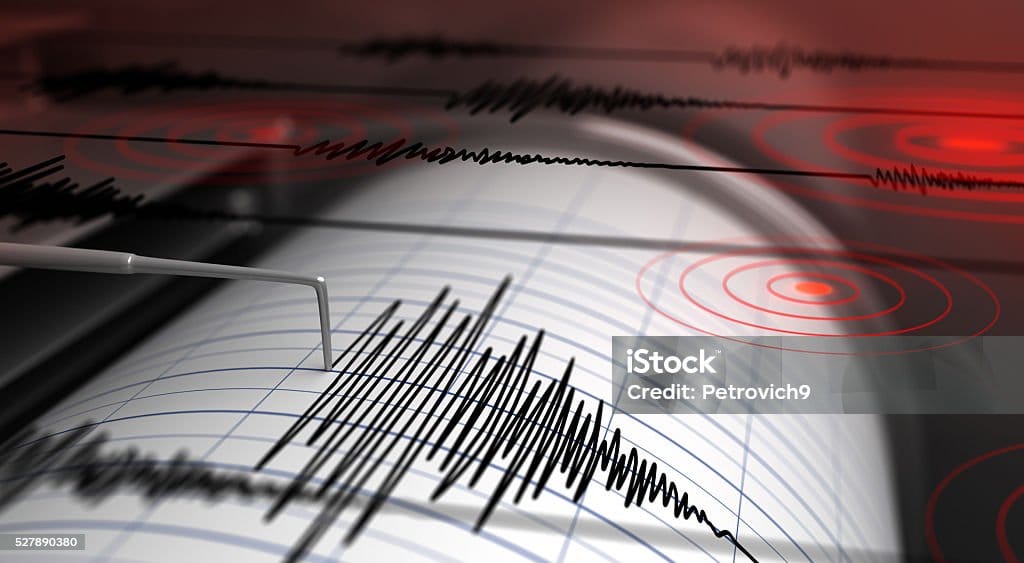Beberapa waktu terakhir, publik menyaksikan manuver hukum dari pemerintah yang disambut dengan tepuk tangan sebagian kalangan, tetapi mengundang tanya bagi sebagian lainnya. Pemberian abolisi terhadap Thomas Lembong dan amnesti kepada Hasto Kristiyanto oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi peristiwa hukum yang sarat nuansa politik.
Langkah itu memang sah secara konstitusional. Presiden punya hak prerogatif sebagaimana diatur dalam Pasal 14 UUD 1945 untuk memberi grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi dengan pertimbangan lembaga terkait. Namun, pertanyaannya, apakah kebijakan ini murni didasarkan pada pertimbangan keadilan dan rekonsiliasi nasional, atau sekadar bagian dari strategi politik kekuasaan?
Dalam demokrasi, tak cukup bagi kekuasaan eksekutif hanya bertindak dalam bingkai legalitas. Ia juga harus diuji secara etis dan institusional, apakah tindakannya menguatkan supremasi hukum, atau justru memperkuat ketergantungan pada figur dan melemahkan sistem hukum itu sendiri?
Pola “Masalah–Solusi–Popularitas”
Tindakan presiden memberi abolisi dan amnesti dalam situasi politik tertentu tampaknya mengikuti pola yang berulang: masalah mencuat, publik bereaksi, lalu presiden hadir sebagai “penyelesai”. Seolah ia menjadi penengah netral atas kekacauan. Padahal, dalam banyak kasus, kekacauan itu muncul dari kelemahan sistem hukum yang dikelola pemerintah itu sendiri.
Pola ini lazim dalam politik populis. Dalam bahasa David Icke (2010), ia memperkenalkan istilah itu sebagai problem–reaction–solution. Masalah sengaja atau tak sengaja dibiarkan membesar, memicu kegaduhan, lalu pemimpin muncul sebagai tokoh sentral penyelesai krisis.
Pola ini membangun narasi kepemimpinan kuat, responsif, dan solutif. Namun, di balik itu, ia menyembunyikan kenyataan pahit, bahwa reformasi sistemik sering kali tak menjadi prioritas.
Supremasi Politik atas Supremasi Hukum
Penggunaan hak prerogatif dalam kondisi proses hukum belum inkracht (putusan yang berkekuatan hukum tetap) memang memunculkan kekhawatiran. Dalam kasus Hasto dan Lembong, proses peradilan masih berjalan, atau setidaknya belum sampai pada tahap putusan yang final dan mengikat. Dalam konteks ini, intervensi politik bisa terbaca sebagai bentuk “super-yudisial”, yakni ketika eksekutif bertindak melampaui atau bahkan mendahului lembaga yudikatif.
Konsekuensinya tidak sepele. Publik bisa melihat hukum sebagai alat kekuasaan, bukan sistem yang berdiri mandiri. Padahal, dalam negara hukum, kepercayaan terhadap independensi lembaga yudikatif adalah prasyarat mutlak. Tanpa itu, legitimasi hukum bisa runtuh.
Reformasi Hukum yang Mandek
Sejak awal reformasi, janji pembaruan sistem hukum selalu menjadi narasi utama setiap rezim. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa reformasi hukum Indonesia mengalami stagnasi yang mengkhawatirkan.
World Justice Project (2023) mencatat skor Rule of Law Indonesia hanya 0,53 (skala 0–1) dan stagnan dalam lima tahun terakhir. Aspek penegakan hukum, absennya korupsi, dan akses keadilan masih berada di bawah 0,6.
Bahkan, dalam Indeks Persepsi Korupsi 2024, Indonesia hanya meraih skor 37 dari 100, merosot dibandingkan tahun-tahun era pemerintahan sebelumnya dan menempati urutan ke-99 dari 180 negara.
Sementara itu, pengawasan kekuasaan eksekutif juga tercatat mengalami penurunan. Di tengah dominasi koalisi besar di parlemen dan lemahnya institusi checks and balances, independensi hukum menjadi isu krusial yang belum terselesaikan. Bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang semula menjadi simbol harapan, kini dirundung krisis kepercayaan akibat serangkaian kontroversi dan intervensi politik.
Reformasi Sistemik, Bukan Solusi Instan
Langkah seperti abolisi dan amnesti bisa saja dibenarkan dalam konteks rekonsiliasi nasional atau pengampunan politik tertentu. Namun, jika langkah-langkah itu dijadikan strategi politik berkala, untuk meredam gejolak yang berasal dari sistem yang tidak beres, maka ia justru menjadi bagian dari masalah.
Alih-alih memperbaiki prosedur hukum, pemerintah justru memilih jalan pintas populer—mencabut kasus, membebaskan terpidana, atau merehabilitasi figur tertentu. Ini bukan reformasi, tetapi taktik populis yang merusak tatanan hukum dalam jangka panjang.
Reformasi hukum sejati memerlukan perombakan menyeluruh, dari independensi aparat penegak hukum, reformasi institusi peradilan, hingga penguatan mekanisme akuntabilitas publik. Tanpa itu, kita hanya berputar dalam siklus “masalah—krisis—solusi instan—popularitas”.
Demokrasi dan Risiko Ketergantungan pada Figur
Ada bahaya lain dari pola semacam ini, yakni ketergantungan rakyat pada figur, bukan pada institusi. Ketika presiden selalu hadir sebagai pemadam kebakaran politik, maka institusi seperti pengadilan, kejaksaan, atau KPK kehilangan otoritasnya. Akibatnya, rakyat lebih percaya pada keputusan lisan seorang pemimpin daripada prosedur hukum yang panjang namun adil.
Ini adalah bentuk degradasi demokrasi. Demokrasi yang sehat membutuhkan kepercayaan terhadap proses, bukan sekadar pada figur. Jika semua masalah hukum harus menunggu belas kasihan presiden, maka kita tidak sedang membangun negara hukum, melainkan negara kasihan.
Menuju Politik Hukum yang Adil
Dalam kondisi seperti ini, publik harus berani menuntut lebih dari sekadar kebijakan “penyelamatan” yang bersifat sesaat. Yang dibutuhkan bukanlah tindakan populis yang menyentuh gejala, tetapi komitmen untuk memperbaiki akar persoalan dalam sistem hukum.
Langkah awal yang perlu dilakukan adalah memulihkan independensi lembaga-lembaga penegak hukum seperti Mahkamah Agung, Kejaksaan, Kepolisian, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Otonomi lembaga-lembaga ini dari tekanan politik adalah fondasi utama negara hukum yang sehat.
Sayangnya, sejauh ini political will Presiden Prabowo justru tampak reaktif, bukan proaktif. Ia kerap hadir setelah persoalan mencuat, mendapat tekanan publik, atau menjadi viral, baru kemudian mengeluarkan kebijakan seolah sebagai solusi. Padahal, kepemimpinan yang berpihak pada rakyat seharusnya tidak menunggu krisis.
Keberpihakan pada keadilan sosial menuntut tindakan-tindakan berani yang menyasar kepentingan jangka panjang, seperti percepatan pengesahan RUU Masyarakat Adat, penuntasan RUU Perampasan Aset, pembenahan total sistem hukum, penghentian dominasi aktor-aktor politik yang bermasalah, komitmen menyelesaikan pelanggaran HAM dan konflik Papua secara bermartabat, serta menghentikan segala bentuk perampasan ruang hidup rakyat di berbagai wilayah di Indonesia.
Political will seharusnya diwujudkan dalam kebijakan struktural yang membela masyarakat luas—bukan sekadar menanggapi kasus-kasus yang sedang ramai dibicarakan publik.
Selain itu, sistem peradilan harus dibuka lebih transparan dan akuntabel, termasuk dengan menjamin perlindungan terhadap saksi, pembela hak asasi manusia, jurnalis, dan masyarakat sipil yang berani bersuara. Publik juga perlu terus diberdayakan melalui pendidikan hukum yang mendorong kesadaran bahwa keadilan bukanlah hadiah dari pemimpin, melainkan hak yang harus dijamin oleh sistem.
Dalam kerangka itu, pengawasan dari parlemen dan masyarakat sipil harus diperkuat agar segala bentuk hak prerogatif presiden tetap berjalan dalam koridor checks and balances. Tanpa pengawasan yang efektif, kekuasaan mudah berubah arah dan menggerus prinsip-prinsip dasar negara hukum.
Penutup
Amnesti dan abolisi bukanlah masalah pada dirinya. Dalam situasi tertentu, keduanya bisa menjadi alat penguatan demokrasi dan rekonsiliasi. Namun, jika digunakan untuk menghindari akuntabilitas hukum atau membangun citra politik sementara, maka ia menjadi ancaman terhadap keadilan dan reformasi hukum yang substansial.
Political will sejati bukan sekadar tampil menyelesaikan masalah viral. Semestinya ia hadir dalam bentuk kebijakan-kebijakan berani yang menyentuh struktur ketimpangan, mengurangi beban hidup masyarakat kelas menengah ke bawah, membenahi hukum, menghapuskan impunitas, dan menata kembali hubungan negara dengan rakyat dalam kerangka keadilan sosial.
Negara hukum tidak lahir dari tindakan simbolik. Ia lahir dari keberanian membenahi sistem, meski tidak populer. Kini saatnya kita menagih komitmen itu.
Baca esai lainnya di sini.

![Menimbang Abolisi dan Amnesti, Solusi [Politik] ala Prabowo - Hidayatullah Rabbani](https://propublika.id/wp-content/uploads/2025/08/abolisi-dan-amnesti-ala-prabowo-300x225.png)