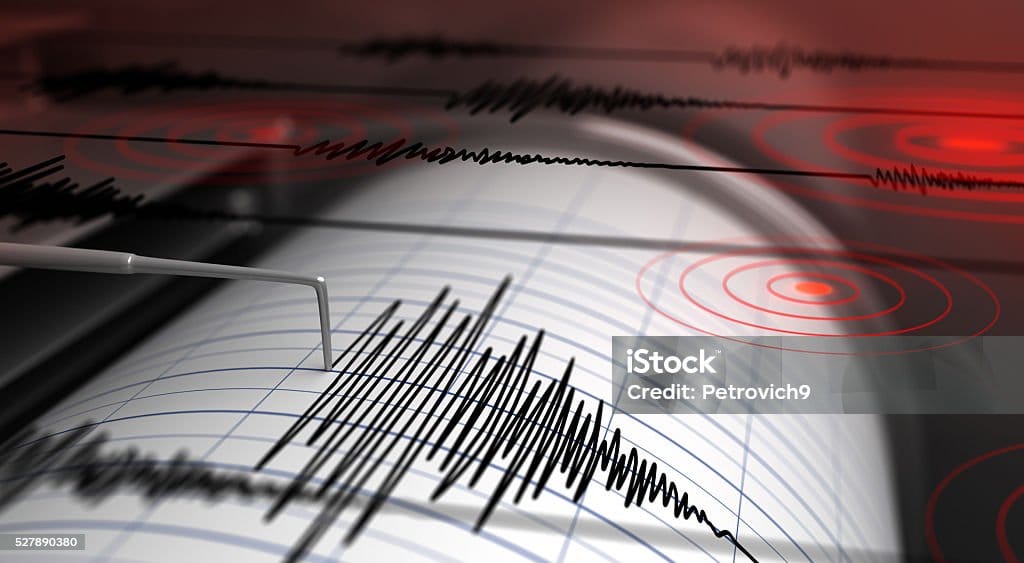Protes digital menggunakan simbol bendera One Piece, demonstrasi lokal akibat pajak bumi dan bangunan, hingga meletus kerusuhan dan diwarnai aksi penjarahan pada periode Agustus-September 2025 lalu menandai perubahan emosi publik terhadap politik Indonesia. Pada rentang waktu tersebut kita dapat melihat amuk politik sudah menjadi bahasa resistensi dari masyarakat.
Protes masyarakat Indonesia ini mendapat dukungan dari warga di kawasan Asia Tenggara. Mereka berbagi solidaritas melalui media sosial dan unjuk rasa di kedutaan Indonesia. Demonstrasi Agustus-September ini mengingatkan kita pada gerakan #MilkTeaAlliance yang berawal dari persoalan kedaulatan Taiwan dan kritik terhadap monarki Thailand hingga menjadi perjuangan global yang lebih luas melawan otoritarianisme. Media sosial pun turut berkontribusi pada eskalasi kondisi Arab Spring yang bermula dari protes seorang pedagang kaki lima yang dirazia aparat keamanan hingga menciptakan kondisi yang memaksa pemimpin-pemimpin di negeri-negeri Arab bertumbangan.
Setelah muncul pada berbagai protes di Indonesia, bendera One Piece dipakai pula oleh demonstran di Nepal, Prancis, dan Filipina. Demonstrasi di Indonesia dan Nepal sebenarnya dipicu faktor yang sama, yakni kesulitan ekonomi, korupsi, dan gambaran kehidupan yang kontras antara masyarakat dan kelompok pejabat.
Demonstrasi Nepal memunculkan kembali istilah nepo kids untuk menandai anak-anak pejabat yang mengumbar kehidupan mewah di media sosial mereka. Istilah nepo baby bahkan sudah muncul di Indonesia sejak transisi pemerintahan Jokowi dan Prabowo untuk menandai skandal konstitusi syarat calon presiden dan wakil presiden yang memuluskan jalan Gibran Rakabuming Raka menjadi wakil presiden. Peragaan hidup mewah yang ditunjukkan Kaesang Pangarep dan istrinya, Erina Gudono, yang bolak-balik menggunakan jet pribadi untuk sarana transportasi masih berada dalam spektrum perdebatan yang sama.
Eskalasi demonstrasi berbasis aspirasi di Indonesia dan Nepal pun menunjukan kesamaan. Protes di kedua negara kemudian berubah menjadi momentum ekspresi amuk politik yang menyasar pihak-pihak yang semula tak terjamah. Di Nepal, menteri ditelanjangi dan digiring masuk sungai, bahkan istri perdana menteri di sana mengalami kondisi kritis setelah terbakar bersama rumahnya.
Di Indonesia, setelah Affan Kurniawan dilindas kendaraan lapis baja milik polisi, kantor-kantor DPRD dan polisi menjadi sasaran pembakaran dan rumah-rumah pejabat menjadi sasaran penjarahan. Kendati aksi penjarahan tersebut dicurigai dimobilisasi oleh pihak tertentu, fenomena ini menjadi menyebar di internet dan diakses orang di berbagai negara. Mobil berplat dinas pun tidak luput dari sasaran amuk massa di Indonesia.
Oleh karena itu, tidak heran bahwa protes di Nepal terinspirasi demonstrasi di Indonesia. Kedua protes pun sama-sama digerakkan oleh anak muda yang sama-sama mengoptimalkan media sosial sebagai sarana perjuangan.
Vedi R. Hadiz menandai kekerasan politik sebagai ciri utama demokrasi illiberal di Indonesia. Kekerasan politik ini dapat terejawantahkan pembungkaman atau pengabaian terhadap aspirasi politik, ketiadaan akuntabilitas dalam penggunaan kekuasaan, akumulasi kekuasaan dan sumber daya, sampai kekerasan politik yang berdimensi simbolik seperti memamerkan kekayaan dan kesejahteraan di media sosial. Dalam konteks demikian, amuk politik menjadi lawan dari kekerasaan politik.
Hubungan dialektik antara protes di Nepal dan Indonesia telah melahirkan terminologi dinepalkan yang menandai amuk politik untuk merespon penyimpangan kekuasaan. Kata ini bermunculan di kolom komentar pemberitaan mengenai tindakan atau pilihan kebijakan publik yang diambil pejabat yang untuk menunjukkan protes sekaligus peringatan.
Protes-protes di media sosial bersifat sporadis tetapi menjadi fase pendahuluan penting ketika kita melihat kembali meletusnya demonstrasi Agustus-September. Signifikansi kolom komentar atau unggahan remeh seperti meme atau video pendek merupakan arena pertukaran afeksi. Setiap scroll adalah proses penumpukan, setiap viral adalah percepatan. Pertukaran kata dinepalkan sendiri berarti pula pertukaran emosi amuk politik.
Awalnya Nepal terinspirasi Indonesia. Kemunculan kata dinepalkan berarti pula pengakuan bahwa Indonesia dipengaruhi peristiwa di Nepal kemarin. Nepal menjadi imajinasi politik kewargaan Indonesia. Gerakan di Nepal tidak hanya berhasil melampiaskan afeksi amuk, tetapi bahkan melampauinya. Mereka menata amuk itu menjadi sebuah revolusi terorganisir.
Yang lebih menakjubkan, sebagian besar koordinasinya dilakukan melalui platform yang tidak lazim, yaitu Discord. Server-server Discord menjadi ruang warung kopi digital abad ke-21, tempat strategi dirancang, informasi disebarkan, dan mobilisasi dikelola. Elit Nepal yang terbiasa bermewah-mewahan tidak hanya dijatuhkan, tapi juga dipermalukan di ruang publik, dan yang paling simbolis, pemerintahan sementara justru “dipilih” melalui mekanisme partisipatif di platform tersebut. Discord, yang biasanya menjadi tempat komunitas gamer, berubah menjadi arena demokrasi digital yang radikal.
Peristiwa Musim Semi Arab, gerakan #MilkTeaAlliance, maupun demonstrasi Agustus-September menunjukkan kehebatan media sosial dalam menyebarkan amuk, tetapi sering gagal menjinakkannya menjadi perubahan sistematis. Anak muda Nepal menunjukkan kemampuan menjinakkan media sosial tersebut sehingga mampu mengelola energi dari afeksi yang tersirkulasi di platform publik seperti Twitter yang rentan diinterupsi oleh propaganda komputasional. Pilihan terhadap Discord menunjukkan pemahaman mereka mengenai media sosial itu sendiri. Discord meski bersifat sosial, tetapi lebih terbatas dan privat sehingga meminimalkan potensi gangguan koordinasi.
Dengan demikian, kehadiran kata dinepalkan dalam leksikon politik Indonesia bukan sekadar tren linguistik semata, melainkan alarm yang berdetak kencang. Ia adalah pengingat nyata bahwa amuk politik yang sporadis akan berubah menjadi gelombang revolusi terorganisir ketika akuntabilitas dan partisipasi publik terus diabaikan. Nepal, yang awalnya terinspirasi Indonesia, kini telah berbalik menjadi imajinasi politik yang konkret bagi warga Indonesia. Apa yang terjadi di Nepal memberikan gambaran yang lebih jelas dari sekadar wacana “Reset Indonesia”.