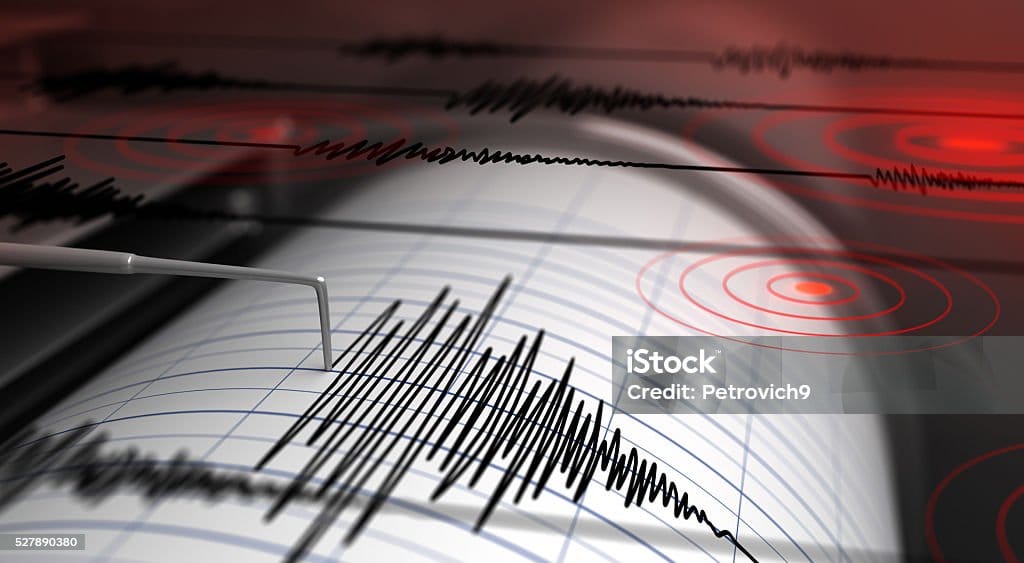Luka politik dan rakyat yang terabaikan
Akhir Agustus 2025, Indonesia diguncang sebuah peristiwa yang menyayat hati. Seorang pemuda bernama Affan Kurniawan, pengemudi ojek online, tewas setelah dilindas kendaraan taktis Brimob di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat.
Peristiwa ini terekam dalam video yang cepat menyebar di media sosial dan menimbulkan gelombang kemarahan publik. Bagi banyak orang, kematian Affan bukan sekadar kecelakaan tragis. Ia menjadi simbol dari luka yang lebih dalam, luka antara rakyat yang terus berjuang dalam kesulitan ekonomi dan elit yang dianggap tak lagi peduli.
Kemarahan publik sebenarnya sudah mendidih sejak pertengahan Agustus. Bermula dari momen Sidang Tahunan 15 Agustus, ketika video beberapa anggota DPR yang berjoget di ruang sidang beredar luas. Perilaku itu dianggap meremehkan martabat lembaga negara sekaligus mengabaikan penderitaan rakyat.
Tidak berhenti di sana, pernyataan-pernyataan kontroversial bermunculan. Wakil Ketua DPR sempat menyebut adanya kenaikan tunjangan beras dan bensin untuk anggota dewan, meski kemudian mengklarifikasi ucapannya.
Ahmad Sahroni menyulut amarah lebih besar dengan menyebut masyarakat yang menyerukan pembubaran DPR sebagai orang tolol sedunia. Nafa Urbach, yang juga duduk di parlemen, membela tunjangan perumahan anggota DPR sebesar lima puluh juta rupiah per bulan. Angka yang terasa jomplang dengan realitas masyarakat yang harus berjibaku dengan harga kebutuhan pokok.
Ketika Affan meninggal, amarah publik mencapai titik didih. Demonstrasi merebak di berbagai kota, berujung pada kericuhan dan aksi penyerbuan ke rumah sejumlah anggota DPR hingga rumah Menteri Keuangan. Namun, aksi penyerbuan dan penjarahan banyak yang menyangsikan dilakukan oleh demonstran organik. Ia terkesan dimobilisasi oleh kelompok terlatih untuk mengalihkan poin tuntutan demonstrasi dan berpeluang untuk diterapkannya darurat militer.
Atas rentetan peristiwa tersebut, Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri menyampaikan permohonan maaf, sementara pelaku dalam insiden rantis dihukum. Beberapa anggota DPR yang dianggap menyulut kontroversi pun dinonaktifkan oleh partai mereka. Namun, rakyat telanjur merasa dikhianati. Dari rangkaian peristiwa itu lahirlah Gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat, yang merangkum aspirasi dalam tujuh belas tuntutan jangka pendek hingga 5 September dan delapan tuntutan jangka panjang hingga 31 Agustus 2026.
Kemarahan rakyat hari ini tidak muncul tiba-tiba. Sejarah politik Indonesia memperlihatkan pola yang berulang. Pada masa Orde Baru, rakyat lama dibuat bungkam. Kritik terhadap pemerintah dibatasi dengan ketat. Namun, korupsi, kolusi, dan nepotisme tetap merajalela.
Reformasi 1998 menjadi titik balik ketika rakyat turun ke jalan, menuntut perubahan. Harapan besar lahir, tetapi perjalanan dua dekade lebih setelah reformasi menunjukkan bahwa demokrasi tidak serta merta membuat politik menjadi bersih. Praktik oligarki, politik uang, dan jarak antara elite dan rakyat tetap bertahan. Kasus demi kasus mengingatkan bahwa kepercayaan publik mudah terkikis.
Situasi ini menyadarkan kita bahwa hubungan antara rakyat dan elite politik sedang rapuh. Kepercayaan publik tergerus oleh sikap arogan dan kebijakan yang dirasa tidak berpihak.
Dalam keadaan seperti ini, kita butuh ruang lain untuk bercermin, ruang yang tidak hanya memberi kritik tetapi juga menawarkan jalan keluar. Indonesia sebagai bangsa memiliki warisan kebudayaan yang kaya. Salah satunya adalah panggung wayang, yang dengan segala kesederhanaannya mampu menyampaikan kritik lebih tajam daripada pidato panjang para pejabat.
Warisan kritik dari panggung budaya
Sejak lama, seni pertunjukan menjadi ruang aman bagi rakyat untuk menyampaikan kegelisahan. Dalam masyarakat tradisional yang penuh hirarki, seni menghadirkan cara untuk menegur kekuasaan tanpa harus mengangkat senjata.
Wayang, baik kulit maupun golek, berfungsi sebagai cermin sosial. Melalui tokoh-tokohnya, dalang bisa menyelipkan sindiran pedas terhadap kebijakan penguasa sekaligus menghibur penonton. Humor, musik, dan narasi epik menyatu menjadi medium yang ampuh.
Wayang golek Sunda memiliki peran istimewa dalam konteks ini. Tidak hanya sebagai tontonan, ia adalah tuntunan. Keluarga Giri Harja 3, yang dipimpin almarhum Asep Sunarya, dikenal konsisten menjadikan panggung wayang sebagai sarana pendidikan masyarakat. Asep pernah mengatakan bahwa pertunjukannya terdiri dari tujuh puluh persen dakwah dan tiga puluh persen penyampaian visi misi untuk masyarakat. Prinsip itu membuat setiap lakon bukan hanya cerita, tetapi juga pesan moral dan sosial.
Perlu dipahami bahwa wayang golek Sunda tidak lahir semata dari tradisi dakwah para wali. Ia juga mendapatkan pengaruh kuat dari dunia sastra. Dalam tradisi Sunda, sastra yang disebut kakawen atau kakawin menjadi salah satu sumber utama cerita.
Kakawin inilah yang kemudian berkembang sebagai sastra padalangan, yaitu teks-teks yang menjadi pegangan dalang. Dari kakawin, lahir cerita-cerita kreatif yang adaptif dengan perkembangan zaman. Tidak seperti wayang kulit Jawa yang lebih terikat pada pakem Mahabharata dan Ramayana, wayang golek Sunda lebih lentur dan terbuka pada pengembangan.
Beberapa kakawin penting yang menjadi rujukan di antaranya adalah Kakawin Arjunawiwaha karya Mpu Kanwa yang kemudian digubah dalam versi Sunda, Kakawin Bharatayuddha karya Mpu Sedah dan Mpu Panuluh yang memberi kerangka perang besar Mahabharata, serta Kakawin Ramayana yang diadaptasi dalam nuansa lokal.
Namun, dalang Sunda tidak hanya menyalin cerita itu apa adanya. Mereka mencampurkannya dengan kisah lokal, legenda rakyat, hingga ajaran moral Islami. Dari perpaduan itulah lahir cerita-cerita khas, misalnya lakon Cepot Rarabi atau Dawala Jadi Raja, yang tidak akan ditemukan dalam pakem Jawa maupun India.
Kakawin sebagai sastra padalangan memberi legitimasi bahwa dalang bukan sekadar penghibur, tetapi juga seorang pujangga yang berhak mencipta. Dengan dasar teks itu, dalang bebas berimprovisasi sesuai konteks sosial zamannya.
Maka tidak mengherankan jika di tangan keluarga Giri Harja, wayang golek mampu berbicara tentang Pancasila, demokrasi, bahkan isu korupsi dan kemiskinan. Fleksibilitas inilah yang membuat wayang golek Sunda begitu hidup, tidak membeku sebagai peninggalan masa lalu, tetapi senantiasa hadir mengikuti denyut nadi masyarakat.
Lakon Cepot Kembar: Sebuah cerita tentang negara
Lakon Cepot Kembar dimulai dengan hilangnya pusaka negara, Layang Jamus Kalimusada. Pusaka itu dianggap sebagai simbol kekuatan kerajaan Amarta. Para saksi menuduh Cepot sebagai pencuri. Tuduhan ini menggemparkan, karena Cepot adalah anak sulung Semar, sosok punakawan yang dikenal setia.
Kerajaan pun heboh. Yudistira sebagai raja meminta saudara-saudaranya bergerak. Bima dan Gatotkaca turun tangan, begitu juga Arjuna yang meminta nasihat Kresna. Perburuan terhadap Cepot dimulai.
Namun Cepot pencuri ternyata tidak mudah ditaklukkan. Bahkan Bima dan Gatotkaca yang terkenal sakti bisa dikalahkan dengan mudah. Cepot hanya berkata lemas dan mereka pun jatuh tersungkur.
Situasi ini membuat keduanya heran. Cepot kemudian menjelaskan bahwa ia memang mencuri pusaka, tetapi punya alasan mulia. Ia berjanji akan mengembalikan pusaka itu setelah tujuannya tercapai.
Gatotkaca yang penasaran akhirnya mencari Cepot asli ke desa Tumaritis. Ia menemukan Cepot bersama Dawala, kakaknya, dan menyadari ada dua Cepot berbeda. Cepot asli marah karena nama baiknya dirusak, sementara masyarakat sudah terlanjur mengucilkan keluarganya. Ketika mereka berbicara, datang raksasa yang menuntut penyerahan pusaka. Gatotkaca membela Cepot asli, pertarungan pun terjadi.
Di sisi lain, Arjuna berhasil menemukan Cepot pencuri. Dengan panah Gandeva, ia mencoba melumpuhkan, tetapi panah itu tak mempan. Kresna kemudian mengajak dialog. Di sinilah pesan utama lakon muncul.
Cepot pencuri berkata bahwa pusaka negara bukan hanya milik raja atau pejabat, melainkan juga milik rakyat. Ia memberi ilustrasi sederhana, seperti seseorang yang mengambil kembali barang miliknya dari rumah teman. Bagi Cepot, Layang Jamus adalah milik semua rakyat Amarta, bukan monopoli penguasa.
Lebih jauh, Cepot pencuri mengingatkan bahwa isi Layang Jamus adalah Panca Darma, yang menyimbolkan Pancasila. Namun, nilai itu hanya jadi slogan, tidak diamalkan baik oleh pemerintah maupun rakyat. Karena itu ia mencuri pusaka agar semua pihak ingat kembali tugas mereka.
Pemerintah dan rakyat harus duduk bersama, bermusyawarah, dan bergotong royong demi kesejahteraan bangsa. Kritik itu disampaikan dengan cara yang segar, melalui humor Cepot, tetapi maknanya amat dalam.
Lakon ini jelas menyasar situasi Indonesia modern. Pancasila sebagai ideologi negara sering kali hanya diucapkan, bukan dipraktikkan. Korupsi, ketimpangan, dan kemiskinan menjadi bukti. Melalui Cepot Kembar, panggung wayang mengingatkan bahwa negara bukan milik segelintir elit, tetapi milik semua rakyatnya.
Negara, rakyat, dan pusaka bernama Pancasila
Panca Darma dalam lakon Cepot Kembar adalah inovasi kreatif yang menyimbolkan Pancasila. Nilai itu dipinjamkan ke dalam cerita untuk menghubungkan dunia wayang dengan realitas Indonesia. Konsep ini menegaskan bahwa ideologi bukan sekadar teks dalam konstitusi, melainkan pusaka yang harus dirawat dan diimplementasikan isinya bersama.
Namun kenyataan sering jauh dari harapan. Pancasila kerap dijadikan jargon dalam pidato pejabat, tetapi sulit ditemui dalam kebijakan nyata. Keadilan sosial masih jauh dari terwujud. Kemiskinan tetap tinggi, sementara praktik korupsi menyebar luas. Nilai kemanusiaan sering tersingkir oleh kepentingan politik. Persatuan bangsa kerap retak oleh polarisasi. Dalam konteks itu, lakon Cepot Kembar hadir sebagai kritik yang menohok.
Jika kita menengok ke belakang, Pancasila sejak awal dirancang sebagai landasan moral sekaligus politik. Pada era Orde Baru, ia dijadikan alat indoktrinasi melalui Penataran P4. Generasi muda dipaksa menghafal butir demi butir, tetapi tidak pernah diajak memahami makna sebenarnya. Setelah reformasi, indoktrinasi itu hilang, tetapi praktik pengamalan Pancasila tetap tidak membumi. Nilai luhur masih berhenti di upacara dan slogan, bukan dalam tindakan nyata.
Pendidikan Pancasila yang kini kembali digalakkan di sekolah seharusnya tidak jatuh pada pola lama. Ia perlu diajarkan sebagai etika hidup bersama, bukan sekadar mata pelajaran formal. Pemerintah pun harus menunjukkan teladan, bukan hanya berbicara. Masyarakat kecil sudah terbiasa hidup bergotong royong, sementara elit sering kali terjebak pada kepentingan pribadi atau kelompok. Inilah yang dikritik dalam lakon Cepot Kembar. Pusaka negara harus dijaga oleh semua orang.
Punakawan dan kritik kekuasaan
Salah satu kekuatan wayang golek adalah kehadiran punakawan. Mereka bukan tokoh utama, tetapi justru sering menjadi pusat perhatian. Semar, Cepot, Dawala, dan Gareng mewakili rakyat kecil. Mereka lucu, jenaka, bahkan kadang sembrono. Namun di balik itu, mereka membawa suara nurani. Ketika raja atau ksatria khilaf, punakawan hadir untuk menasihati.
Semar adalah simbol kebijaksanaan rakyat jelata. Ia bisa menegur raja tanpa takut, karena wibawanya datang dari moralitas, bukan dari kekuasaan. Cepot, dengan humor dan kelucuannya, bisa mengkritik hal-hal yang serius tanpa terasa menggurui. Dawala dan Gareng menambah dinamika, menghadirkan ironi sekaligus kejujuran yang polos.
Fungsi punakawan ini relevan dengan politik modern. Rakyat sering dianggap lemah, tetapi sebenarnya memiliki kekuatan moral yang besar. Ketika suara rakyat diabaikan, krisis politik bisa terjadi. Lakon Cepot Kembar mengingatkan elit bahwa rakyat bukan sekadar objek kekuasaan. Mereka adalah pemilik sah negara. Suara punakawan adalah suara rakyat, dan mengabaikannya berarti mengabaikan fondasi negara itu sendiri.
Belajar dari Indonesia, belajar dari dunia
Wayang golek tidak lahir di ruang kosong. Ia adalah hasil dari dialog panjang antara tradisi besar India dengan kearifan lokal Nusantara. Dari India, kita mengenal kisah Mahabharata dan Ramayana. Epos ini menghadirkan tokoh-tokoh ksatria, dewa, dan raja yang membawa pesan tentang dharma atau kebenaran, karma atau hukum sebab-akibat, serta moksha atau jalan pembebasan. Wayang di India sangat sakral.
Pertunjukan dilakukan sebagai bagian dari ritual keagamaan. Cerita-ceritanya menekankan kosmologi, menghubungkan manusia dengan dunia dewa. Tidak heran jika tokoh utama selalu para bangsawan dan dewa, sementara rakyat jelata hampir tidak pernah hadir dalam panggung utama.
Ketika kisah itu tiba di Jawa dan Sunda, sesuatu yang unik terjadi. Tradisi lokal tidak menelan bulat-bulat, tetapi menyerap lalu mengolahnya. Di sinilah lahir tokoh-tokoh punakawan. Semar, Cepot, Dawala, dan Gareng tidak ada dalam naskah Mahabharata India. Mereka adalah ciptaan Nusantara, terutama ketika Islam mulai berkembang melalui para wali. Semar dihadirkan sebagai simbol rakyat kecil sekaligus penuntun spiritual.
Sunan Kalijaga, diyakini sebagai sosok yang menata ulang cerita wayang agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat Jawa kala itu. Bahkan sosok Cepot adalah karakter asli dalam pewayangan Sunda, yang mana asal-usulnya terinspirasi dari sosok Bagong atau Bawor dalam pewayangan Jawa. Jika dalam pewayangan Jawa, Petruk adalah sosok kakak dari Gareng (anak kedua) dan Bagong (anak bungsu), dalam pewayangan Sunda sosok Cepotlah yang menjadi kakak dari Dawala/Petruk (anak kedua) dan Gareng (anak bungsu).
Perbedaan ini bukan sekadar tambahan tokoh, melainkan perubahan filosofi. Jika wayang India mengajak manusia menengadah ke langit, memahami hukum kosmos dan dewa, wayang Sunda mengajak manusia menunduk ke bumi, menengok kehidupan sosial yang nyata. Punakawan adalah wajah rakyat. Mereka lucu, blak-blakan, kadang sembrono, tetapi justru karena itu mereka bisa mengatakan kebenaran yang sulit diucapkan oleh raja. Kritik sosial mengalir deras lewat kelucuan mereka.
Keluarga Giri Harja 3, terutama Asep Sunarya, mempertegas arah ini. Lakon-lakon yang diciptakan tidak berhenti pada kisah epik India, melainkan berani mengangkat isu kontemporer. Dalam lakon Cepot Kembar, kritik diarahkan kepada pemerintah dan rakyat sekaligus.
Pusaka Layang Jamus Kalimusada yang diperebutkan bukan lagi sekadar simbol sakti, tetapi dimaknai ulang sebagai Panca Darma atau Pancasila. Kritik ini jelas tidak mungkin muncul dalam wayang India, karena di sana fokusnya bukan pada negara modern dan rakyat jelata, melainkan pada hubungan manusia dan dewa.
Dengan kata lain, perbedaan paling mendasar adalah letak pusat nilai. Wayang India menekankan keteraturan kosmis. Wayang Sunda menekankan keteraturan sosial. Di India, kebenaran tertinggi adalah menjalankan dharma sesuai kasta. Di Sunda, kebenaran muncul ketika pejabat dan rakyat sama-sama mengamalkan nilai keadilan dan gotong royong. Filosofi Giri Harja menegaskan bahwa negara ada karena rakyat, bukan sebaliknya.
Jika kita melangkah lebih jauh, perbandingan ini memperlihatkan bahwa wayang Nusantara telah bertransformasi dari tradisi impor menjadi medium kritik lokal yang sangat kontekstual. Inilah kekuatan local genius. Budaya asing tidak ditolak, tetapi dicerna, lalu dikeluarkan kembali dalam bentuk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Giri Harja menjadi contoh nyata bahwa seni tradisi mampu hidup, berkembang, dan menyuarakan kepentingan rakyat tanpa kehilangan akarnya.
Dengan cara ini, wayang Sunda memberi pelajaran yang sangat relevan. Bahwa budaya tidak harus membeku sebagai peninggalan masa lalu. Ia bisa menjadi arena dialog antara sejarah, agama, dan politik. Dari India kita belajar tentang kosmologi. Dari Sunda kita belajar tentang demokrasi rakyat. Dan dari Giri Harja kita belajar bagaimana seni bisa menjadi jembatan antara tradisi dan kritik sosial yang tajam.
Menutup luka dengan ingatan budaya
Kematian Affan Kurniawan, demonstrasi, dan kontroversi politik belakangan ini menunjukkan rapuhnya hubungan antara rakyat dan elite. Kepercayaan yang rusak tidak bisa dipulihkan dengan pidato belaka. Kita butuh ruang untuk bercermin, dan salah satunya adalah melalui kebudayaan.
Lakon Cepot Kembar memberi gambaran bahwa negara bukan milik segelintir orang, melainkan milik bersama. Pusaka bernama Pancasila adalah milik seluruh rakyat, bukan sekadar slogan di bibir pejabat. Kritik melalui wayang menghadirkan solusi yang sederhana, yakni gotong royong dan pengamalan nilai luhur. Pesan ini relevan di tengah krisis politik dan ekonomi saat ini.
Sebagai bangsa, kita tidak boleh melupakan kekuatan budaya kita sendiri. Wayang, punakawan, dan cerita rakyat adalah sumber kearifan yang bisa menuntun langkah. Dari panggung sederhana di kampung-kampung, lahir kritik yang tajam sekaligus harapan yang tulus. Jika elit mau mendengar, rakyat siap bergotong royong membangun kembali kepercayaan. Jika tidak, jurang itu akan semakin dalam. Belajar dari lakon Cepot Kembar, kita diajak untuk menegaskan kembali bahwa sejatinya negara adalah rakyatnya.
Baca esai lainnya di sini.