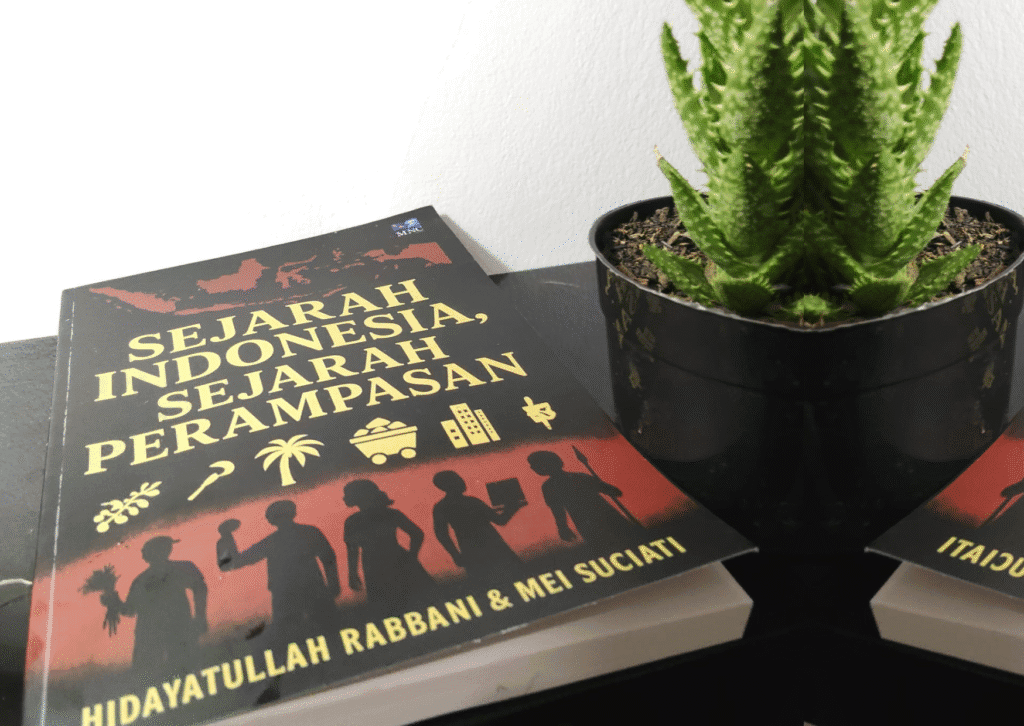Terbit pertama kali di Kompas Minggu, 22-12-1991. Halaman: 010
Oleh Afrizal Malna*
SASTRA Indonesia adalah kesusasteraan yang banyak membicarakan kekecewaan dan cenderung menghukum tokoh-tokohnya sendiri menjadi tokoh yang gagal. Adakah “sejarah kekecewaan” telah memasuki prosedur-prosedur personafikasi sedemikian rupa, tetapi tak terpecahkan di dalamnya? Salah satu dunia yang sedih itu, dan mengalami personafikasi dalam kekecewaan tersebut, banyak dihadapi oleh tokoh-tokoh wanita.
Dalam feminisme, prosedur tersebut bisa bersinggungan dengan tema yang menjadi landasan teks terbesarnya, yaitu emansipasi. Tetapi bagaimanakah kini, teks tersebut bisa menjelaskan dirinya kembali di hadapan fenomena berkembangnya kaum biseks, lesbian, dan homoseksual? Mereka tidak lagi hanya berhadapan dengan tesis bahwa lelaki menciptakan kekuasaan, dan wanita memperindah kekuasaan itu. Tetapi juga dengan tesis: kecantikan adalah kekuasaan.
Namun rupanya, dalam perkembangannya sendiri, emansipasi yang terlalu dihadapkan kepada dunia lelaki (kebudayaan lelaki, sejarah lelaki, teologi lelaki, sampai ke ideologi kodratisme wanita) telah menggeser arti emansipasi dan pergeseran-pergeseran yang berlangsung dalam masyarakat. Terutama dari peran wanita dalam pertumbuhan industri.
Faktor industri ini menjadi penting, karena pertumbuhannya mengandaikan stabilitas. Dan wanita menyimpan, atau menjadi basis reproduksi dari mitos kesetiaan yang menjamin berlangsungnya stabilitas. Dalam pengertian ini,emansipasi berarti produksi, dan bukan reaksi. Kalau aku kembali ke kamarmu—mencumbumu, adalah karena aku rindu kepastian-kepastian, kata Subagio Sastrowardoyo dalam sebuah puisinya.
Peran transitif
Tetapi prosedur personafikasi terhadap kesetiaan wanita dalam sastra, tampaknya telah terbelah. Atau ia berada di luar prosedur- prosedur individualisasi yang berlangsung dalam sastra. Dalam prosedur personafikasi tersebut, wanita ternyata lebih banyak menjalankan peran transitif. Dan selalu gagal memasuki individualisasi: wanita sebagai pribadi yang independen, memiliki dirinya sendiri.
Berbagai tokoh telah berjatuhan dalam peran transitif itu: Sitti Nurbaya gagal membangun jembatan antara dunia tradisi (Datuk Maringgih) dengan dunia modern (Syamsulbahri). Bahkan ketiga tokoh ini mati.
Hal ini terjadi lebih tragis pada tokoh Srintil dalam novel trilogi Ahmad Tohari, Ronggeng Dukuh Paruk. Srintil yang hidup dalam tradisi ronggeng di desanya, juga terseret ke dalam dunia politik serta kehidupan orang-orang kota yang tak dikenalnya. Dan akhir dari peran transitif ini, Srintil menjadi gila. Peran transitif itu tidak pernah mencapai solusi untuk dirinya sendiri sebagai wanita.
Pada cerpen Iwan Simatupang, Tunggu Aku di Pojok Jalan Itu, peran transitif yang dijalankan wanita, menjadi absurd. Di sebuah jalan, tokoh istri harus menunagu tokoh suami yang sedang membeli rokok. Dan ternyata si suami baru kembali 10 tahun kemudian. Di sini tokoh istri tetap setia menunggu di pojok jalan. Tetapi ketika sang suami menyapa, sang istri menjelaskan berapa tarifnya untuk tidur semalam. Seperti janjinya, sang istri tetap setia menunggu, tetapi telah memasuki peranan lain dalam penungguannya sebagai seorang pelacur.
“Speaker” perubahan
Apakah yang bisa dijelaskan dari personafikasi peran transitif yang diambil wanita pada prosa-prosa di atas? Pada satu sisi, kegagalan peran transitif itu bisa dijelaskan bahwa wanita telah gagal memasuki prosedur-prosedur individualisasi. Dalam hal ini, emansipasi mendapatkan maknanya. Bahwa wanita tidak banyak menggunakan emansipasi sebagai transportasi, untuk memecahkan ruang gerak bagi peranperan individualisasi yang dimasukinya.
Tetapi pada sisi lain penempuhan prosedur personafikasi pada peran transitif yang diambil wanita, menjelaskan sisi yang mendalam dari emansipasi itu sendiri. Bahwa wanita ternyata telah dipresentasi sebagai “speaker perubahan”. Karena semua peran transitif yang dijalankan di atas, menjelaskan adanya perubahan dalam masyarakat, yang ditandai oleh pengambilan peran tersebut.
Apa artinya itu? Artinya, wanita telah menempati sisi depan yang adaptatif dalam berhadapan dengan perubahan. Wanita itu adalah speaker dari perubahan itu sendiri. Tapi ia selalu gagal menempati peran transitif tersebut, karena ia berada di luar prosedur-prosedur individualisasi. Di sini wanita telah menjadi “speaker yang terbelah” untuk perubahan. Hal ini menjelaskan bahwa emansipasi, dalam konteks ini, harus bermakna sebagai individualisasi wanita. Dan itu tidak terjadi.
Pada beberapa prosa lain, peran ini memang tidak selalu gagal. Karmila, karya Marga T adalah salah satu kasus untuk Itu. Karmila harus hidup bersama seorang lelaki yang telah memperkosanya, sekaligus lelaki itu adalah ayah dari anak hasil perkosaan itu. Mereka kemudian hidup bahagia sebagai keluarga. Atau Nyai Ontosoroh dalam Bumi Manusia karya Pramoedya Ananta Noer, justru berhasil memasuki prosedur individualisasi. Ini kasus sebaliknya dari peran transitif yang dijalankan wanita dalam sastra.
Mereka mulai bertengkar
Prosedur individualisasi wanita dalam puisi, tampaknya lebih maju dibandingkan dengan prosa-prosa di atas. Dalam puisi, wanita lebih jauh memasuki prosedur tersebut. Puisi-puisi Chairil misalnya, mulai menghadirkan pertengkaran dengan wanita atau menghukum dirinya sendiri karena wanita : Melayang ingatan ke biniku, lautan yang belum terduga. Biar lebih kami tujuh tahun bersatu, barangkali tak setahuku, ia menipuku. Atau : Beginilah nanti jadinya. Kau kawin, beranak dan berbahagia, sedang aku mengembara serupa Ahasveros.
Dalam sajak di atas, wanita tidak lagi dijelaskan dari kesetiaannya, tetapi juga dari penyelewengan yang dilakukannya. Begitu pula lelaki tidak lagi dijelaskan dari wanita sebagai “kurban lelaki”, tetapi lelaki juga sebagai “kurban wanita”. Dalam dimensi yang lain, prosedur individualisasi diperlihatkan oleh Subagio dalam sajaknya seperti ini : Kekasihku lekas dewasa. Dia baru enam belas tapi sudah berkali-kali, lihat maknya membawa lelaki pulang, dan tidur di bilik tanpa pintu. Apa peduli, sejak itu dia sendiri suka ngerjakan begitu.
Sajak di atas tidak harus dikatakan sebagai yang telah menganjurkan demoralisasi sebagaimana novel Belenggu yang pernah dikritik serupa itu. Karena tidak ada teks yang sungguh-sungguh telah yatim piatu dari kenyataan. Sebagai teks, sajak di atas memperlihatkan kualitas dari prosedur-prosedur individualisasi yang berlangsung dalam masyarakat. Bahwa ia tidak selalu berlangsung tertib, normatif, tetapi juga menyimpang. Di situ, masyarakat juga bukan sebuah biografi bagi dirinya sendiri.
Contoh seperti ini lebih banyak lagi terjadi pada puisi-puisi Rendra atau Toeti Heraty. Walaupun pada Rendra, dunia wanita lebih banyak dijelaskan dari sosok ibu, kekasih, dan seorang lelaki sebagai petualang. Dan Toeti melihat banyak sandiwara serta topeng tidak hanya dalam relasi lelaki-wanita, tetapi juga antarsesama wanita: ah, sandiwara ini pun sudah terlalu lama, bila dua wanita bicara.
Sementara pada sajak-sajak Dorothea Rosa Herliany, banyak menampilkan dunia yang dihantui oleh waktu, daun yang berjatuhan, bunga yang layu, dan almanak yang tanggal satu demi satu : telah kudengar bisikan jauh daun-daun jatuh, terpetik luka matahari musim kematian. Telah kudengar jerit mengaduh daun-daun membusukm dalam tanah yang busuk.
Prosedur individualisasi yang ditulis oleh penyair wanita, di sini menampilkan sosok yang cepat berlalu. Mereka berhadapan pada “waktu hidup” yang terasa singkat. Personafikasi itu seakan-akan berhadaan dengan waktu sebagai lawan dari personifikasinya. Waktu mengandaikan ketuaan dan kematian. Artinya ada mitos kemudaan dan ketuaan yang membatasi personifikasi yang dilakukan wanita, yang membayangi kegagalan dalam prosedur individualisasi yang dijalaninya.
Sedangkan pada prosa yang ditulis oleh wanita, peran transitif itu terus berlangsung. Dalam salah satu cerpen Leila S, Chudori (dalam Malam Terakhir), peran transitif itu dijalankan oleh wanita yang masih kanak-kanak, yang mencoba memasuki dunia ibunya. Tetapi ia kemudian bunuh diri dalam dunia orangtua itu, bersama pakaian dan alat-alat kosmetik yang biasa digunakan oleh ibunya.
Seluruh uraian di atas, pada akhirnya mendesakkan satu pertanyaan, dari manakah kegagalan peran transitif wanita harus dijelaskan? Kenapa selalu ada keterbatasan dalam prosedur-prosedur individualisasi yang dltempuh wanita, tidak hanya dalam pengertian ruang, tetapi juga waktu? Pertanyaan kedua seakan-akan memang bisa menjelaskan pertanyaan pertama. Tetapi juga ada mitos seperti ini: Kepalaku yang lelah, kurebahkan dekat kabut pagi: aku ingin berhenti- tanpa berkata. Ia biarkan aku minum dari teteknya.
Kutipan itu, merupakan penggalan dari sajak Subagio Sastrowardoyo, yang menyinggung narasi besar dari sebuah mitos bahwa wanita adalah ibu dalam sejarah, yang tidak hanya melahirkan tetapi juga menghidupkan.
*) Afrizal Malna, seorang penyair.
Baca arsip lainnya di sini: Arsip.