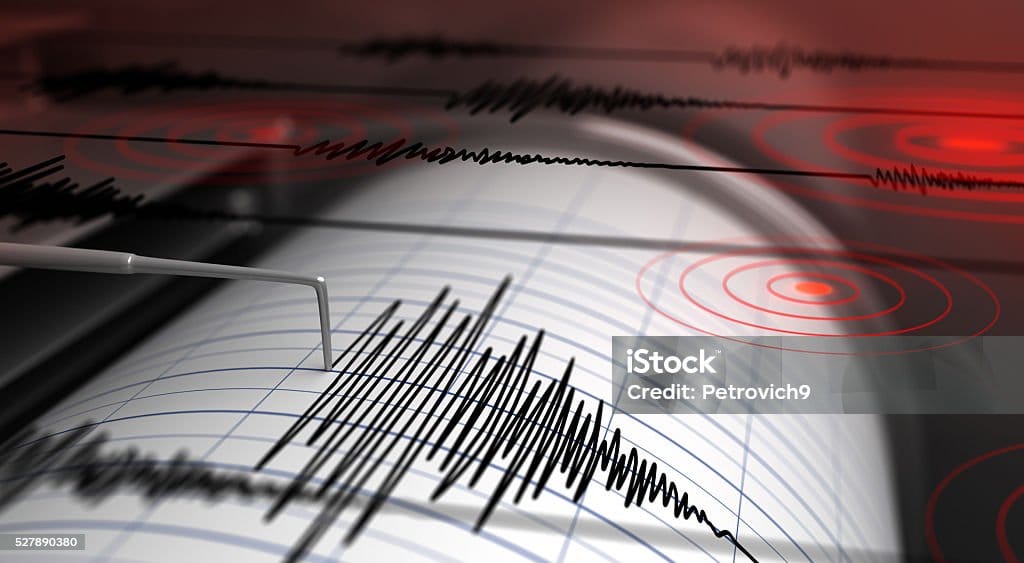Delapan puluh tahun adalah usia panjang bagi sebuah bangsa. Sejak proklamasi kemerdekaan pada 1945, Indonesia telah menempuh jalan berliku penuh pergolakan politik, pembangunan ekonomi yang tidak selalu konsisten, serta pencarian jati diri di tengah arus globalisasi.
Usia delapan dekade ini memberi kesempatan bagi kita untuk menengok ke belakang, menghitung capaian yang sudah diraih, sekaligus mengakui kekurangan yang masih membayangi. Refleksi ini penting bukan hanya untuk menilai masa lalu, tetapi juga untuk menyiapkan langkah menuju seratus tahun Indonesia merdeka yang akan tiba pada 2045.
Ketika kita mengukur perjalanan bangsa, perbandingan dengan negara-negara lain yang merdeka di periode serupa memberi gambaran yang jernih. India merdeka pada 1947, Vietnam meneguhkan kemerdekaan pada 1945 meski harus melalui perang panjang, Korea Selatan berdiri pada 1948 setelah terbelah dari utara, dan Republik Rakyat Tiongkok berdiri pada 1949.
Keempat negara ini, dalam kurun waktu delapan puluh tahun, berhasil melesat dalam berbagai bidang. Mereka bukan hanya menyeimbangkan diri dengan negara maju, melainkan mampu menunjukkan strategi pembangunan yang konsisten dan berani. Indonesia, meskipun kaya sumber daya alam dan punya banyak penduduk, terlihat belum menempuh lompatan yang sama.
Tingkat kesejahteraan dan pendapatan per kapita
Salah satu ukuran yang paling mudah dilihat adalah tingkat kesejahteraan. Pada 1960-an, pendapatan per kapita Korea Selatan lebih rendah dari Indonesia. Namun, pada 2020-an, Korea Selatan sudah mencapai pendapatan per kapita lebih dari 30.000 dolar AS, sementara Indonesia masih berkisar di bawah 6.000 dolar.
India, meskipun jumlah penduduknya lebih dari satu miliar, berhasil menumbuhkan kelas menengah yang besar dan menjadi salah satu pusat pasar global. Vietnam yang baru memasuki tahap industrialisasi kini memiliki pendapatan per kapita lebih tinggi dari Indonesia, padahal mereka berangkat dari kehancuran perang. Tiongkok, dengan pertumbuhan ekonomi pesat sejak reformasi 1978, kini menjadi raksasa dengan GDP terbesar kedua dunia.
Indonesia, dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, justru masih menghadapi ketimpangan besar. Kesejahteraan belum merata dan masih bergantung pada ekspor komoditas mentah. Kekuatan ekonomi Indonesia lebih banyak bertumpu pada konsumsi domestik ketimbang industrialisasi berorientasi ekspor.
Salah satu penyebab yang jarang dibicarakan secara terbuka adalah keberadaan segelintir pihak yang memiliki kekuatan untuk mengendalikan kebijakan negara di sektor strategis. Mereka sering disebut sebagai mafia negara. Kelompok ini memanfaatkan celah politik dan ekonomi untuk mengarahkan regulasi agar menguntungkan kepentingan mereka, baik dalam pengelolaan sumber daya alam, perizinan ekspor impor, maupun dalam menentukan arah industrialisasi. Akibatnya, kebijakan yang seharusnya mendukung kesejahteraan rakyat luas seringkali hanya memperbesar akumulasi keuntungan bagi sebagian pihak saja.
Pendidikan, literasi, dan kualitas sumber daya manusia
Kemajuan sebuah bangsa ditentukan oleh kualitas manusianya. Tingkat melek huruf Indonesia memang membaik drastis sejak kemerdekaan, tapi masih tertinggal dalam kualitas pendidikan tinggi dan penguasaan teknologi. Korea Selatan, yang pada awalnya lebih miskin, memilih menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama. Dalam beberapa dekade, negeri itu berhasil mencetak generasi yang disiplin dan inovatif.
India, dengan segala kerumitannya, melahirkan ribuan insinyur dan pakar teknologi yang kini menduduki posisi penting di perusahaan global. Vietnam menyiapkan tenaga kerja terampil yang sesuai kebutuhan industri manufaktur. Tiongkok bahkan menjadikan pendidikan sains dan teknologi sebagai tulang punggung pembangunan, dengan universitas riset yang masuk peringkat dunia.
Indonesia, meski memiliki peningkatan signifikan dalam angka melek huruf sejak awal kemerdekaan, masih menghadapi masalah serius dalam kualitas pendidikan. Laporan internasional tentang kemampuan membaca, matematika, dan sains (PISA) menunjukkan capaian pelajar Indonesia masih berada di bawah rata-rata negara-negara dengan periode kemerdekaan hampir sama. Masalah lain adalah kesenjangan kualitas pendidikan antara perkotaan dan pedesaan, serta lemahnya budaya membaca yang menyebabkan masyarakat seringkali kurang kritis dalam menyaring informasi.
Fenomena ini membuat sebagian masyarakat mudah terbawa arus isu-isu yang sengaja dimainkan untuk memecah belah persatuan. Alih-alih memperkuat daya kritis dan semangat kolaborasi, masyarakat kerap dipengaruhi narasi provokatif yang justru melemahkan proses pembangunan.
Kondisi ini menjadi tantangan besar karena kualitas sumber daya manusia bukan hanya ditentukan oleh tingkat literasi teknis, tetapi juga oleh kedewasaan berpikir dan ketahanan terhadap manipulasi informasi. Negara-negara lain yang seangkatan dengan Indonesia relatif lebih cepat membangun kohesi sosial dalam rangka mendukung pembangunan nasional, sementara Indonesia masih sering terjebak dalam pertentangan internal yang menghambat kemajuan.
Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan industrialisasi
Kemajuan suatu bangsa ditentukan pula oleh sejauh mana ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi tulang punggung pembangunan. Korea Selatan sejak 1970-an mulai berfokus pada industrialisasi berbasis teknologi, Vietnam pada 1990-an mulai menata ulang anggaran negaranya dengan efisiensi ketat agar sebagian besar dapat dialihkan untuk mendukung riset dan pengembangan, sedangkan Tiongkok sejak era Deng Xiaoping mendorong besar-besaran riset terapan yang kemudian melahirkan raksasa teknologi global.
Indonesia sebenarnya sempat memiliki visi yang cukup berani. Pada masa Demokrasi Terpimpin, Presiden Sukarno hampir menjalin kerja sama dengan Republik Rakyat Tiongkok untuk pengembangan teknologi nuklir sebagai sumber energi dan landasan industrialisasi nasional. Namun, rencana ini tidak pernah terealisasi karena gejolak politik domestik yang berakhir pada jatuhnya Sukarno. Peristiwa politik tersebut tidak hanya mengakhiri wacana kerja sama nuklir, tetapi juga memutus kesinambungan agenda riset strategis Indonesia.
Pasca 1965, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia berjalan pasif dan lebih banyak tersandera oleh birokrasi yang tidak sehat. Daniel Dhakidae, dalam studinya tentang cendekiawan dan kekuasaan Orde Baru, menunjukkan bagaimana para ilmuwan dan akademisi lebih sering dijadikan instrumen legitimasi politik ketimbang motor kemajuan.
Pertama, banyak cendekiawan direkrut untuk memperkuat narasi pembangunan yang diinginkan pemerintah sehingga riset diarahkan bukan pada kepentingan bangsa secara otonom, melainkan untuk menopang legitimasi kekuasaan.
Kedua, lahir kategori baru yang disebut Dhakidae sebagai “ilmuwan organik negara,” yakni kaum intelektual yang dekat dengan birokrasi dan militer, sehingga independensi akademiknya melemah.
Ketiga, universitas dan lembaga penelitian dikendalikan agar hanya menghasilkan pengetahuan yang sesuai dengan arah pembangunan resmi, sementara penelitian yang kritis terhadap pemerintah dianggap berbahaya.
Keempat, tradisi intelektual kritis semakin merosot karena banyak akademisi lebih memilih kompromi dibanding menghadapi risiko politik.
Kelima, Orde Baru meninggalkan warisan birokratisasi ilmu pengetahuan yang membuat ilmuwan lebih sibuk dengan kepatuhan administratif ketimbang terlibat dalam terobosan kreatif, dan akibatnya Indonesia kehilangan momentum untuk membangun basis riset yang kokoh.
Dengan kondisi seperti itu, ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia tidak pernah benar-benar dijadikan landasan pembangunan jangka panjang. Anggaran riset dan pengembangan tetap rendah, sementara kebijakan industrialisasi lebih banyak berorientasi pada kepentingan jangka pendek serta mudah dipengaruhi oleh kepentingan segelintir elit. Sementara Vietnam mampu menjaga komitmen politiknya untuk menyalurkan anggaran terbatas ke sektor riset yang strategis, Indonesia masih kesulitan menempatkan sains sebagai prioritas.
Warisan politik Orde Baru membuat banyak ilmuwan terjebak dalam struktur yang tidak memberi ruang penuh bagi kebebasan akademik dan independensi riset, dan kondisi ini menjadi hambatan besar dalam mengejar ketertinggalan dari negara-negara yang merdeka di periode yang hampir sama.
Kepemimpinan, ideologi, dan tata kelola negara
Pemimpin visioner menjadi faktor penting dalam perjalanan bangsa. India memiliki tokoh seperti Nehru yang meletakkan dasar demokrasi dan kemudian pemimpin yang berani mendorong industrialisasi. Vietnam memiliki Ho Chi Minh dan para penerus yang konsisten dengan ideologi nasionalisme sosialis. Korea Selatan memiliki Park Chung Hee yang keras namun fokus pada industrialisasi. Tiongkok memiliki Deng Xiaoping yang berani mengubah arah ekonomi tanpa melepaskan ideologi politik.
Indonesia tentu memiliki pemimpin besar seperti Soekarno dan Soeharto. Namun perbedaan yang mencolok adalah konsistensi arah kebijakan. Setelah Reformasi 1998, Indonesia sering mengalami perubahan arah pembangunan seiring pergantian presiden. Hal ini memang bagian dari dinamika demokrasi, tetapi tanpa konsistensi jangka panjang, pembangunan menjadi setengah hati.
Selain itu, tata kelola negara menjadi masalah serius. Korupsi, birokrasi yang berbelit, serta lemahnya penegakan hukum membuat banyak kebijakan kehilangan daya dorong. Di balik itu, ada pula pengaruh kelompok kecil yang mampu menekan atau membelokkan arah kebijakan nasional demi kepentingan ekonomi mereka.
Mereka menjalin hubungan erat dengan kekuatan politik dan birokrasi sehingga mampu menghalangi reformasi yang seharusnya dibutuhkan bangsa. Bahkan pengaruh itu bisa datang dari eksternal negara. Negara lain mungkin juga menghadapi kepentingan oligarki, tetapi mereka berhasil menekan pengaruhnya agar tidak mengganggu kebijakan pembangunan nasional. Indonesia justru masih sering tersandera oleh kepentingan jangka pendek kelompok ini.
Etos sosial dan sikap masyarakat
Kemajuan sebuah bangsa tidak hanya ditentukan oleh kebijakan ekonomi atau strategi politik, tetapi juga oleh etos sosial yang hidup dalam masyarakatnya. Filosofi hidup yang berkembang di tengah rakyat sering kali menjadi energi moral yang menentukan arah perjalanan negara. Dalam hal ini, setiap bangsa yang merdeka di periode hampir sama dengan Indonesia memiliki fondasi kultural yang membentuk pola sikap berbeda dalam menyongsong pembangunan.
India membawa warisan filosofi pluralisme dari Mahatma Gandhi dan semangat demokrasi yang dihidupkan oleh para pemimpin pasca-kemerdekaan. Masyarakatnya memiliki keyakinan mendalam bahwa keberagaman dapat dikelola sebagai kekuatan. Meski masih dihantui oleh persoalan kasta, kemiskinan, dan konflik sektarian, etos sosial India ditandai oleh daya tahan kolektif untuk bertahan dalam keragaman. Hal ini membuat demokrasi India tetap bertahan bahkan di tengah guncangan besar.
Vietnam mewarisi semangat perjuangan kolektif yang kuat dari pengalaman perang panjang melawan kolonialisme Perancis dan agresi Amerika Serikat. Filosofi yang hidup dalam masyarakatnya adalah bahwa penderitaan harus dibayar dengan kerja keras bersama demi masa depan bangsa.
Etos ini yang membuat rakyat Vietnam mampu menerima efisiensi anggaran dan pengorbanan generasi kini demi terciptanya pembangunan jangka panjang. Tidak mengherankan bila Vietnam sanggup menyalurkan tenaga sosialnya untuk mendukung riset dan industrialisasi meski berangkat dari keterbatasan.
Korea Selatan menjadikan etos han dan jeong sebagai fondasi kulturalnya. Han merupakan rasa sakit kolektif akibat penjajahan dan perang, yang kemudian ditransformasikan menjadi dorongan untuk bekerja keras dan membuktikan diri di mata dunia. Jeong adalah ikatan emosional dalam komunitas yang mendorong solidaritas sosial. Kedua nilai ini membuat masyarakat Korea bersedia menanggung kerja keras luar biasa demi membangun negeri, hingga lahir generasi yang siap mengantarkan negaranya menjadi salah satu kekuatan industri dan teknologi global.
Tiongkok memiliki filosofi Confucianism yang menekankan pada harmoni sosial, ketaatan hierarki, dan orientasi pada kepentingan kolektif. Nilai ini, yang sudah berakar sejak berabad-abad, menjadi modal sosial ketika Partai Komunis Tiongkok membangun strategi modernisasi. Rakyat Tiongkok terbiasa menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi, bahkan ketika harus menjalani disiplin ketat atau pengorbanan ekonomi. Etos ini, yang kadang dipandang keras oleh pihak luar, justru menjadi salah satu faktor penting yang memungkinkan Tiongkok bergerak cepat dalam industrialisasi dan kemajuan teknologi.
Di Indonesia, nilai gotong royong dan musyawarah telah lama menjadi bagian dari identitas sosial. Namun, dalam praktiknya, etos ini tidak selalu berhasil diterjemahkan ke dalam semangat kolektif untuk mencapai tujuan nasional. Gotong royong kerap berhenti pada konteks komunitas kecil, tetapi melemah ketika dihadapkan pada kepentingan bersama yang lebih besar. Akibatnya, masyarakat Indonesia sering terjebak dalam orientasi jangka pendek, pragmatisme sehari-hari, dan kerentanan terhadap perpecahan yang ditimbulkan oleh provokasi politik.
Padahal, sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, situasi ini seharusnya menjadi potensi besar. Dalam Islam diajarkan nilai untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, menuntut ilmu sejak lahir hingga liang lahat, dan keyakinan bahwa Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum tersebut berusaha merubah dirinya sendiri. Nilai-nilai keislaman ini selaras dengan semangat kemajuan yang membutuhkan ketekunan, kejujuran, dan disiplin sosial.
Selain itu, Indonesia juga kaya dengan filosofi lokal yang berakar dalam budaya daerah. Di tatar Sunda terdapat nilai silih asah, silih asuh, silih asih yang bermakna saling mengasah pengetahuan, saling mengasuh dalam kebaikan, dan saling mengasihi dalam hubungan sosial. Ada pula semangat sabilulungan yang menekankan kerja sama kolektif untuk mencapai tujuan bersama.
Dari Jawa dikenal falsafah hamemayu hayuning bawana yang berarti memelihara dan memperindah dunia, sebuah prinsip yang menekankan keseimbangan dan tanggung jawab bersama. Dari Bugis-Makassar lahir konsep siri’ na pacce yang berarti kehormatan diri dan solidaritas sosial sebagai pendorong keberanian dan tanggung jawab. Dari Bali ada Tri Hita Karana yang mengajarkan keseimbangan antara hubungan manusia dengan Tuhan, sesama, dan alam. Semua kearifan lokal ini seharusnya dapat memperkuat etos nasional apabila benar-benar dihayati dalam kehidupan sehari-hari.
Namun, kenyataannya pengamalan nilai agama dan budaya sering terbentur oleh arus modernisasi. Generasi sekarang kerap lebih terpengaruh oleh nilai-nilai dari budaya luar yang tidak selalu sesuai dengan kebutuhan bangsa. Budaya instan, hedonisme, dan individualisme mulai menggantikan nilai gotong royong dan pengorbanan untuk kepentingan bersama. Jika negara-negara lain mampu mengelola filosofi hidup mereka menjadi energi pembangunan nasional, Indonesia justru masih berjuang agar nilai agama dan budaya yang luhur tidak tergilas oleh derasnya arus globalisasi.
Perbandingan ini menunjukkan bahwa bangsa-bangsa yang menanjak lebih cepat dari Indonesia memiliki etos sosial yang bertransformasi menjadi energi pembangunan nasional. Filosofi hidup mereka berhasil melahirkan sikap masyarakat yang siap bekerja keras, berkorban, dan mendukung agenda besar negara. Indonesia sebenarnya memiliki modal luar biasa baik dari sisi ajaran agama maupun kearifan lokal, tetapi belum mampu mengubahnya menjadi motor kolektif yang konsisten. Tanpa transformasi etos sosial yang lebih matang, Indonesia akan terus menghadapi kesulitan untuk mengejar negara-negara yang sudah melesat jauh ke depan.
Menuju 100 tahun Indonesia merdeka
Dua puluh tahun ke depan Indonesia akan memasuki usia satu abad kemerdekaan. Perjalanan delapan dekade pertama menunjukkan capaian penting seperti stabilitas politik yang relatif terjaga, pembangunan infrastruktur yang semakin merata, serta peningkatan taraf hidup masyarakat dibanding masa awal kemerdekaan. Namun, perbandingan dengan negara-negara lain yang merdeka pada periode hampir sama menunjukkan bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan mendasar yang belum tuntas diatasi.
Tantangan tersebut meliputi rendahnya tingkat kesejahteraan dibanding potensi sumber daya alam yang dimiliki, lemahnya kualitas pendidikan dan literasi yang membuat sebagian masyarakat rentan terhadap provokasi, birokrasi riset yang membelenggu perkembangan iptek, serta masih kuatnya pengaruh segelintir elite yang menjadi mafia negara dalam mengendalikan kebijakan strategis. Etos sosial masyarakat Indonesia yang seharusnya bisa menjadi motor pembangunan, baik dari nilai keislaman maupun kearifan lokal, belum sepenuhnya mampu bertransformasi menjadi energi kolektif yang konsisten.
Oleh sebab itu, menyongsong satu abad kemerdekaan, bangsa Indonesia memerlukan strategi yang lebih jelas dan pondasi yang lebih kokoh. Pertama, pengelolaan sumber daya alam harus diarahkan pada sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan hanya menguntungkan kelompok tertentu. Kedua, pendidikan harus dibenahi dengan serius agar tidak hanya menghasilkan angka melek huruf, tetapi juga daya kritis, kemandirian berpikir, dan kemampuan adaptasi menghadapi perubahan zaman. Ketiga, riset dan pengembangan ilmu pengetahuan perlu ditempatkan sebagai prioritas nasional dengan anggaran yang memadai serta tata kelola yang bebas dari intervensi politik jangka pendek. Keempat, peneguhan etos sosial berbasis nilai spiritual dan kearifan lokal perlu digalakkan agar masyarakat tidak mudah terombang-ambing oleh budaya instan dan pengaruh luar yang melemahkan solidaritas kebangsaan.
Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menjelang satu abad Indonesia merdeka akan menjadi penentu apakah bangsa ini mampu keluar dari jebakan ketertinggalan. Program pembangunan yang sedang berjalan perlu diarahkan bukan hanya pada proyek fisik, tetapi juga pada penguatan sumber daya manusia dan industrialisasi berbasis riset.
Jika fondasi yang ditanamkan hanya bersifat simbolik dan jangka pendek, Indonesia akan kembali tertatih-tatih menuju cita-cita sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tetapi jika keberanian politik digunakan untuk membongkar dominasi mafia negara, menguatkan komitmen pada riset dan teknologi, serta meneguhkan kembali etos kebersamaan, maka Indonesia memiliki peluang nyata untuk melompat sejajar dengan bangsa-bangsa yang kini lebih maju.
Satu abad Indonesia merdeka bukan sekadar tonggak sejarah, melainkan ujian apakah kemerdekaan yang diperjuangkan dengan darah dan pengorbanan telah benar-benar menghasilkan bangsa yang berdaulat, mandiri, dan bermartabat. Jalan menuju cita-cita itu memang masih panjang dan penuh rintangan, tetapi dengan konsistensi visi, keteguhan moral, dan keberanian untuk melakukan perubahan struktural, Indonesia tetap memiliki kesempatan untuk membuktikan diri sebagai bangsa besar yang tidak hanya dikenal karena jumlah penduduknya, melainkan juga karena kualitas manusianya, kekuatan ilmunya, dan keadilan sosial yang ditegakkannya.
Baca esai lainnya di sini.