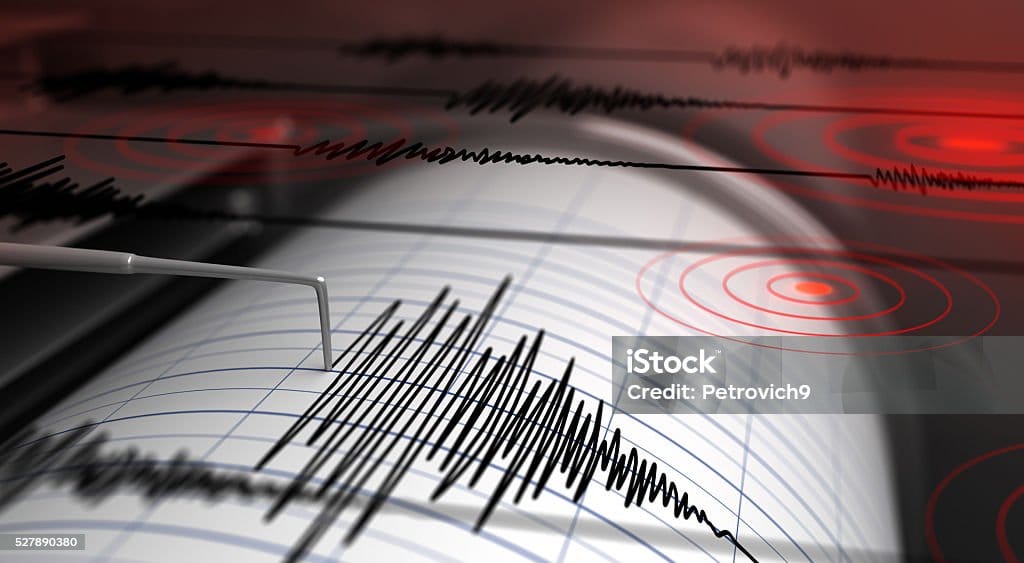Dewasa ini, semakin banyak pelaku usaha—baik berbentuk badan hukum perseroan maupun individu—yang bersengketa dengan pihak perbankan. Data dari berbagai lembaga peradilan menunjukkan bahwa intensitas sengketa antara pelaku usaha dan bank meningkat secara signifikan.
Jenis sengketa yang muncul pun beragam, mulai dari wanprestasi perjanjian kredit hingga keberatan terhadap pelaksanaan eksekusi jaminan, terutama yang berkaitan dengan tanah dan bangunan. Fenomena ini tidak lepas dari dinamika ekonomi nasional pasca-Pandemi Covid-19.
Residu krisis, kebijakan efisiensi pemerintah, dan ketidakpastian pasar telah menyebabkan banyak pelaku usaha gagal memenuhi kewajibannya terhadap fasilitas kredit yang diperoleh dari bank. Ketika utang macet terjadi, mekanisme hukum kredit beralih pada instrumen jaminan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (UUHT).
Pasal 6 UUHT memberikan hak kepada kreditur untuk menjual objek jaminan melalui pelelangan umum apabila debitur wanprestasi. Ketentuan teknis mengenai pelaksanaan lelang ini kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.
Salah satu sumber sengketa yang paling sering muncul dalam praktik ialah penetapan nilai limit lelang, yaitu harga minimal suatu objek jaminan sebelum dilelang. Di sinilah kepentingan antara kreditur dan debitur kerap berbenturan.
Kreditur cenderung menetapkan nilai limit serendah mungkin agar objek jaminan cepat terjual dan piutang segera tertutup. Sebaliknya, debitur berkepentingan agar nilai limit ditetapkan setinggi mungkin demi meminimalisasi kerugian atas hilangnya aset yang dijaminkan.
Idealnya, penentuan nilai limit harus dilakukan secara objektif, profesional, dan akuntabel. Namun, fakta yuridis menunjukkan sebaliknya. Berdasarkan Pasal 57 huruf a PMK 122/2023, hanya objek jaminan dengan nilai di atas Rp10 miliar yang wajib dinilai oleh penilai independen bersertifikat. Sedangkan untuk objek di bawah Rp10 miliar, penetapan nilai limit cukup dilakukan oleh penaksir internal pihak kreditur. Celah hukum inilah yang membuka peluang terjadinya ketimpangan dan penyalahgunaan kewenangan.
Ketidakadilan struktural dan dampaknya
Dalam praktiknya, banyak penaksir internal yang tidak memiliki kompetensi maupun sertifikasi profesional untuk melakukan taksiran nilai pasar secara objektif. Akibatnya, nilai limit sering kali ditetapkan jauh di bawah harga pasar yang wajar. Kondisi ini jelas merugikan debitur, terutama jika hasil penjualan lelang tidak menutupi seluruh utang, sehingga debitur tetap menanggung sisa kewajiban. Ibarat pepatah lama, sudah jatuh tertimpa tangga pula. Aset hilang, utang belum juga lunas.
Menurut hemat penulis, di sinilah letak ketidakadilan struktural dalam sistem hukum kita. Negara melalui regulasinya langsung melegitimasi praktik yang berpotensi merampas hak ekonomi warga negara dengan cara yang “sah secara hukum”, namun tidak “adil secara moral”. Peraturan tersebut menempatkan perlindungan hukum hanya pada kelompok bermodal besar—baik kreditur maupun debitur dengan jaminan di atas Rp10 miliar—sementara debitur kecil dibiarkan bergantung pada kebijakan sepihak kreditur.
Apabila nilai pasar wajar suatu objek senilai Rp3 miliar, tapi oleh penaksir internal ditetapkan hanya Rp1,5 miliar; maka separuh nilai ekonomi dari aset debitur telah “hilang” secara legal. Apakah hal ini sah menurut hukum positif? Jawabannya: sah.
Namun, apakah adil secara substansial? Tentu tidak. Inilah bentuk ketidakadilan yang diciptakan oleh struktur dan substansi hukum itu sendiri.
Bahkan, ketika debitur menggugat ke pengadilan, kemungkinan besar gugatan tersebut akan berakhir dengan kekalahan. Hal ini disebabkan kecenderungan sebagian hakim kita yang masih berpegang secara kaku pada teks undang-undang, seolah-olah pengadilan hanyalah “corong” peraturan, bukan penjaga nurani keadilan.
Padahal, hakim sejatinya adalah corong kebenaran dan keadilan, bukan sekadar penyambung lidah norma formalistik. Hakim seharusnya menggali konteks sosial, ekonomi, dan moral dari setiap perkara yang dihadapinya agar putusan yang lahir tidak hanya benar secara hukum, tetapi juga adil secara hakiki.
Kehilangan nilai ekonomis dari suatu benda milik pribadi sejatinya merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Pasal 17 Universal Declaration of Human Rights serta Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kepemilikan pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh dirampas secara sewenang-wenang oleh siapa pun.
Oleh karenanya, pengambilan manfaat ekonomi dari hak milik seseorang secara tidak kompeten dan tanpa pertanggungjawaban adalah bentuk nyata pelanggaran hak asasi manusia dalam dimensi ekonomi. Negara, melalui peraturan lelang yang ada saat ini, justru terlibat secara tidak langsung dalam memfasilitasi pelanggaran hak tersebut.
Keadilan yang tidak merata dalam penetapan nilai limit lelang adalah bentuk nyata dari kegagalan negara menghadirkan hukum yang memihak pada rakyat kecil. Sudah saatnya regulasi lelang ditinjau ulang dengan semangat keadilan substantif, agar hukum tidak lagi menjadi alat produksi ketidakadilan, melainkan menjadi instrumen penegak martabat manusia dan keseimbangan sosial-ekonomi di negeri ini.
Revisi substansial
Sebagai langkah perbaikan, penulis mengusulkan perlunya revisi substansial terhadap mekanisme penetapan nilai limit. Pertama, penghapusan peran penaksir internal sepenuhnya agar seluruh proses penilaian dilakukan oleh penilai independen bersertifikat yang memiliki keahlian dan tanggung jawab profesional. Kedua, perlu diatur mekanisme mediasi nilai limit apabila debitur memiliki penilaian tersendiri.
Sebagai solusi sementara, bila penjual atau kreditur menetapkan nilai limit Rp1,5 miliar sedangkan penilai debitur menyimpulkan nilai wajar Rp3 miliar, maka penentuan nilai limit setidaknya dapat mengambil nilai rata-rata, yaitu Rp2,25 miliar, guna meminimalisasi kerugian debitur sembari menunggu penyelesaian sengketa yang permanen.
Namun, solusi tersebut hanyalah langkah reaktif. Yang lebih penting adalah evaluasi mendalam oleh pemerintah terhadap keseluruhan tata kelola lelang hak tanggungan, dengan melibatkan pemangku kepentingan seperti praktisi hukum, asosiasi penilai, akademisi, dan lembaga perlindungan konsumen.
Hanya dengan pendekatan sistemik dan berkeadilanlah hukum dapat berfungsi sebagai pelindung, bukan pelaku ketidakadilan—dan negara benar-benar hadir untuk menjamin hak ekonomi setiap warga negaranya tanpa pandang nilai aset atau besar kecilnya suatu modal. [*]