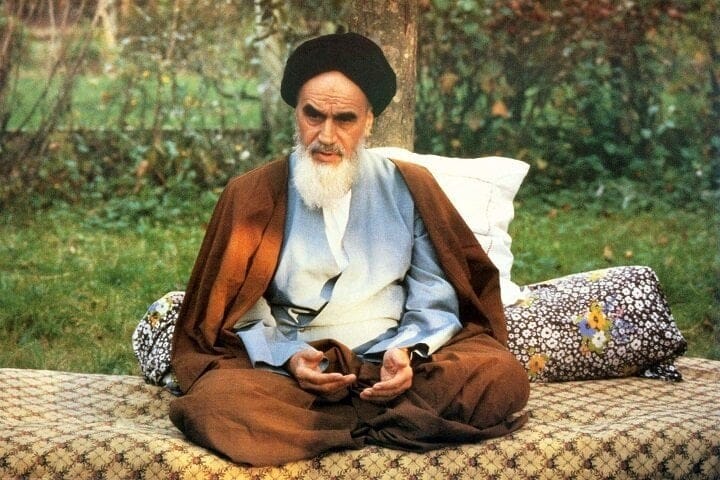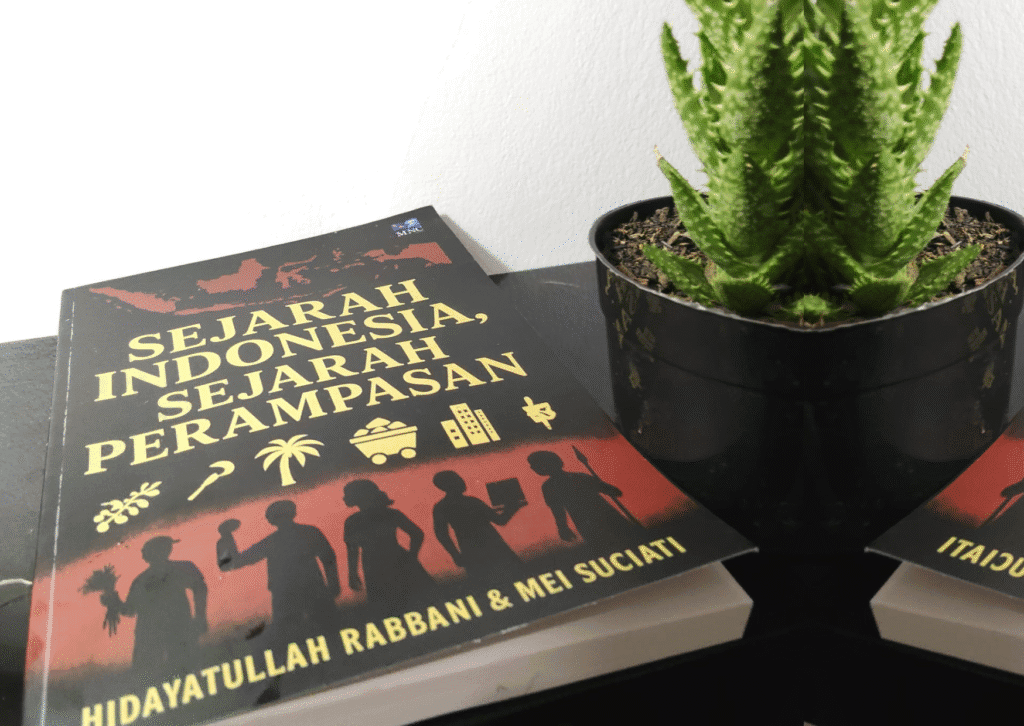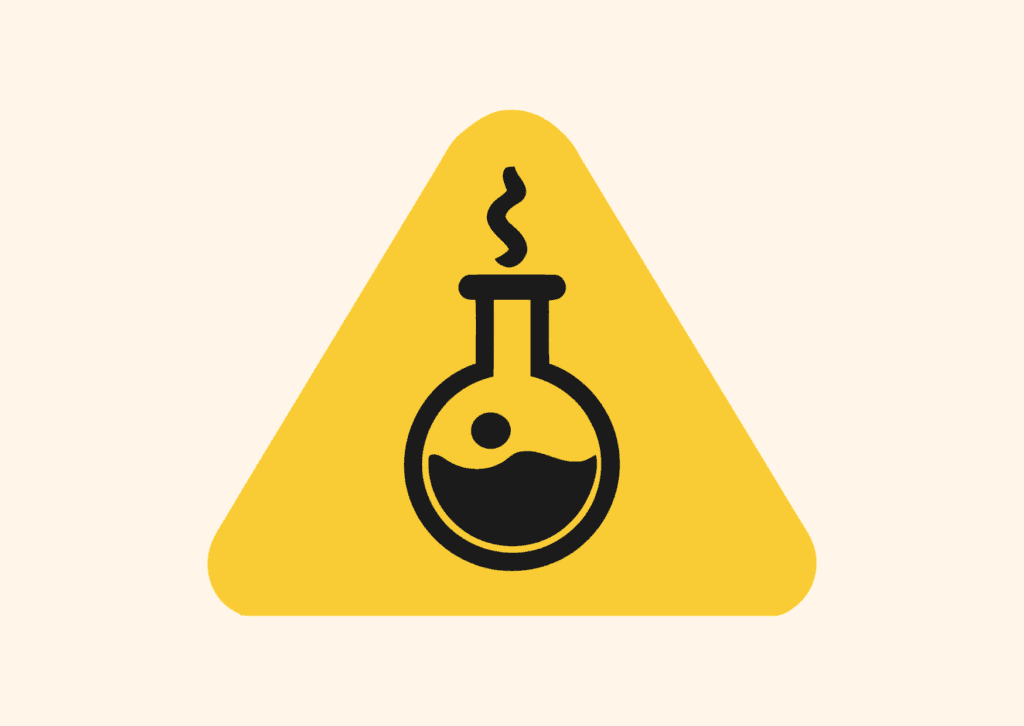Saya mengidentifikasi dua tren politisasi hoaks yang terjadi pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam buku yang diterbitkan pada 2024 lalu. Pertama, produksi hoaks secara terorganisir dan sistematis. Aktor-aktor politik, mulai dari elit hingga buzzer yang dibayar, merancang dan menyebarkan konten hoaks untuk membingkai narasi, menyerang lawan politik, menciptakan polarisasi, dan mengalihkan perhatian publik dari isu-isu krusial.
Di sisi yang lain, politik pelabelan hoaks terhadap suatu informasi bisa datang dari pihak berkuasa sebagai bentuk counter-narrative untuk mendiskreditkan suara yang tidak menguntungkan. Proses menentukan “hoaks” menjadi arena pertarungan kekuasaan, di mana otoritas kebenaran diperebutkan.
Politik pelabelan ini dapat mengancam kebebasan berekspresi, karena kritik yang sah justru dapat dibungkam dengan dalih memerangi hoaks, sehingga memperkuat posisi kelompok dominan.
Rupanya, pola politik pelabelan hoaks ini kembali berulang di tengah kepresidenan Prabowo Subianto yang selalu diwarnai oleh rangkaian demonstrasi berkelanjutan yang berujung pada krisis kepercayaan publik. Artikel saya sebelumnya berargumen bahwa lini masa media sosial berperan sebagai katalisator yang mempercepat dan mempertajam krisis ini dengan mempertontonkan gambaran asimetris antara kehidupan elite penguasa dan kesusahan rakyat.
Pemerintah kemudian memanggil perusahaan platdorm digital untuk membincangkan konten demonstrasi yang dianggap provokatif oleh negara. Alih-alih melakukan perombakan struktural yang menjadi problem laten ketimpangan antara rakyat dan elite yang meningkat tensi, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital lebih memilih mengendalikan algoritma melalui pelbagai perusahaan platform digital.
Respon berbeda dengan judi online
Pemanggilan platform digital ini menunjukkan derajat urgensifitas dalam penyelesaian masalah. Respon Komdigi terhadap situasi politik yang dipengaruhi media sosial ini cukup berbeda dengan responnya menghadapi judi online yang menggerus perekonomian nasional dengan transaksinya yang mencapai ratusan hingga ribuan triliun rupiah.
Meutya Hafid menyebut Pemerintahan Prabowo menjadikan pemberantasan judi online sebagai salah satu permasalahan utama yang akan diselesaikan. Oleh karena itu, Komdigi menginterupsi algoritma di pelbagai platform dengan bersurat agar platform digital menghapus ribuan kata kunci terkait judi online.
Namun, sependek penelusuran, belum ditemukan pemberitaan yang mengabarkan negara melalui berbagai perangkatnya memanggil platform digital berkenaan dengan sirkulasi iklan dan situs judi online di Indonesia. Meski, Meutya Hafid menyebut judi online telah berkembang menjadi krisis nasional.
Pemanggilan platform digital oleh negara sebenarnya bukan hal yang tabu dalam konteks demokrasi. Kita dapat menemukan bagaimana para CEO Meta, Tiktok, atau X dihujani pertanyaan oleh Kongres Amerika Serikat mengenai isu akuntabilitas platform, risiko sensor berlebihan, atau pemengaruh politik melalui penyebaran disinformasi dan manipulasi.
Pemanggilan itu sendiri dapat dilihat sebagai bentuk perimbangan kekuatan antara negara dan platform digital. Sebab, menurut Taylor Owen, gelombang teknologi digital telah melahirkan kekuatan baru yang mampu mengambil alih atau menantang fungsi-fungsi inti negara modern, seperti keamanan, diplomasi, keuangan, pemberitaan, bantuan kemanusiaan.
Namun, kebijakan digital Indonesia masih menunjukkan tren terpolitisasi, sama seperti yang Ross Tapsell khawatirkan. Ia melihat politisasi penegakan hukum penyebaran “hoax” di Indonesia meningkat tajam pada periode pemilihan umum 2018–2019 lalu.
Di tengah tensi tinggi masyarakat, pemanggilan ini berpotensi kontra-produktif karena justru dapat meningkatkan prasangka dan kemarahan publik. Respons negara dalam mengendalikan algoritma yang terlihat dari kontrasnya pendekatan, terhadap unjuk rasa dan judi online, mengonfirmasi kekhawatiran akan politisasi kebijakan digital.
Alih-alih menjadi instrumen netral untuk menjaga ruang digital yang sehat, intervensi algoritma justru berisiko menjadi alat politik untuk membingkai narasi dan meredam kritik di tengah krisis kepercayaan publik.