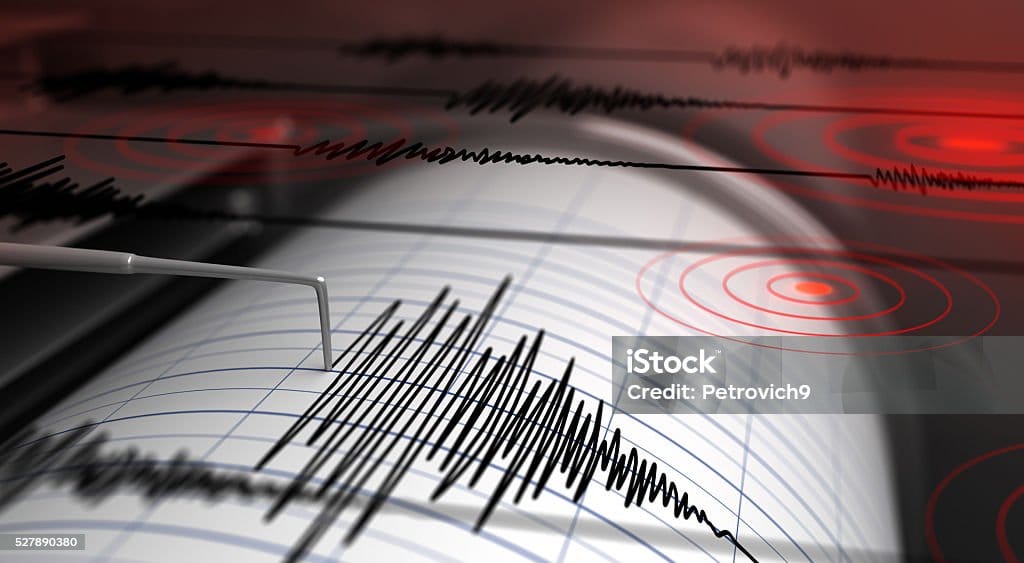Dalam tiga tahun terakhir, Kota Balikpapan menjadi salah satu wilayah dengan jumlah sengketa pertanahan tertinggi di Kalimantan Timur. Berdasarkan data Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, hingga akhir tahun 2023 tercatat 95 kasus pertanahan di Balikpapan dari total 165 kasus di seluruh provinsi.
Angka ini menempatkan Balikpapan sebagai kota dengan intensitas konflik agraria paling tinggi di kawasan tersebut. Ironisnya, situasi ini terjadi di tengah upaya pemerintah mempercepat pembangunan dan memperluas investasi pasca penetapan wilayah Kalimantan Timur sebagai lokasi Ibu Kota Negara (IKN) baru.
Sebagai advokat yang menangani perkara di lapangan, saya melihat masalah pertanahan di Balikpapan tidak berhenti pada tumpang tindih sertifikat atau sengketa batas. Ia adalah cerminan dari kerusakan sistemik dalam administrasi pertanahan dan tata kelola negara.
Banyak kasus berakar pada ketidaksinkronan data antar-instansi, pemalsuan alas hak, dan lemahnya pengawasan atas penerbitan sertifikat. Namun lebih dalam dari itu, persoalan ini lahir dari disfungsi kewenangan pemerintah dan tertutupnya akses publik terhadap proses hukum yang seharusnya transparan.
Kasus di Kelurahan Sumber Rejo menjadi gambaran yang jelas. Warga yang telah menempati lahan sejak 1950-an tiba-tiba diklaim menempati tanah milik Kodam VI Mulawarman. Hal serupa dialami Marjiarti yang menghadapi ancaman pembongkaran rumah di atas lahan yang telah ia tempati lebih dari empat dekade. Bukti hibah dan pembayaran pajak yang sah diabaikan begitu saja.
Kasus-kasus semacam ini hanya sebagian dari yang saya tangani; sebagian besar lainnya tidak pernah terekspos oleh media arus utama. Polanya serupa: klaim sepihak, pemalsuan dokumen, dan lemahnya tanggung jawab pemerintah terhadap praktik mafia tanah yang memanfaatkan birokrasi yang tidak tertib.
Celah memproduksi legalitas buatan
Penyebab utama dari kekacauan ini adalah lemahnya integrasi data pertanahan nasional. Satu bidang tanah bisa memiliki dua bahkan tiga sertifikat dengan dasar hukum yang berbeda.
Hal ini terjadi karena lembaga-lembaga yang mengelola tanah—seperti ATR/BPN, pemerintah daerah, kementerian sektoral, hingga lembaga militer—masing-masing memiliki sistem arsip dan peta sendiri yang tidak saling terhubung. Celah ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang memiliki uang dan akses kekuasaan untuk memproduksi legalitas buatan.
Negara kehilangan kendali atas fungsi pengawasan. Pejabat yang seharusnya menjadi pelindung kepastian hukum justru menjadi pengelola kekuasaan administratif yang dapat dimanipulasi. Ketika verifikasi administratif lebih penting daripada kebenaran sosial, maka hukum berubah menjadi alat pembenaran, bukan alat keadilan.
Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960 menegaskan bahwa tanah dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun dalam praktiknya, penguasaan itu sering disalahartikan sebagai hak untuk mengambil alih, bukan kewajiban untuk melindungi. Negara yang seharusnya hadir untuk menata justru menjadi pihak yang memperumit. Birokrasi pertanahan kini menyerupai labirin, di mana rakyat kecil terjebak tanpa jalan keluar.
Masalah semakin rumit ketika sengketa melibatkan warga berhadapan dengan korporasi besar atau individu yang memiliki kekuatan ekonomi-politik yang besar. Dalam situasi seperti itu, seluruh mekanisme hukum melalui ATR/BPN maupun jalur pengadilan seolah tertutup rapat.
Tidak ada keterbukaan informasi mengapa satu lahan bisa memiliki dua sertifikat. Tidak ada akuntabilitas dalam proses verifikasi. Dalam peradilan, hakim sering kali hanya memeriksa keabsahan dokumen tanpa mempertimbangkan kebenaran penguasaan riil di lapangan. Penguasaan turun-temurun, pembayaran pajak, dan pengakuan sosial sering diabaikan.
Pelanggaran HAM pertanahan
Peradilan kita kerap berfungsi sebagai validator dokumen, bukan penjaga keadilan substantif. Akibatnya, pihak yang memiliki dokumen lebih kuat—sering kali berarti pihak yang lebih berkuasa—akan selalu menang. Keadilan terasa jauh, padahal warga sudah berdiri di depan pintu pengadilan.
Kondisi ini bukan sekadar pelanggaran administratif, tetapi pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 menjamin hak setiap warga negara untuk memiliki dan mempertahankan harta miliknya. Namun di lapangan, banyak warga kehilangan hak tersebut karena kekeliruan atau manipulasi negara sendiri.
Penggusuran dilakukan tanpa dialog, tanpa ganti rugi layak, bahkan tanpa kesempatan pembelaan. Kekerasan yang terjadi tidak hanya bersifat fisik, melainkan juga birokratis—lahir dari pena dan tandatangan pejabat.
Dalam wacana terkini, Pemerintah sedang menggulirkan kebijakan Satu Peta Nasional sebagai solusi untuk mengatasi tumpang tindih data pertanahan. Konsepnya penting dan perlu, tetapi implementasinya berpotensi menimbulkan masalah baru jika tidak dijalankan secara transparan, partisipatif, dan akuntabel.
Tanpa keterlibatan masyarakat dan mekanisme koreksi publik, Satu Peta bisa berubah menjadi Satu Kuasa—alat legitimasi baru bagi pemilik modal dan lembaga besar untuk memperkuat penguasaan mereka atas tanah.
Keadilan agraria di Indonesia tidak akan tercapai hanya dengan pembaruan administrasi. Reformasi pertanahan harus dimulai dari perubahan paradigma: tanah bukan sekadar objek hukum, tetapi ruang hidup.
Pemerintah harus membuka seluruh proses pertanahan bagi publik. Setiap penerbitan sertifikat, perubahan status lahan, dan keputusan administratif harus dapat diawasi masyarakat. Audit menyeluruh terhadap sertifikat lama dan alas hak harus dilakukan secara independen, melibatkan lembaga pengawas eksternal serta masyarakat sipil.
Penegakan hukum terhadap pemalsuan dokumen dan penyalahgunaan wewenang harus dijalankan tanpa pandang bulu. Korupsi agraria adalah bentuk pelanggaran hak rakyat yang sama seriusnya dengan korupsi keuangan negara.
Lembaga peradilan pun harus kembali kepada hakikatnya sebagai penjaga keadilan substantif. Dalam perkara pertanahan, hakim tidak boleh berhenti pada teks dokumen, tetapi wajib menggali konteks sosial dan niat baik penguasaan tanah.
Krisis pertanahan di Balikpapan dan di banyak daerah lain adalah cermin dari krisis kepercayaan terhadap negara hukum. Ketika rakyat tidak lagi yakin bahwa hukum dapat melindungi mereka, legitimasi negara sebagai pelindung hak-hak warga ikut runtuh. Hukum yang seharusnya hidup kini terasa mati di tangan birokrasi dan dokumen-dokumen belaka.
Sebagai advokat, saya percaya hukum yang sejati adalah hukum yang hidup bersama rakyat. Ia mendengar, menimbang, dan melindungi. Tanah bukan hanya soal kepemilikan, melainkan juga tentang martabat manusia.
Ketika negara gagal melindungi tanah rakyat, maka ia telah gagal melindungi kemanusiaan itu sendiri. Keadilan terasa begitu jauh, padahal rakyat sudah berada di depan pintu pengadilan. Kita membutuhkan keberanian moral dan kemauan politik untuk mengembalikan hukum kepada tujuan sejatinya: melindungi yang lemah dari kesewenang-wenangan kekuasaan. Tanpa itu, setiap sertifikat, setiap peta, dan setiap keputusan hukum hanya akan menjadi lembaran kosong di atas tanah yang terus berteriak meminta keadilan.
Baca juga: