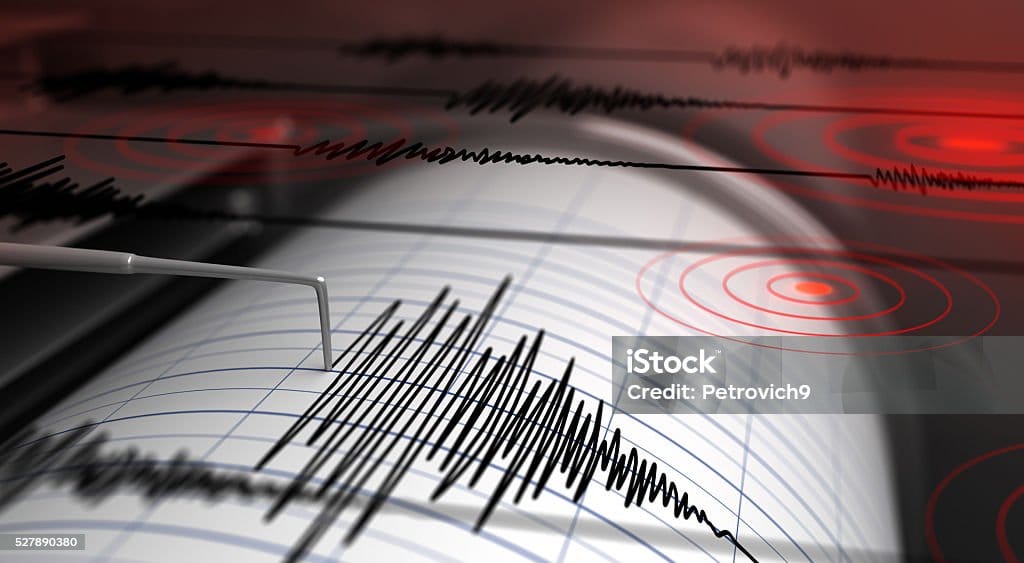Media sosial X ramai tagar #AllEyesOnUnisbaUnpas dan #AllEyesOnBandung setelah aparat kepolisian menembakkan gas air mata dan peluru karet ke arah mahasiswa yang berunjuk rasa di sekitar kampus pada Selasa, 2 September 2025, dini hari. Mahasiswa Unisba dan Unpas Bandung bahkan mendapati asap gas air mata sampai ke dalam area kampus.
Di media, aparat lalu memberi penjelasan yang sudah berulang kita dengar: Massa dianggap anarkis, rusuh, dan menjadi ancaman ketertiban umum. Bahkan, dalam pidatonya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa demonstrasi yang berujung kekacauan tidak bisa ditoleransi dan harus ditindak tegas.
Narasi resmi ini tampak lugas, seolah memberi kepastian bahwa negara hadir untuk melindungi publik dari ancaman kerusuhan. Namun, jika diperiksa lebih jauh, ada problem besar yang tersembunyi di balik penyamaan demonstrasi dengan anarkis dan kerusuhan: Negara sedang berupaya mendelegitimasi protes rakyat sekaligus melegitimasi kekerasan aparat.
Istilah “anarkis” di Indonesia memang sudah lama digunakan secara serampangan. Apa pun yang terlihat gaduh, merusak, atau bentrok di jalan segera dilabeli anarkis. Lebih jauh lagi, istilah “anarko” menjadi stempel kriminal yang dilekatkan pada siapa saja yang berpakaian hitam atau membawa simbol tertentu.
Padahal, secara historis, anarkis bukanlah sinonim dari kerusuhan. Anarkisme adalah sebuah ideologi politik yang lahir di Eropa pada abad ke-19. Tokoh seperti Pierre-Joseph Proudhon, Mikhail Bakunin, hingga Emma Goldman merumuskan anarkisme sebagai penolakan terhadap segala bentuk dominasi negara, kapitalisme, dan otoritas sosial yang menindas.
Tujuan anarkisme bukan menciptakan kekacauan, melainkan membayangkan masyarakat egaliter yang mengatur diri secara kolektif tanpa hierarki. Namun demikian, kata anarkis di Indonesia dipreteli maknanya menjadi sekadar sinonim dari rusuh.
“Kerusuhan” jelas berbeda dengan anarkis. Kerusuhan adalah ledakan kekerasan destruktif yang bisa dilakukan siapa pun, mulai dari demonstran, provokator, bisa juga aparat keamanan. Adapun “demonstrasi” lagi-lagi memiliki arti lain, yakni sebuah ekspresi politik yang sah, dilindungi konstitusi, dan merupakan kanal demokratis bagi rakyat untuk menyuarakan tuntutannya.
Menyamakan ketiga istilah ini bukanlah sekadar salah kaprah semantik, tetapi strategi politik. Dengan penyamaan itu, negara mendapat keuntungan. Pertama, aspirasi rakyat yang diekspresikan lewat demonstrasi kehilangan legitimasi. Isu-isu penting, kenaikan harga kebutuhan pokok, ketimpangan sosial, atau kebijakan politik-ekonomi yang memberatkan rakyat, disulap menjadi sekadar gangguan ketertiban umum.
Publik yang seharusnya membicarakan substansi justru disuguhi tontonan visual seperti ban terbakar, kaca pecah, bangunan terbakar, aparat melempar gas air mata dan memukuli massa pemrotes. Kedua, cap “anarkis” memberi alasan bagi negara untuk membenarkan kekerasan terhadap demonstran.
Gas air mata, tembakan senjata, dan penganiayaan aparat, serta penangkapan massal para pemrotes seolah menjadi wajar. Sebab, yang dihadapi aparat dianggap bukan lagi warga negara yang bersuara, melainkan perusuh. Ketiga, narasi ini menanamkan ketakutan di masyarakat luas. Mereka yang mungkin bersimpati terhadap tuntutan protes akhirnya menjauh, khawatir dicap pembuat onar.
Pola berulang yang digunakan negara
Pola semacam ini bukan hal baru. Tahun 1974, gerakan mahasiswa dalam peristiwa Malari dicap makar dan anarkis. Tahun 1998, protes reformasi dibayangi tuduhan provokator, perusuh, bahkan “massa tak dikenal” yang sampai hari ini masih menyisakan misteri.
Gelombang aksi 2019 dalam “Reformasi Dikorupsi” pun dilabeli anarko, sementara protes 2020 menentang Omnibus Law dituduh didanai asing. Narasi negara nyaris selalu sama. Ketika protes rakyat membesar, ia dibingkai sebagai ancaman stabilitas.
Padahal dalam setiap demonstrasi selalu ada alasan riil. Rakyat turun ke jalan bukan karena suka kekacauan, tetapi karena saluran formal aspirasi sering buntu. Parlemen sibuk berkompromi dengan elit, partai politik lebih mementingkan kursi kekuasaan, sementara kebijakan publik terus mengabaikan suara mereka yang paling terdampak.
Demonstrasi, betapapun kerasnya, lahir dari kebutuhan untuk didengar. Di titik inilah negara seharusnya hadir sebagai pendengar, bukan sebagai pemukul.
Alih-alih mendengar, negara justru menggunakan aparat untuk menekan. Pola kriminalisasi demonstrasi ini tidak unik di Indonesia. Amnesty International dalam laporan 2023 mencatat tren global pembatasan protes, termasuk di negara-negara Eropa, dengan alasan keamanan dan stabilitas.
Bedanya, di Indonesia praktik ini terasa lebih kasar karena diwarisi langsung dari kultur politik Orde Baru yang mengutamakan “stabilitas” dengan segala cara. Dalam logika ini, demokrasi dipersempit menjadi sekadar menjaga ketertiban versi penguasa, bukan mendengarkan rakyat.
Ketika aparat menembakkan gas air mata ke arah mahasiswa, itu bukan sekadar tindakan teknis pengendalian massa. Itu adalah pesan politik “negara lebih memilih menaklukkan tubuh rakyat daripada memahami isi kepalanya”. Kata “anarkis” diucapkan bukan untuk menjelaskan, melainkan untuk menutup diskusi. Ia adalah cap yang membungkam.
Di sini penting untuk meluruskan perbedaan “demonstrasi adalah hak, kerusuhan adalah tindak kekerasan, anarkis adalah gagasan politik”. Menyamakan ketiganya berarti menolak memahami substansi. Lebih jauh, itu adalah strategi negara untuk memecah inti tuntutan rakyat.
Dengan cara ini, protes tidak lagi dipandang sebagai koreksi politik, tetapi sekadar ancaman keamanan. Publik pun diarahkan untuk melupakan isu-isu yang sebenarnya, dan hanya mengingat “kerusuhan” sebagai kata kunci.
Label dari negara
Refleksi yang harus diajukan adalah mengapa negara begitu cepat melabeli rakyatnya sendiri? Jawaban paling sederhana adalah karena kekuasaan takut. Demonstrasi adalah tanda bahwa rakyat tidak puas. Semakin besar protes, semakin besar pula ancaman terhadap legitimasi penguasa. Maka, yang dipertaruhkan bukan hanya stabilitas, tetapi juga keberlanjutan status quo elit politik dan ekonomi.
Namun, justru di sinilah kegagalan demokrasi kita terbaca. Demokrasi seharusnya memberi ruang aman bagi rakyat untuk menyuarakan kritik, bukan sebaliknya: menutupnya dengan stigma.
Demokrasi pasca-reformasi, yang dibanggakan sebagai capaian besar bangsa, kini terasa kian jauh dari janji itu. Proses elektoral sekadar menjadi arena bagi elite politik untuk berganti kursi, sementara partisipasi rakyat berhenti pada kotak suara. Begitu rakyat mencoba melampaui itu, jalanan segera dipenuhi barikade, kawat berduri, dan aparat bersenjata.
Maka wajar bila muncul pertanyaan mendasar “masih relevankah demokrasi yang kita jalankan hari ini?”
Jika demokrasi hanya berarti memilih elite setiap lima tahun sekali tanpa ruang koreksi di luar pemilu, bukankah itu sekadar prosedur, bukan substansi? Bukankah demokrasi yang lebih nyata justru kita temukan pada masa sebelum kemerdekaan, ketika para cerdik pandai bangsa berdebat dengan serius merumuskan dasar negara, bukan sekadar memperebutkan kekuasaan?
Pertanyaan ini membawa kita pada renungan yang lebih jauh. Jika negara terus gagal mendengar suara rakyat, jika demokrasi hanya jadi kedok untuk dominasi elite, lalu apa alternatifnya?
Jawabannya mungkin ada pada gagasan yang selama ini sengaja dihindari, bahwa kehidupan bersama bisa dibayangkan tanpa dominasi, tanpa hirarki yang menindas, tanpa aparat yang selalu menjadi ujung tombak kekuasaan. Sebuah masyarakat yang setara, di mana orang-orang saling mengatur diri dengan prinsip kebersamaan, bukan dengan ketakutan.
Mungkin ide itu terdengar mustahil di hadapan realitas politik hari ini. Tetapi justru dengan membayangkannya, kita bisa melihat kegagalan demokrasi kita dengan lebih jernih. Bahwa negara yang terus-menerus melegitimasi kekerasan terhadap rakyatnya sendiri sejatinya telah kehilangan hak moral untuk menyebut dirinya demokratis.
Akhirnya, meluruskan istilah demonstrasi, anarkis, dan kerusuhan bukan sekadar perkara bahasa. Ia adalah upaya untuk mengingatkan bahwa protes rakyat adalah bagian sah dari demokrasi, bukan ancaman yang harus dibungkam.
Negara boleh terus melabeli, tetapi rakyat juga berhak terus mengingatkan bahwa suara mereka tidak bisa dipadamkan dengan kekerasan aparat negara. Justru dalam suara-suara itulah letak demokrasi yang sesungguhnya.