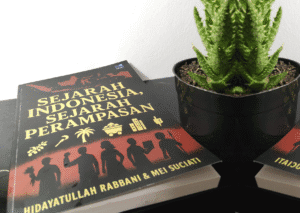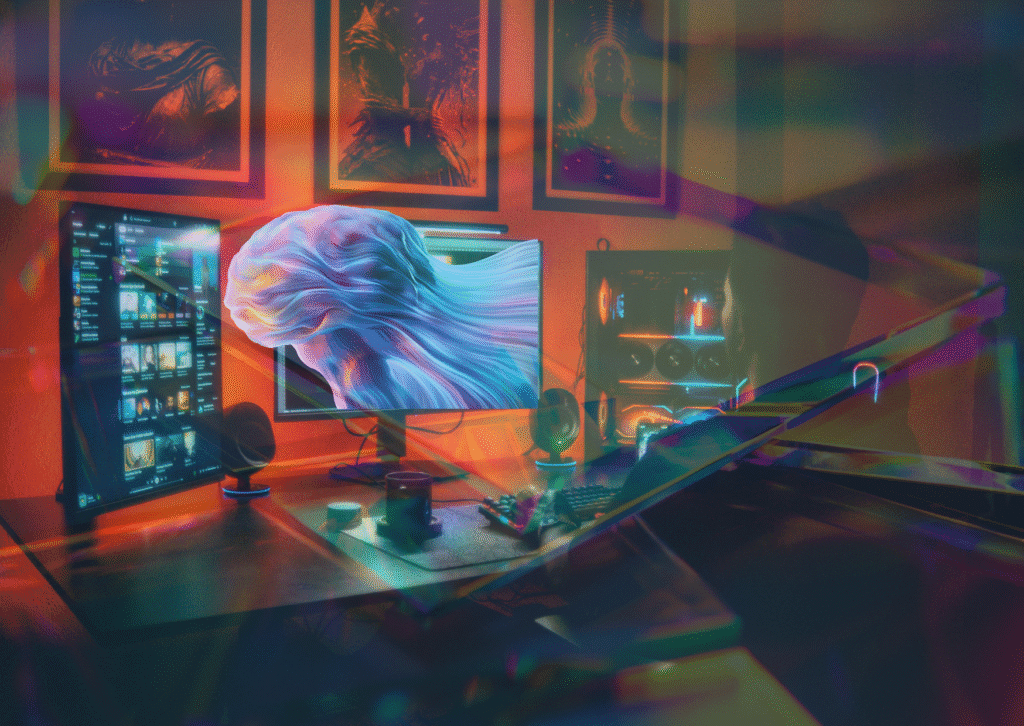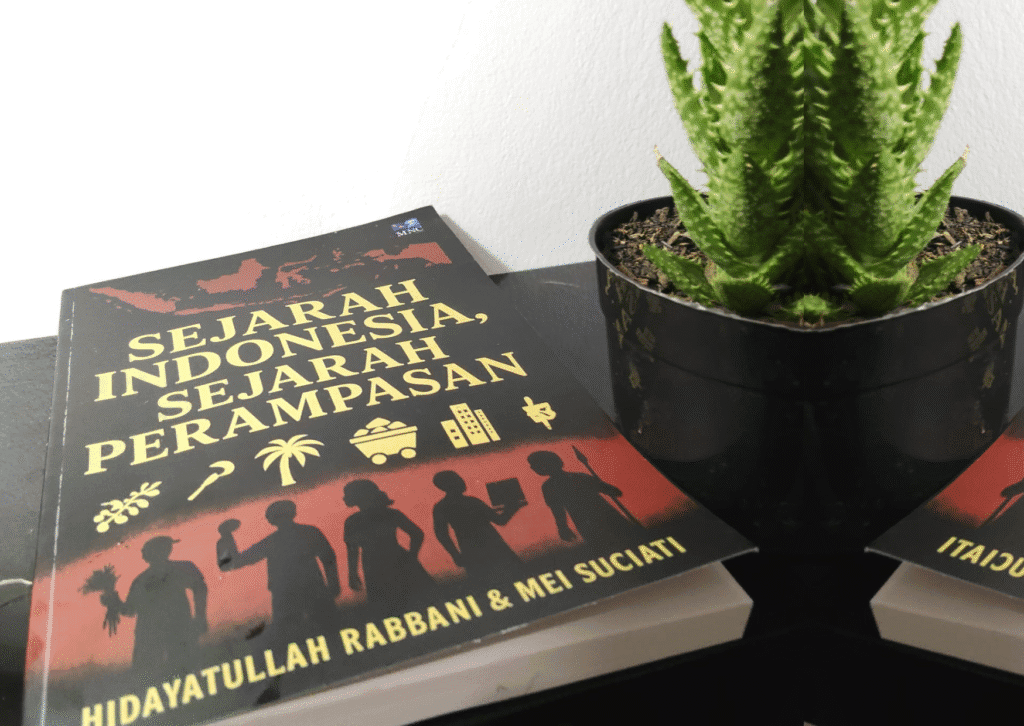Judul Buku: Sejarah Indonesia, Sejarah Perampasan
Penulis: Hidayatullah Rabbani, Mei Suciati
Penerbit: MNC Publishing, 2026
Halaman: 203 halaman
Non-Fiksi
Buku Sejarah Indonesia, Sejarah Perampasan yang ditulis Hidayatullah Rabbani dan Mei Suciati terlihat berambisi menjadi katalog ‘perampasan’ yang terjadi di Indonesia 500 tahun terakhir. Buku ini menyediakan letupan gagasan untuk menggugah kita melihat genosida rakyat Banda oleh Jan Pieterszoon Coen sampai proyek digitalisasi dari perspektif kritis yang tegas. Rentang waktu antara dua fenomena itu dilihat oleh kedua penulis sebagai masa evolusi bentuk-bentuk perampasan.
Aktor perampasan sumber daya di Indonesia ini silih berganti seturut zaman dengan inovasinya masing-masing. Reformasi 1998 yang menjanjikan perbaikan kualitas hidup masyarakat nyatanya tetap dikooptasi elit lama yang dulu menjadi pendukung Orde Baru lewat serangkaian penyesuaian institusional (Robinson dan Hadiz, 2004).
Aktor-aktor yang membawa panji liberalisasi ekonomi dan politik akhirnya terserap dalam jaringan otoritarian yang masih bercokol. Amerika Serikat sebagai promotor demokrasi berposisi ambigu karena mengambil untung dari penanganan illiberal untuk meredam gejolak sosial akibat investasi modal global di Indonesia (Hadiz, 2004).
Buku ini menunjukkan bahasa dan hukum sebagai instrumen untuk menormalisasi atau menyembunyikan perampasan yang menjadi prasyarat pembangunan dan kemajuan, terutama setelah masa Politik Etis. Logika otoritarian tetap ada, namun diselimuti jargon politik, terminologi hukum, atau pemberitaan di masa Indonesia modern.
Pada titik ini, membaca buku Sejarah Perampasan membuat saya merefleksikan relasi antara perampasan sumber daya dan epistemik. Apakah perampasan epistemik mendahului, menyertai, atau mengikuti perampasan? Penulis menempatkan perampasan epistemik sebagai akibat atau datang belakangan setelah perampasan sumber daya dilakukan? Bahkan penulis menyebut pengambilalihan cara hidup dan pengetahuan sebagai bentuk terdalam dari perampasan (hal. 109).
Problematisasi ini mengemukakan klasifikasi peran aktor perampasan dalam tipologi state apparatus dan ideological apparatus. Agaknya buku ini akan lebih signifikan ketika mampu memetakan simbiosis peran antar-kategori tersebut untuk tiap masa atau salah satu masa secara spesifik.
Misalnya, setelah Perang Jawa yang menelan biaya sangat besar berhasil dimenangkan, pemerintah kolonial melaksanakan proyek dekonstruksi hubungan Islam dan Jawa dengan melakukan kajian filologi atas naskah Jawa masa Hindu-Budha untuk mengembalikan imajinasi Jawa yang asli adalah era tersebut, dan Islam menjadi unsur asing yang memicu sifat liar dalam diri orang Jawa hingga memberontak (Afifi, 2019) atau upaya Jawanisasi kolonialisme dengan mengapropiasi elemen kultural yang ada, dari kebaya, tata upacara, panggilan, sampai pelibatan priyayi sebagai aktor tengah yang menjembatani pemerintah kulit putih dengan masyarakat (Meer, 2020).
Kedua penulis dan Cahyo Pamungkas yang memberi pengantar untuk buku ini sama-sama menempatkan bahasa sebagai arena pertarungan kuasa dalam upaya pembangunan dan perampasan. Namun secara temporal, buku ini hadir bersamaan dengan upaya penulisan ulang sejarah Indonesia yang digagas oleh Kementerian Kebudayaan. Dengan kata lain, sejarah Indonesia secara diskursif dari dua buku yang hadir bersamaan itu dapat dipersandingkan.
Sejarah Indonesia adalah arena pertarungan kekuasaan itu sendiri. Buku sejarah Indonesia resmi yang ditulis dapat dilihat sebagai wujud dari high tradition dalam klasifikasi Scott (2012) dan buku Sejarah Perampasan ini menandai low tradition yang menawarkan perspektif historis orang-orang lemah. Penulisan sejarah yang terpublikasi dapat juga menjadi senjata orang-orang lemah, tidak lagi terbatas pada ‘hidden scripts‘ atau kritik dan perlawanan yang tersembunyi dari penguasa dan hanya diketahui anggota komunitas, seperti yang ditulis Scott (1985).
Dalam konteks inilah klaim buku sebagai “senjata orang-orang lemah” menemukan momentumnya. Dengan mempublikasikan analisis yang sistematis, buku ini mentransformasikan hidden transcripts menjadi senjata diskursif yang terbuka. Narasi resmi negara (high tradition) yang seringkali meminggirkan atau meromantisasi kekerasan struktural, kini berhadap-hadapan dengan sebuah low tradition yang terartikulasi dengan jelas, yaitu kronologi panjang perampasan yang justru menjadi fondasi bangunan negara modern. Buku ini mereklamasi lubang epistemik dengan mendefinisikan realitas sejarah dari sudut pandang yang kalah dengan menyediakan argumen historis yang terdokumentasi dan dapat diperdebatkan di ruang publik.
Kehadiran buku ini menjadi sangat relevan justru karena diterbitkan dalam iklim politik di mana narasi besar tentang pembangunan dan kemajuan masih mengaburkan jejak perampasan di dalamnya. Misalnya, debat sekitar UU Cipta Kerja atau ekspansi proyek infrastruktur raksasa dapat dibaca ulang bukan sebagai fenomena baru, melainkan sebagai evolusi kontemporer dari logika yang sama yang pernah diterapkan oleh otoritas di era ratusan tahun lalu.
Dengan kerangka perampasan, buku ini menyediakan lensa untuk mengaitkan ketimpangan masa kini dengan pola historis yang berulang dan beradaptasi. Ia mengajak pembaca untuk selalu bertanya: dalam setiap lompatan modernitas dan digitalisasi hari ini, bentuk perampasan apa yang sedang dinormalisasi melalui bahasa hukum, teknologi, atau janji kesejahteraan?
Pada akhirnya, signifikansi utama buku ini terletak pada upayanya untuk menempatkan pengalaman dan pengetahuan orang-orang lemah sebagai pusat penulisan sejarah. Sejarah yang utuh harus menyertakan jeritan yang tertahan, pengetahuan yang diambilalih, dan sumber daya yang terampas dari mereka yang menjadi korban dalam proses itu. [*]