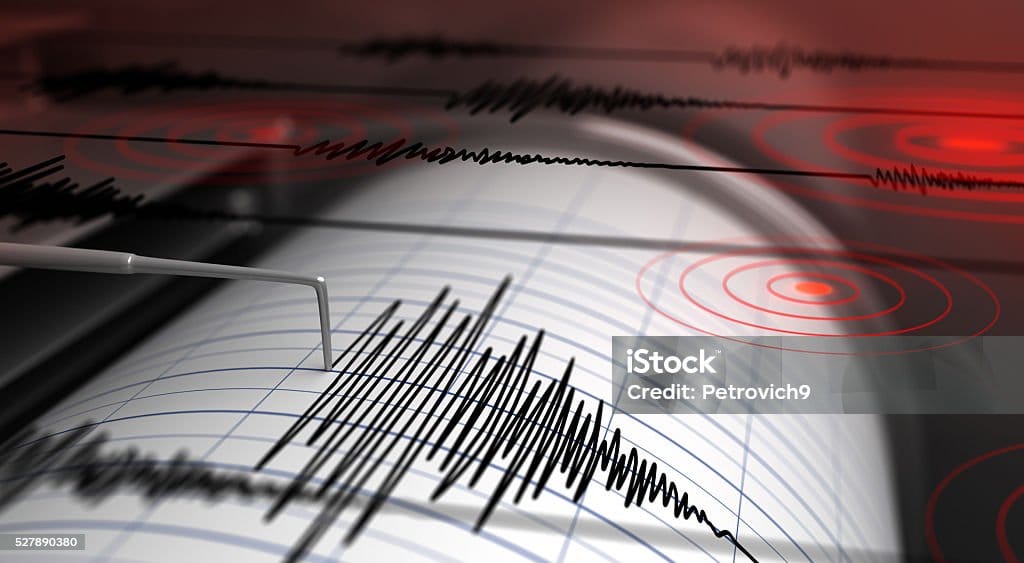Mudik adalah kisah tentang manusia yang terbelah: antara pengembaraan dan kembali pulang. Antara kota yang menjanjikan kesuksesan dan kampung halaman yang dirindukan. Jika pun kantong di perantauan belum memungkinkan untuk ongkos pulang, mimpi mudik akan selalu terselip—dicicil untuk tahun selanjutnya.
Di kota, para perantau—laiknya pekerja lainnya—adalah angka dalam deretan laporan upah minimum. Bahkan, beberapa di antaranya mesti menanggung sial dengan bayaran di bawah upah minimun, terombang ambing-ambing di tengah kerasnya hidup di kota.
Sementara di kampung, mereka adalah subjek yang ditunggu dan diharapkan hidup lebih baik dari keluarganya. Mereka seolah simbol perjuangan di tengah hidup di kampung yang kadang serba sulit.
Seorang buruh bangunan dari Cilacap bisa menjadi pencerita ulung tentang betapa kerasnya Jakarta; sementara kuku-kukunya yang retak menyimpan cerita lain tentang beton yang mengering dan majikan yang tak pernah tepat waktu membayar upah.
Di dalam tasnya mungkin ada dompet dengan kartu ATM, tetapi isinya hanya beberapa juta saja. Sebab, upah hariannya sudah habis untuk biaya kontrakan, hutang rokok dan makan, atau kiriman bulanan keluarga.
Mungkin pikirannya melayang: lebih baik tinggal di kampung halaman. Tapi apakah mungkin? Tanah keluarga bisa jadi tak seberapa sebagai petani gurem.
Dalam konteks ini, mudik adalah pertarungan batin bagi orang-orang yang dimiskinkan: tak mendapat perlindungan kerja, mengais masa depan dengan susah payah, dan tak punya privilese.
Baginya mudik akhirnya menjadi ritual yang membenturkan kepalanya pada pilihan sulit. Pilihan ketika yang miskin terpaksa bermain dalam aturan penguasa dan pengusaha.
Kota yang menjadi magnet
Ada yang menyebut mudik berasal dari kata mulih dilik yang berarti ‘pulang sebentar’ dari bahasa Jawa. Fonema dan istilah mudik lebaran mengemuka kembali pada 1970-an. Saat itu, Jakarta merupakan satu-satunya kota besar di Indonesia.
Orang dari desa beramai-ramai datang ke Jakarta untuk mencari pekerjaan dan mengubah nasib. Untuk yang sudah mendapat pekerjaan, mereka akan mendapatkan jatah libur panjang.
Libur panjang inilah yang dimanfaatkan untuk membawa keluarga besar ke kampung halaman. Momen ini dimanfaatkan juga untuk mengenang sejarah leluhur dengan berziarah.
Di tengah kemajuan teknologi komunikasi, mudik tetap menjadi ritual penting yang dilakukan jutaan orang. Sosiolog Universitas Gadjah Mada Arie Sudjito (2012) menyebut beberapa penyebabnya.
Teknologi tak mampu menggantikan perjumpaan langsung. Ada pula kepercayaan masyarakat yang eksis, yakni mencari berkah dengan bersilaturahmi dengan orangtua, kerabat, dan tetangga di kampung.
Ada pula terapi psikologis. Perantau yang bekerja di kota besar memanfaatkan momen lebaran untuk menyegarkan diri kembali dari rutinitas dan kerasnya hidup di kota.
Perantau yang sudah berkeluarga pun biasanya memanfaatkan mudik sebagai momen untuk mengenalkan asal-usul mereka. Tak sedikit pula yang pulang untuk menunjukkan kesuksesan—versi masing-masing—di perantauan.
Romantisme pulang
Mudik adalah cerita tentang kerinduan, tentang manusia yang terjepit antara masa lalu dan masa depan. Tapi, dalam ratusan hingga ribuan kilometer yang ditempuh pemudik, ada lebih dari sekadar angka statistik.
Ia adalah metafora dari bangsa Indonesia sendiri: desa dan banyak daerah tak pernah benar-benar mewujudkan harapan warganya. Mereka mesti pergi ke tempat yang jauh untuk sekadar bekerja.
Di situlah Indonesia sesungguhnya berada: dalam denyut nadi orang-orang yang bergerak, tercabik janji kesejahteraan, dan tetap berjuang untuk kembali pulang.
Lalu, apa yang tersisa dari mudik selain hidup yang mesti diperjuangkan dan ilusi kota?
Mungkin jawabannya ada pada perempuan tua di pelosok kampung desa yang menunggu. Setiap tahun, ia ingin mendengar cerita tentang “kesuksesan” dan perjuangan anaknya di kota.
Baginya, mungkin momen mudik bukanlah perkara ramainya desa, melainkan jeda di mana waktu berhenti sejenak: anaknya kembali seperti bocah yang lari-lari di kebun, sebelum nasib membawanya pergi lagi.
Pada akhirnya, dengan segala kemegahannya, ternyata kota bukanlah apa-apa tanpa orang-orang dari berbagai desa. Dan desa, akan tetap jadi tempat pulang sebagai cermin tak meratanya pembangunan.
Baca juga: