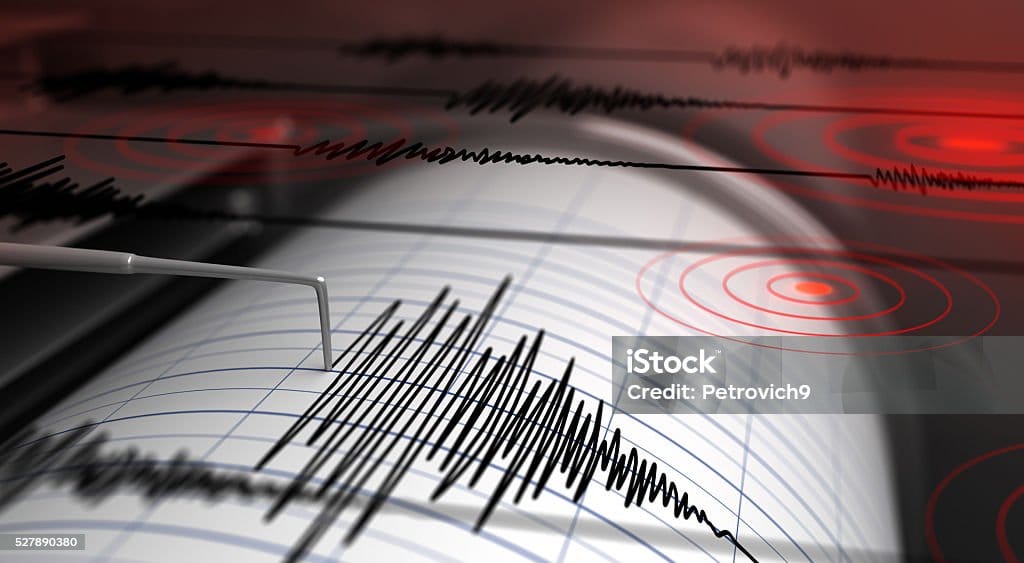Setiap akhir bulan September, masyarakat Indonesia selalu disuguhkan pada sebuah diskusi tentang peristiwa 30 September 1965 (G30S), tragedi politik yang mengubah arah bangsa. Selama puluhan tahun, diskusi ini berkutat pada pertanyaan klasik tentang siapa dalang, siapa korban, dan bagaimana kekuasaan beralih.
Namun, kali ini, saya mencoba menawarkan sudut pandang yang berbeda, dengan menempatkan peristiwa G30S dalam bingkai ‘kontestasi perkembangan sains dan industri global’. Mengapa begitu? Untuk melihat sejarah, kita harus meresapi jiwa zamannya secara luas. Teknologi nuklir, yang pada dekade 1960-an menjadi perhatian utama dunia, menempatkan Indonesia dalam pusaran perebutan kepentingan internasional. Perspektif ini memberi ruang untuk menimbang kembali apakah konflik 1965 murni soal politik dalam negeri atau bagian dari skenario geopolitik global.
Karena itu, pembahasan dalam tulisan ini akan mengajak pembaca untuk melihat ulang jejak sejarah yang sering ditutup oleh narasi resmi. Peristiwa 1965 tidak hanya melibatkan elite politik dalam negeri, tetapi juga terkait dengan perlombaan teknologi antara Barat dan Timur.
Sukarno dengan ambisi nuklirnya menantang tatanan global, sementara blok Barat berusaha mencegah lahirnya kekuatan baru di Asia Tenggara. Situasi ini melahirkan pertanyaan lebih besar, apakah tragedi itu sekadar kudeta, atau sebuah upaya sistematis untuk menggagalkan kemandirian Indonesia? Untuk menjawabnya, mari telusuri perlahan-lahan, mulai dari warisan sejarah militer, jaringan personal, dan intervensi global yang membentuk jalannya peristiwa.
Pendudukan Jepang dan Awal Karir Soeharto, Sebuah Prolog Peristiwa G30S?
Pada awal abad ke-20, Jepang mulai mengirimkan mata-mata ke Hindia Belanda untuk memetakan potensi sumber daya dan jalur perdagangan strategis. Para agen ini tidak hanya bekerja dalam ruang intelijen, tetapi juga membangun jaringan komunitas Jepang melalui perdagangan, perkawinan, hingga sekolah budaya. Kehadiran mereka menandai upaya sistematis Jepang untuk menanamkan akar sosial di tengah masyarakat kolonial yang dikuasai Belanda. Strategi jangka panjang ini memberi landasan bagi penetrasi lebih dalam pada dekade berikutnya. Fakta ini memperlihatkan bagaimana Jepang menyiapkan diri jauh sebelum Perang Dunia II meletus (Cribb & Brown, 1995).
Ketika pendudukan Jepang berlangsung antara 1942–1945, mereka memanfaatkan momentum perang untuk membentuk berbagai organisasi semi-militer di Indonesia. Lembaga seperti PETA dan Heiho didirikan untuk melatih kader pribumi dalam disiplin militer. Selain itu, Jepang mendirikan sekolah militer, sekolah intelijen, dan sekolah polisi yang menanamkan doktrin loyalitas mutlak terhadap atasan. Pendidikan kader semacam ini menyiapkan generasi baru yang kelak berperan penting dalam dinamika politik Indonesia. Jaringan kader inilah yang kemudian menjadi modal politik Soeharto dan kelompok militer lainnya setelah proklamasi kemerdekaan (Anderson, 1972).
Soeharto lahir di desa Kemusuk, dekat Yogyakarta, pada tahun 1921, dan memasuki dunia militer sejak usia muda. Pada 1940, ia masuk KNIL, tentara kolonial Belanda, dan sempat menjadi sersan sebelum Jepang datang (Crouch, 1975). Ketika KNIL bubar setelah Belanda menyerah, Jepang membentuk PETA sebagai wadah militer lokal, dan Soeharto cepat menanjak sebagai komandan kompi (Anderson & McVey, 1971).
Ia dilatih di Bogor sebagai shodancho (komandan peleton) lalu chudancho (komandan kompi), memperlihatkan bakat kepemimpinan sejak awal (Roosa, 2006). Pasca pemberontakan PETA Blitar pada Februari 1945, ia ditempatkan untuk melatih pasukan baru pengganti satuan yang dibubarkan Jepang. Setelah Jepang kalah, PETA dibubarkan, namun para bekas anggotanya segera diintegrasikan ke BKR/TKR setelah proklamasi (Crouch, 1975). Ketika PETA menjadi cikal bakal TKR yang kemudian menjelma menjadi TNI, dan Soeharto sudah berada di dalam arus itu (Anderson & McVey, 1971).
Pada tahun 1946, terdapat peristiwa di mana kelompok yang dipimpin Tan Malaka berusaha melakukan kudeta terhadap pemerintahan kabinet PM Sutan Sjahrir. Peristiwa ini dikenal dengan nama Peristiwa 3 Juli 1946. Saat itu, ibukota Republik sudah pindah ke Yogyakarta, dan dinamika politik masih rapuh di tengah ancaman kembalinya Belanda. Peristiwa ini melibatkan tokoh-tokoh penting, Panglima Besar Jenderal Sudirman, Panglima Divisi IX Mayor Jenderal Sudarsono, serta Letnan Kolonel Soeharto yang kala itu menjabat Komandan Resimen III.
Ben Anderson menulis,
“Pada 1946, di usia 25 tahun, Soeharto sudah menjadi seorang perwira militer yang relatif senior. Pada titik inilah ia dapat dikatakan mulai menapaki karier politiknya. Pada malam 27 Juni 1946, sekelompok milisi bersenjata yang terhubung dengan oposisi politik—gabungan nasionalis pra-perang yang sebagian besar pernah berkolaborasi dengan Jepang—menculik Perdana Menteri Sutan Sjahrir. Mereka menuduhnya lemah menghadapi kembalinya Belanda. Sukarno lalu mengambil kendali langsung pemerintahan dan menuntut agar Sjahrir segera dibebaskan. Para konspirator—didukung secara terbuka oleh Panglima Divisi Yogyakarta dan secara tidak langsung oleh Panglima Besar Sudirman yang berusia 31 tahun—mundur ke markas komando Soeharto. Dari sana mereka mencoba melakukan kudeta pada 3 Juli, yang akhirnya dengan mudah digagalkan. Para tokoh sipil dipenjara sebentar, begitu juga Panglima Divisi Yogyakarta, tetapi Sudirman memastikan tidak ada perwira lain yang terimbas. Kendati demikian, kudeta ini bisa saja mengakhiri karier militer Soeharto, sehingga ia menjadi sangat berhati-hati setelahnya” (Anderson, 2008).
Soeharto dalam biografinya memberi versi berbeda. Ia bercerita,
“Tengah malam Pak Darsono datang lagi ke Markas Resimen dengan membawa rombongan. Rombongan itu ternyata terdiri atas pimpinan politik yang dikeluarkan dari Rumah Tahanan Wirogunan. Pak Darsono memberitahu saya, bahwa beliau telah memperoleh kuasa dari Panglima Besar (Jenderal Sudirman) untuk besok pagi menghadap Presiden Soekarno di Istana, menyampaikan surat yang malam ini akan disiapkan. Batin saya bicara, ‘Wah keterlaluan panglima saya ini, dikira saya tidak mengetahui persoalannya. Saya mau diapusi. Tidak ada jalan lain selain balas ngapusi dia.’ Malam itu juga saya segera memberi informasi ke Istana, apa yang sedang terjadi di Wiyoro dan apa yang akan terjadi besok pagi di Istana. Saya persilakan Pasukan Pengawal Presiden menangkap sendiri Mayor Jenderal Sudarsono di Istana besok pagi dan saya jamin di luar Istana tidak akan terjadi apa-apa” (Soeharto, 1989).
Catatan dari Anderson, seperti melengkapi kisah biografi Soeharto sebagai berikut,
“Pada pagi 3 Juli, kelompok Wijoro berangkat sekitar pukul 06.30 menuju Istana. Para pemimpin politik yang baru dibebaskan dari penjara dinaikkan ke sebuah truk, sementara Sudarsono dan pengawalnya menempati empat mobil. Mereka kaget karena kota Yogyakarta tampak sepi. Tidak ada tanda-tanda massa rakyat, tidak ada Lasjkar Rakyat maupun Hizbullah, dan sudah terlambat memanggil bala bantuan dari markas Soeharto di Wijoro. Saat tiba di Istana, mereka hanya membawa empat belas mantan tahanan yang kelelahan, beberapa prajurit, serta General Sudarsono yang marah. Namun begitu sampai di halaman dalam Istana, rombongan itu langsung disergap Pesindo dan Polisi Militer yang lengkap bersenjata. Pasukan Sudarsono dilucuti tanpa perlawanan”. (Anderson, 2008)
Dalam wawancaranya dengan Anderson pada 1962, Sudarsono mengenang dengan getir bahwa Sudirman bersikap plinplan, menipu, dan tidak pantas bagi seorang satria. Kekecewaan ini dapat dimengerti, karena Sudarsono kemudian dijatuhi hukuman penjara panjang dan diberhentikan dari dinas militer, sedangkan Sudirman tetap Panglima Besar hingga wafat pada 1950. Dalam kekosongan kepemimpinan Divisi, sejumlah perwira mencoba merebut kendali, tetapi akhirnya Sukarno menunjuk Soeharto sebagai penanggung jawab sementara Divisi III. Menariknya, Soeharto menolak untuk menerima jabatan komandan permanen dengan alasan yang tidak pernah dijelaskan secara terang (Anderson, 2008).
Dua tahun kemudian, pada 1948, Soeharto kembali dipanggil menjadi mediator dalam krisis yang hampir menjerumuskan Indonesia ke perang saudara antara kelompok kiri dan lawan-lawannya. Kali ini ia diminta bersama Wikana, gubernur sipil Jawa Tengah dari PKI.
Anderson menulis,
“Wikana mengatakan kepada saya pada 1963 bahwa Soeharto sangat baik, tidak memihak, dan melakukan segala yang bisa ia lakukan untuk mencegah pertumpahan darah. Namun usahanya gagal. Perang saudara singkat tetapi berdarah tetap pecah, dan kubu kiri akhirnya hancur”. (Anderson, 2008)
Dari sini muncul gambaran karakter Soeharto yang khas, selalu menjaga jarak dari risiko langsung namun tetap berada cukup dekat dengan pusat peristiwa. Dengan langkah itu, karier militernya aman, bahkan ia justru makin dipercaya oleh atasan karena dianggap tidak terlibat. Narasi ini membuat sulit menyatakan Soeharto benar-benar terlibat sebagai pelaku kudeta, tetapi jelas ia berada dalam orbit peristiwa itu dan bisa mengambil keuntungan dari situasi tersebut. Teori retrospective self-legitimation dapat dipakai untuk membaca ulang peran Soeharto dalam peristiwa 3 Juli 1946. Dalam narasi biografinya, Soeharto menempatkan diri sebagai perwira yang sigap melaporkan rencana kudeta dan seolah menjadi penyelamat stabilitas negara. Namun, pilihan katanya dengan menyebut apa yang “sedang” terjadi di Wiyoro dan apa yang “akan” terjadi di Istana, justru menunjukkan bahwa ia memiliki pengetahuan mendalam tentang jalannya peristiwa sebelum benar-benar berlangsung.
Hal ini membuka kemungkinan bahwa Soeharto tidak sepenuhnya berada di luar skenario, melainkan bagian dari lingkaran yang mengetahui arah kudeta sejak awal. Dengan cara itu, ia membangun legitimasi diri di kemudian hari, tampil sebagai perwira yang “benar” di hadapan Sukarno sekaligus menghapus potensi keterlibatannya yang lebih dalam. Narasi semacam ini adalah tipe dari strategi retrospective self-legitimation, di mana tokoh politik memoles masa lalunya agar selaras dengan citra yang hendak ia bangun di masa depan (Ricoeur, 2004).
Pelajaran lain yang diambil Soeharto dari peristiwa itu adalah pentingnya membangun jaringan di luar struktur formal. Pada 1946, ia melihat bagaimana kelompok-kelompok militer non-formal bisa mengancam stabilitas negara, tetapi juga bisa dimanfaatkan. Dengan pengalaman itu, Soeharto di tahun-tahun berikutnya membangun jaringan personal di dalam dan luar militer, termasuk dengan pengusaha sipil dan intelijen. Inilah yang menjelaskan kemampuannya mengelola hubungan “dua muka” menjelang G30S, antara Untung-Latief-Supardjo di satu sisi dan Ali Moertopo-Yoga Soegomo di sisi lain. Seperti pada 1946, ia tidak tampil sebagai tokoh paling depan, tetapi sebagai aktor yang paling diuntungkan.
Soeharto dan Jaringan Militernya
Karier militer Soeharto berkembang pesat pasca proklamasi, ia bahkan segera dipercaya menjadi komandan resimen di Yogyakarta. Saat menjadi Panglima Kodam Diponegoro pada 1956 di Jawa Tengah, Soeharto membangun jaringan erat dengan perwira muda yang kelak namanya sering disebut dalam peristiwa 1965. Untung, Latief, Dul Arief, dan Bungkus, semuanya pernah berada di bawah komando Soeharto, baik di Diponegoro maupun operasi Irian (Roosa, 2006). Bahkan, kedekatan personal terlihat ketika Soeharto menghadiri pernikahan Untung, yang kala itu menjadi penerjun pertama di Operasi Trikora. Selain hubungan struktural, ia juga dekat dengan Sarwo Edhie, Pranoto Reksosamodra, dan Ahmad Yani, yang seangkatan dengannya (Crouch, 1975). Jaringan ini menunjukkan bahwa G30S melibatkan nama-nama yang pernah bersama dengan Soeharto dalam karier panjang militernya (Anderson & McVey, 1971).
Selain memiliki hubungan personal dengan nama-nama perwira muda yang nantinya disebut sebagai pelaku peristiwa G30S, Soeharto juga membuat hubungan dengan dua tokoh yang nantinya akan menjadi aktor intelijen terbentuknya Orde Baru, Yoga Soegomo dan Ali Moertopo. Mengutip dari bukunya, Memori Jenderal Yoga, ia adalah lulusan Rikugun Shikan Gakko (Akademi Militer Jepang di Tokyo) yang dikenal mengagumi tokoh-tokoh Nazi Jerman seperti Goebbels, Hermann Göring, dan Erich Rommel. Latar belakang ini membentuk citra Yoga sebagai perwira yang disiplin dan berpandangan keras dalam geopolitik. Setelah menempuh kursus singkat intelijen di Maresfield (MI6), Inggris, berkat dukungan Kolonel Zulkifli Lubis, Yoga kemudian ditempatkan sebagai Asisten I (Intelijen) pada Komando TT-IV/Diponegoro di bawah Kolonel Bachrum (Yoga, 1990).
Pengalaman lapangan Yoga mempertemukannya dengan sejumlah tokoh penting lain. Selama bertugas di Yogyakarta, ia sempat bekerja di bawah Kolonel Latief Hendraningrat, Komandan KMKB Yogyakarta. Salah satu tugasnya adalah menahan Letkol S. Parman, yang dicurigai karena hubungan keluarganya dengan Ir. Sakirman, tokoh PKI yang terlibat dalam pemberontakan Madiun. Hubungan antara Yoga dan S. Parman ini diawali dengan ketegangan politik, yang kelak memberi warna pada peristiwa di 1965.
Yoga juga dipercaya langsung oleh Soeharto ketika menjabat Panglima TT-IV/Diponegoro. Ia ditunjuk sebagai Komandan Resimen Tim Pertempuran (RTP) II dalam operasi militer menumpas PRRI di Sumatera Barat, dengan Kapten Ali Murtopo sebagai Kepala Staf. Dalam operasi tersebut, Yoga kembali berinteraksi dengan perwira muda seperti Letnan Untung, yang pernah berada di bawah komandonya. Ikatan personal ini membentuk jaringan perwira yang kemudian muncul dalam peristiwa G30S.
Saat menjadi Panglima Kostrad di 1965, Soeharto mengirim telegram kepada Yoga yang sedang bertugas di Beograd sebagai Atase Militer. Isinya meminta Yoga segera kembali ke Indonesia untuk menjabat Kepala Intelijen Kostrad. Yoga tiba di Jakarta pada 5 Februari 1965 dan langsung menghadap Soeharto di rumahnya di Jalan H. Agus Salim. Sejak saat itu, ia sering terlibat dalam pembahasan persoalan nasional bersama Panglima Kostrad (Anderson, 2000).
Kemudian Ali Moertopo, salah satu perwira intelijen paling berpengaruh di lingkaran Soeharto. Sama seperti banyak perwira Angkatan Darat generasi awal, ia merupakan lulusan PETA pada masa pendudukan Jepang. Setelah proklamasi kemerdekaan, Ali melanjutkan karier di Tentara Nasional Indonesia dan masuk dalam jaringan Diponegoro, tempat ia pertama kali bekerja langsung di bawah komando Soeharto (Crouch, 1975).
Pada akhir 1950-an, Ali sudah menjadi figur yang dekat dengan dunia intelijen. Ia kerap dilibatkan dalam operasi-operasi keamanan internal, terutama di Jawa Tengah. Dalam operasi militer menumpas PRRI di Sumatera Barat, ia ditunjuk sebagai Kepala Staf Resimen Tim Pertempuran II di bawah komando Yoga Soegomo, sementara Soeharto sendiri saat itu adalah Panglima Divisi Diponegoro (Yoga, 1990). Kedekatan struktural ini membuat Ali menjadi bagian dari lingkaran inti perwira yang sejak lama berada dalam orbit Soeharto.
Hubungan patronase antara Soeharto dan Ali semakin kuat ketika Soeharto menjadi Panglima Kostrad pada awal 1960-an. Ali sering disebut sebagai salah satu perwira yang paling setia dan mampu menerjemahkan keinginan Soeharto ke dalam operasi intelijen. Crouch (1975) menyebut Ali sebagai “arsitek politik intelijen Orde Baru” yang memainkan peran penting dalam operasi kontra-PKI setelah 1965. Kemampuannya mengorganisir jaringan operasi psikologis dan propaganda menjadikannya salah satu figur kunci dalam konsolidasi kekuasaan Soeharto.
Dalam perspektif sejarah politik, Ali Moertopo berperan sebagai perantara antara militer, kelompok sipil, dan kekuatan asing. J. Kristiadi (1999) mencatat bahwa Ali memiliki jaringan komunikasi dengan diplomat Amerika Serikat menjelang dan sesudah G30S, terutama dalam rangka memastikan dukungan terhadap Soeharto.
Peran Ali tidak hanya terbatas pada masa transisi pasca-1965. Ia kemudian menjadi arsitek “Golkarisasi,” yakni upaya membangun partai Golongan Karya sebagai mesin politik Orde Baru. Kemampuannya dalam rekayasa politik elektoral dan propaganda media menempatkannya sebagai salah satu figur paling berpengaruh di balik konsolidasi rezim (Crouch, 1975; Kristiadi, 1999).
Salah satu jejak penting Ali adalah pendirian Centre for Strategic and International Studies (CSIS) pada 1971, yang bukan hanya think tank akademik, tetapi juga sarana untuk membingkai wacana politik sesuai kepentingan Orde Baru (Liddle, 1973). Sebagai penggagas ‘jurnalisme intelijen’(Anderson, 2000), ia tidak hanya menjalankan operasi rahasia tetapi juga menuliskannya dalam bentuk konsep politik seperti Strategi Pembangunan (Moertopo, 1973) dan Demokrasi Pancasila (Moertopo, 1978).
Tulisan-tulisan itu berfungsi sebagai legitimasi ideologis bagi praktik militer dalam mengendalikan politik sipil. Crouch (1975) mencatat bahwa Ali menggunakan propaganda dan operasi psikologis untuk menyingkirkan lawan-lawan politik Soeharto. Dengan cara ini, Ali Moertopo menjadikan tulisan sebagai instrumen untuk menyamarkan praktik intelijen di balik bahasa pembangunan dan stabilitas politik (Crouch, 1975; Liddle, 1973).
Soeharto dan Terbentuknya Jaringan Bisnis
Dalam tugasnya sebagai Panglima Kodam Diponegoro, Soeharto juga dikenal sebagai figur yang membangun jaringan bisnis kuat melalui kedudukannya sebagai Ketua Peperda (Penguasa Perang Daerah) Jawa Tengah. Posisi ini memberinya kewenangan untuk menjalankan kegiatan ekonomi di tengah lemahnya jalur resmi negara, sehingga membuka peluang menjalin kerja sama dengan sejumlah pengusaha Tionghoa lokal Jawa Tengah. Nama-nama seperti Liem Sioe Liong, Oei Tek Young, dan The Kian Seng alias Bob Hasan menjadi mitra dekat Soeharto, yang kelak berperan besar dalam menopang bisnis sekaligus karier politiknya (Crouch, 1975).
Liem Sioe Liong—Sudono Salim, pendiri Salim Grup—saat itu masih pedagang skala menengah, yang mendapatkan proteksi militer dari Soeharto, sehingga bisnisnya bisa berkembang pesat. Nasution sendiri pernah menyinggung persoalan ini. Kepada Brian May, ia mengaku bahwa saat menjabat KSAD, dirinya memerintahkan pemeriksaan atas Soeharto yang terlibat dalam aktivitas ekspor-impor ilegal di Semarang. Soeharto dituduh mengekspor gula ke Singapura dan Hong Kong dengan memanfaatkan pasokan dari Jawa Timur, lalu menukarnya dengan barang-barang lain. Akan tetapi, alih-alih diadili atau dicopot, Soeharto hanya mendapat teguran keras, dan malah membuat Nasution menandatangani perintah agar Soeharto tidak diadili (May, 1978). Mengapa begitu?
Dalam kasus ini, eksistensi Bob Hasan memainkan peran penting. Setelah ayah kandungnya meninggal, Bob Hasan diasuh dan dianggap sebagai anak angkat oleh Gatot Subroto, Deputi KSAD sekaligus salah satu perwira paling berpengaruh di Angkatan Darat pada akhir 1950-an (Tempo, 2001). Status sebagai “anak angkat” memberi Bob Hasan legitimasi sosial dalam lingkaran militer, sehingga ia bukan hanya mitra bisnis biasa, melainkan bagian dari “keluarga besar” tentara. Christopher Barr (1998) mencatat bahwa hubungan Bob Hasan dengan Gatot Subroto berperan penting dalam membangun kemitraan jangka panjang dengan Soeharto. Perlindungan Gatot memastikan bahwa bisnis bersama Soeharto tidak sekadar aman secara ekonomi, tetapi juga terlindungi secara politik.
Bahkan, ketika Nasution mempertimbangkan untuk menyingkirkan Soeharto pada Oktober 1959 akibat kasus penyelundupan di Semarang, status Bob Hasan sebagai anak angkat Gatot membuat keputusan itu jadi lebih kompleks. Alih-alih dijatuhi hukuman, Soeharto dipindahkan ke Seskoad Bandung dan justru dipromosikan menjadi brigadir jenderal (Barr, 1998). Dengan demikian, relasi Soeharto-Bob Hasan tidak bisa dipahami hanya melalui lensa bisnis, melainkan juga patronase berbasis kekerabatan semu (fictive kinship). Hubungan orangtua-anak antara Gatot Subroto dan Bob Hasan memberi dasar simbolis yang lebih kuat bagi kolaborasi mereka. Richard Robison (1986) menekankan bahwa praktik seperti ini bukan hal asing, karena pada masa itu banyak perwira dan pengusaha menggunakan jaringan keluarga nyata maupun semu untuk mengokohkan posisi mereka dalam struktur negara yang rapuh.
Situasi nasional pada akhir 1950-an juga memperkuat basis ekonomi militer. Nasionalisasi perusahaan Belanda pada Desember 1957, akibat kebijakan Belanda terkait Irian Barat (kini seluruh Papua bagian Indonesia), membuka ruang bagi perwira militer untuk menguasai perusahaan-perusahaan vital. Nasution dalam memoarnya menulis bahwa tindakan pengambilalihan itu dilakukan atas dasar pertimbangan keamanan, bukan semata motif ekonomi. Namun, faktanya penguasaan militer terhadap perusahaan-perusahaan Belanda, mulai dari perkapalan, perkebunan, hingga sektor perdagangan besar, menempatkan Angkatan Darat sebagai aktor ekonomi baru di Indonesia (Nasution, 1984). Kondisi inilah yang membuat praktik bisnis militer menjadi hal yang lumrah, dan Soeharto sekadar menjadi salah satu perwira yang paling lihai memanfaatkannya untuk membangun jaringan bisnis-politik yang kelak menopang kekuasaannya.
Richard Robison (1986) menyebut fenomena ini sebagai lahirnya “kapitalis birokratis”, yakni perwira militer yang menguasai aset negara sekaligus memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. Soeharto sendiri, ketika masih memimpin Divisi Diponegoro, semakin memperdalam hubungannya dengan pengusaha Tionghoa seperti Liem Sioe Liong dan Bob Hasan. Pencopotannya dari posisi itu pada 1959 diduga erat kaitannya dengan upaya sejumlah perwira pusat, seperti Jenderal Sunarjo dan Pranoto, untuk menertibkan “ekstremitas” hubungan militer-bisnis. Bahkan, Divisi Diponegoro disebut-sebut terlibat dalam kepemilikan perkebunan eks-Belanda sebelum 1965, yang memperlihatkan kedalaman integrasi militer dalam struktur ekonomi pasca-nasionalisasi (Robison, 1986).
Pada akhir 1950-an, TNI semakin masuk ke bisnis melalui yayasan militer, dan Soeharto adalah salah satu aktor aktif dalam proses itu (Robison, 1986). Kombinasi koneksi bisnis dan intelijen inilah yang memperkuat posisinya, bahkan sebelum ia naik ke puncak politik (Crouch, 1975). Dengan latar belakang ini, mudah dipahami mengapa Orde Baru terbentuk dengan fondasi militer-bisnis yang erat (Robison, 1986).
Jaringan ini semakin menguat ketika Soeharto memimpin Operasi Mandala di Irian Barat pada awal 1960-an. Dalam operasi tersebut, kebutuhan logistik sangat besar, dan Soeharto kembali mengandalkan jaringan bisnisnya untuk mendukung gerakan militer. Setelah G30S 1965, jaringan bisnis ini menjadi pondasi ekonomi rezim. Liem Sioe Liong, Bob Hasan, dan sejumlah pengusaha lain diberi konsesi besar dalam sektor industri, kehutanan, serta perbankan. Dengan cara ini Soeharto memadukan kekuasaan politik-militer dengan kapitalisme patrimonial, mewariskan jaringan oligarki yang menguasai perekonomian Indonesia, di mana loyalitas personal lebih penting daripada regulasi formal (Robison, 1986; Hadiz & Robison, 2004).
Tekanan Geopolitik, Ambisi Nuklir, dan Politik Dalam Negeri
Ketika Jepang kalah perang, pada periode 1945 hingga 1950-an, sebagai negara berideologi fasis mereka diberi sanksi militer oleh blok sekutu yang notabene berideologi liberal dan masuk dalam orbit politik Amerika Serikat yang sedang membangun strategi global. Dalam konteks Perang Dingin, Jepang diposisikan sebagai sekutu utama bagi Washington di Asia. Hal ini selaras dengan Doktrin Truman dan teori domino yang menekankan pencegahan ekspansi komunisme di Asia Tenggara. Amerika melihat Jepang sebagai benteng ekonomi sekaligus basis militer yang strategis. Transformasi Jepang dari kekuatan imperialis menjadi mitra strategis AS berlangsung sangat cepat (Cumings, 1997).
Puncak integrasi Jepang ke dalam sistem keamanan regional terjadi pada 1951 dengan ditandatanganinya Perjanjian Keamanan AS–Jepang. Melalui perjanjian itu, Jepang diarahkan bukan lagi sebagai kekuatan militer ekspansionis, tetapi sebagai pilar ekonomi anti-komunis. Tugas Jepang adalah menjadi mesin pertumbuhan yang dapat menopang stabilitas Asia Timur dan Asia Tenggara. Strategi ini menjadikan Jepang sebagai penyeimbang dalam perang ideologi melawan komunisme di kawasan. Dengan kata lain, Jepang menjadi perpanjangan tangan strategi containment Amerika di Asia (Dower, 1999).
Di saat Jepang diarahkan untuk menjadi negara pengawas komunisme di Asia, negara-negara dunia ketiga di kawasan itu justru berusaha mencari jalannya sendiri untuk menunjukkan kemandirian. Indonesia di bawah Sukarno memandang bahwa teknologi maju, khususnya nuklir, dapat menjadi simbol sekaligus alat untuk menegaskan posisi strategisnya di panggung global. Kesadaran inilah yang kemudian melahirkan langkah awal pembangunan lembaga nuklir nasional.
Setelah melakukan perjalanan kenegaraan ke Tiongkok pada tahun 1956, Sukarno mendapatkan inspirasi mendalam dari keberhasilan model politik yang dijalankan Mao Zedong (Liu, 1997). Baginya, konsep guided democracy atau Demokrasi Terpimpin terbukti mampu mempercepat proses perubahan sosial dan ekonomi di negeri tersebut. Salah satu pencapaian penting yang dikaguminya adalah keberhasilan Tiongkok pada tahap awal dalam mengembangkan teknologi nuklir. Sukarno melihat bahwa hanya dengan sistem kepemimpinan terpusat, negara pascakolonial dapat mengejar ketertinggalan dari kekuatan negara dunia pertama yang disebutnya sebagai old emerging forces (Liu, 1997).
Atas dasar pemikiran itu, ia kemudian menetapkan Demokrasi Terpimpin pada 1959 sebagai jalan politik baru Indonesia. Melalui sistem ini, Sukarno berharap visi menjadikan Indonesia negara besar dan modern dapat segera diwujudkan, tanpa harus bergantung sepenuhnya pada pola liberal yang dianggap terlalu lambat (Zhou, 2019). Sukarno membentuk hubungan poros hubungan Jakarta-Peking dalam konteks kerjasama iptek. Namun narasi yang dibuat oleh blok barat, hubungan tersebut merupakan hubungan kerjasama politik untuk menguatkan pengaruh komunis di wilayah Asia (Liu, 1997).
Langkah awal Indonesia dalam mengembangkan teknologi nuklir dimulai pada 1954 dengan berdirinya Lembaga Tenaga Atom, cikal bakal Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN). Pendirian lembaga ini mencerminkan kesadaran pemerintah bahwa energi nuklir bukan sekadar instrumen militer, tetapi juga simbol modernitas dan kemandirian bangsa (Zhou, 2019). Dalam konteks Perang Dingin, negara-negara berkembang berusaha mengejar teknologi tinggi sebagai cara mengurangi ketergantungan pada Barat. Tidak mengherankan bila Indonesia menempatkan energi atom dalam kerangka strategi pembangunan nasional. Langkah ini menandai bahwa sejak awal, ambisi nuklir Indonesia tidak bisa dilepaskan dari aspirasi politik internasional dan kebutuhan domestik (Zhou, 2019).
Ketika Tiongkok berhasil meledakkan bom nuklir pada Oktober 1964, Sukarno segera merespons dengan pernyataan yang menggema di dalam maupun luar negeri. Ia menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh hanya menjadi penonton dalam perlombaan senjata dunia. Sukarno bahkan berjanji suatu saat bangsa Indonesia akan memiliki bom atom sendiri. Ucapan yang bersifat politis, tetapi juga merefleksikan ambisi menempatkan Indonesia sejajar dengan kekuatan global. Dengan retorika itu, Sukarno ingin menegaskan peran Indonesia sebagai negara yang berdaulat dan anti-dominasi asing (Kahin, 1999).
Ambisi tersebut tidak berhenti pada tataran wacana, melainkan diwujudkan melalui langkah-langkah diplomasi dan kerja sama internasional. Pada September 1965, delegasi Indonesia dikirim untuk mengunjungi fasilitas nuklir di Beijing. Walaupun program nuklir Tiongkok saat itu masih jauh di bawah Uni Soviet dan Amerika Serikat, kunjungan tersebut menunjukkan kedekatan politik kedua negara. Indonesia ingin belajar sekaligus menunjukkan bahwa ia memiliki mitra strategis di luar blok Barat. Hal ini sekaligus memperkuat posisi Sukarno dalam memainkan politik poros Jakarta-Peking-Moskow-Pyongyang melawan hegemoni Barat di Asia (Crouch, 1975).
Memasuki 1960-an, Jepang menghadapi kebutuhan mendesak untuk mengakses bahan baku dari Asia Tenggara, khususnya Indonesia, guna menopang pertumbuhan industrinya. Namun, kebutuhan tersebut terhalang oleh sikap politik Presiden Sukarno yang anti-Barat dan anti kolonialisme. Kondisi ini menimbulkan hambatan besar bagi Jepang yang sudah masuk ke orbit ekonomi Amerika Serikat. Jepang pun harus menunggu momentum perubahan politik di Indonesia yang memungkinkan akses sumber daya kembali terbuka. Situasi ini memperlihatkan betapa erat kaitannya kepentingan ekonomi Jepang dengan dinamika politik dalam negeri Indonesia (Yoshihara, 1988).
Informasi Intelijen dan Posisi Soeharto pada 30 September
Peran intelijen menjadi salah satu aspek paling krusial dalam memahami dinamika menjelang peristiwa 30 September 1965. Salah satu episode penting terjadi pada Agustus 1965, ketika Yoga melapor kepada atasannya, Mayjen S. Parman, tentang kemungkinan adanya penculikan. Percakapan itu terekam dalam Memori Jenderal Yoga:
Yoga: “Ada informasi mengenai kemungkinan akan terjadi penculikan, Pak.”
Parman: “Kamu punya bukti-bukti?”
Yoga: “Belum ada, Pak. Ini baru informasi.”
Parman menilai informasi itu masih bernilai rendah. Tapi ia minta Yoga untuk terus mengikutinya dan jangan diabaikan. Info tersebut memang belum jelas, siapa akan menculik siapa. Episode ini memperlihatkan bahwa intelijen Angkatan Darat sebenarnya sudah menangkap gelagat mencurigakan sebelum meletusnya G30S. Namun, laporan itu tidak ditindaklanjuti secara serius karena dianggap terlalu lemah. Di sinilah letak ambiguitas narasi sejarahnya, apakah laporan Yoga benar-benar minim bukti padahal dia intelijen terlatih dari Inggris atau sebenarnya narasi laporannya dibuat sesederhana mungkin sehingga terlihat kurang serius? Kemudian hal ini menjadi alibi buat Yoga jika dia sebenarnya telah mengabari pihak Angkatan Darat satu bulan sebelumnya namun karena tidak ditanggapi, menjadi kesalahan pihak Angkatan Darat sendirilah peristiwa 30 September lahir.
Jika laporan itu bisa sampai ke Parman, kemungkinan besar Soeharto juga sudah mengetahuinya secara informal dari Yoga, karena pada dasarnya Yoga adalah intelijen untuk Kostrad. Anderson dan McVey (1971) menekankan bahwa kesiapan Soeharto pada malam 1 Oktober 1965 tidak bisa dilepaskan dari akses informasi intelijen. Roosa (2006) juga menegaskan bahwa Soeharto tampak paling siap menghadapi situasi dibanding jenderal lain yang justru diculik. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah Soeharto sekadar penerima laporan atau dengan sengaja membiarkan gerakan itu berlangsung.
Kolonel Abdul Latief, yang disebut sebagai salah satu pimpinan G30S, dalam pleidoinya dalam Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmilub) secara terbuka menuduh Soeharto mengetahui rencana aksi “menjemput” para jenderal yang dituduh tergabung dalam Dewan Jenderal. Ia mengaku dua kali bertemu langsung dengan Soeharto menjelang 1 Oktober 1965. Pertemuan pertama terjadi pada 29 September 1965 di rumah Soeharto. Dalam kesempatan itu, Latief menyampaikan rencana membawa para jenderal untuk menghadap Presiden Sukarno dan menjelaskan dugaan rencana kudeta. Soeharto tidak tampak terkejut, bahkan mengatakan bahwa ia sudah mengetahui hal itu dari Subagyo, mantan anak buahnya (Tempo, 2013).
Pertemuan kedua berlangsung pada malam 30 September 1965 di RSPAD Gatot Subroto, beberapa jam sebelum gerakan dilancarkan. Latief datang menemui Soeharto yang kala itu sedang menunggui anaknya, Tommy, yang dirawat di rumah sakit. Latief kembali menyampaikan bahwa Dewan Revolusi akan menculik para jenderal Dewan Jenderal. Soeharto hanya mengangguk-angguk tanpa memberi respons tegas. Dalam versi lain, menurut Victor M. Fic (2005), Latief mengajak Soeharto untuk bergabung dalam barisan Dewan Revolusi tetapi Soeharto menolak untuk ikut serta dalam aksi tersebut, dengan alasan masalah Dewan Jenderal masih perlu penyelidikan lebih lanjut.
Sikap ambigu ini membuat Latief menaruh curiga terhadap Soeharto. Ia merasa ajakannya untuk mengikutsertakan Soeharto bersama 60.000 pasukan Kostrad guna menghadang kudeta dan melindungi Presiden Sukarno dari ancaman justru ditolak. Padahal posisi Soeharto sebagai Pangkostrad memberinya kekuatan militer yang sangat besar untuk menentukan arah peristiwa. Karena itu, Latief meyakini bahwa Soeharto telah mengetahui dan bahkan mungkin sengaja membiarkan aksi itu berjalan, demi kepentingannya sendiri.
Dalam konteks inilah Benedict Anderson menafsirkan bahwa Soeharto bukan hanya bermuka dua, sebagaimana tuduhan Latief, tetapi berdiri di atas “dua kaki.” Ia memegang erat jaringan Latief-Untung-Supardjo, namun pada saat yang sama juga memelihara jalur lain melalui Ali Moertopo-Yoga Soegomo-Benny Moerdani. Dengan cara itu, apa pun hasil dari gerakan, Soeharto tetap berada di posisi aman (Anderson, 2000). Jika pada peristiwa 30 September 1965 komunisme yang menang, Soeharto akan mengklaim perannya sebagai atasan dari Untung, Latief, Dul Arief, Supardjo, dan Bungkus, dengan alibi menyelamatkan Presiden Sukarno dari kudeta. Tetapi kita semua tahu, skenario yang menang adalah pihak militer AD, yang mungkin lebih dipilih Soeharto karena bisa menyingkirkan Ahmad Yani selaku atasannya dan menjadi kepercayaan Sukarno, sekaligus menyingkirkan paham komunisme sesuai pesanan elite global, dan memiliki nilai ekonomi yang besar.
Posisi Soeharto sebagai Panglima Kostrad memberinya kewenangan untuk merespons segera, tetapi ia memilih menunggu. Keputusan untuk tidak langsung bergerak dapat dipahami sebagai strategi politik, yaitu membiarkan situasi berkembang untuk kemudian dikendalikan. Crouch (1975) menyebut hal ini sebagai karakteristik kepemimpinan Soeharto—hati-hati, oportunis, dan menunggu momentum. Bisa jadi, bermainnya Soeharto di dua kaki, justru untuk mengadu domba pihak Angkatan Darat dan simpatisan Sukarno yang notabene berhaluan komunis. Melalui jaringan intelijen di pihak Soeharto, laporan yang diterima pihak Angkatan Darat dan perwira PKI sangat mungkin bersifat saling serang dan menjatuhkan. Sehingga ketika konflik antar keduanya semakin memuncak, Soeharto sudah memposisikan diri.
Dampak krisis 1965 ternyata membuka peluang emas bagi Jepang untuk kembali memainkan jaringan kader yang telah ditanam sejak masa pendudukan. Para mantan kader PETA seperti Soeharto, Yoga Soegomo, dan Ali Moertopo tampil sebagai tokoh kunci dalam perubahan politik. Jepang memandang krisis ini sebagai kesempatan untuk menegaskan kembali pengaruhnya di Indonesia. Keterhubungan personal dan ideologis dengan kader lama membuat Jepang mampu bergerak cepat mendukung kekuatan baru. Peristiwa ini memperlihatkan kesinambungan strategis dari penanaman kader era pendudukan hingga konsolidasi Orde Baru (Crouch, 1975).
Negara Boneka Manchuria, kaitan dengan Orde Baru?
Bisa dibilang, apa yang terjadi di Indonesia pada 1965 juga memiliki kemiripan dengan situasi di Manchuria pada 1932, ketika Jepang membentuk negara boneka Manchukuo. Latar belakang utamanya adalah ambisi imperialis Jepang dan kepentingannya di wilayah Cina timur laut. Sejak kemenangan dalam Perang Sino-Jepang (1894-1895) dan Perang Rusia-Jepang (1904-1905), Jepang telah memperoleh hak ekonomi dan politik di Manchuria, termasuk penguasaan jalur kereta api South Manchuria Railway dan kehadiran militer Kwantung untuk melindunginya (Young, 1998). Manchuria kaya akan sumber daya alam strategis, yang semakin penting bagi ekonomi Jepang terutama setelah Depresi Besar pada 1929. Ketika gerakan nasionalis Tiongkok di bawah Partai Kuomintang berusaha menyatukan kembali wilayah-wilayahnya, dominasi Jepang di Manchuria terancam. Zhang Xueliang, warlord Manchuria saat itu, menyatakan kesetiaan kepada pemerintah Nasionalis Tiongkok, yang semakin memperburuk kekhawatiran Jepang (Lary, 2007).
Jepang melakukan invasi ke Manchuria, namun melalui sebuah rekayasa. Invasi ini dikenal sebagai Insiden Mukden, pada 18 September 1931, ketika perwira Tentara Kwantung merekayasa ledakan kecil di jalur kereta api milik Jepang di dekat Shenyang. Ledakan ini dijadikan alasan untuk melancarkan serangan penuh ke pasukan Cina dan menduduki wilayah Manchuria (Peattie, Drea, & van de Ven, 2011). Dalam waktu singkat, Jepang berhasil menguasai wilayah tersebut, dan pada awal 1932 mendirikan negara boneka Manchukuo. Tujuannya adalah melegitimasi pendudukan Jepang di mata internasional dan menjadikan Manchuria basis industri serta sumber daya bagi ekspansi lebih lanjut ke Asia Timur. Jepang kemudian mengangkat Pangeran Puyi, mantan kaisar terakhir Dinasti Qing, sebagai kepala negara. Penunjukan Puyi dilakukan untuk memberi kesan adanya unsur keberlanjutan kedinastian Tiongkok di Manchuria, meskipun seluruh kekuasaan sesungguhnya berada di tangan militer Jepang (Young, 1998).
Jika Manchukuo menunjukkan bagaimana sebuah rezim lokal dijadikan simbol untuk menutupi dominasi kekuatan asing, Orde Baru memperlihatkan pola yang sebanding. Setelah peristiwa 1965, Soeharto membuka jalan bagi modal asing, terutama Jepang, melalui Undang-Undang Penanaman Modal Asing 1967, yang segera menjadikan Jepang mitra utama dalam sektor industri Indonesia (Robison, 1986). Seperti halnya Puyi yang menjadi figur simbolis bagi proyek kolonial Jepang, Soeharto dapat dibaca sebagai elite lokal yang berfungsi menopang kepentingan geopolitik eksternal, dalam hal ini arsitektur containment Amerika Serikat yang menjadikan Jepang motor ekonomi Asia Timur (Dower, 1999). Silakan lihat tabel di bawah ini untuk menjadi bahan renungan.
| Aspek | Manchukuo (1932–1945) | Orde Baru Indonesia (1966–1998) |
|---|---|---|
| Latar Belakang | Jepang ingin mengamankan kepentingan ekonomi dan militer di Manchuria pasca Depresi Besar. | Barat (AS) khawatir Indonesia jatuh ke komunisme, Jepang diarahkan jadi motor ekonomi Asia. |
| Aktor Lokal | Puyi, mantan kaisar Dinasti Qing, dijadikan simbol legitimasi negara boneka. | Soeharto, jenderal AD, naik pasca G30S sebagai simbol stabilitas nasional. |
| Alasan Intervensi | Insiden Mukden 1931: ledakan buatan di jalur kereta, dijadikan alasan untuk invasi. | Peristiwa G30S 1965: penculikan jenderal dijadikan legitimasi pembersihan politik. |
| Kepentingan Asing | Jepang menguasai sumber daya Manchuria dan menjadikannya basis industri perang. | Jepang & Barat menguasai investasi strategis Indonesia melalui UU PMA 1967. |
| Fungsi Rezim | Manchukuo jadi “etalase” kekuasaan Jepang, meski kendali penuh di tangan Tentara Kwantung. | Orde Baru jadi pilar containment AS, sekaligus pintu ekspansi modal Jepang di Asia Tenggara. |
| Legitimasi Politik | Kebangkitan Dinasti Qing dijadikan alasan simbolik untuk meyakinkan rakyat Manchuria. | Narasi penyelamatan bangsa dari komunisme dipakai untuk membenarkan otoritarian Orde Baru. |
Jadi pada dasarnya, peristiwa September 1965 tidak bisa dilepaskan dari konteks global. Sukarno berusaha membangun kemandirian nasional dengan menasionalisasi industri strategis, menggerakkan massa rakyat, dan merintis penguasaan teknologi maju termasuk nuklir. Amerika Serikat dan sekutunya melihat langkah ini sebagai ancaman serius terhadap stabilitas kawasan Asia Tenggara. Jika Indonesia benar-benar berhasil menguasai teknologi tersebut, peta politik regional bisa berubah drastis. Dalam pandangan Washington, munculnya kekuatan baru dengan orientasi anti-Barat di Asia Tenggara tidak boleh dibiarkan (Leifer, 1983).
Situasi ini menjadikan Indonesia sebagai arena penting dalam kompetisi geopolitik antara kekuatan besar pada masa Perang Dingin. Sukarno memandang penguasaan teknologi, termasuk nuklir, sebagai bagian dari strategi global untuk memperkuat posisi bangsa di panggung internasional. Sebaliknya, Amerika dan sekutunya menilai kebijakan itu sebagai langkah menuju radikalisasi politik yang berbahaya. Kontradiksi inilah yang memperparah ketegangan internal Indonesia, yang kemudian meledak menjadi krisis politik pasca peristiwa G30S. Program nuklir tidak hanya isu teknologi, melainkan juga faktor strategis dalam perebutan kekuasaan nasional maupun global (McIntyre, 2005).
Soeharto, Nasution, dan Dwifungsi ABRI
Pembaca tentu tahu istilah Dwifungsi ABRI. Ya, program Orde Baru yang mencuat kembali di era Prabowo Subianto sebenarnya adalah gagasan dari sosok A. H. Nasution. Pada saat Nasution masih menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, ia menyampaikan pidato bersejarah berjudul “Jalan Tengah” di Akademi Militer Magelang pada 1958. Abdul Haris Nasution adalah tokoh militer yang memainkan peranan penting dalam transisi kekuasaan pasca peristiwa G30S 1965. Sebagai Ketua MPRS, Nasution menjadi figur yang memiliki legitimasi politik untuk mengesahkan kepemimpinan baru bagi Indonesia.
Pada Maret 1967, dialah yang secara resmi melantik Soeharto sebagai pejabat presiden menggantikan Sukarno yang dipandang gagal menjaga stabilitas politik. Setahun kemudian, tepatnya pada Maret 1968, Nasution kembali memimpin sidang MPRS yang mengukuhkan Soeharto sebagai presiden penuh Republik Indonesia. Tanpa jasa dan wewenang Nasution, langkah politik Soeharto menuju puncak kekuasaan tidak akan berjalan semulus itu.
Namun setelah mencapai targetnya, Soeharto mulai menjaga jarak sekaligus membatasi ruang gerak politik Nasution yang dianggap berpotensi mengganggu. Rezim Orde Baru melihat ketokohan Nasution, dengan latar belakang panjang sebagai panglima dan konseptor strategi militer, sebagai ancaman tersendiri. Soeharto mengeluarkan berbagai kebijakan yang membuat Nasution kehilangan pengaruh, termasuk pencopotan dari jabatan Ketua MPRS pada 1972. Nasution juga dilarang berbicara di ruang publik, termasuk di kampus maupun media massa, yang seolah dimaksudkan untuk menghapus suaranya dari ruang demokrasi. Perlakuan ini menunjukkan bahwa Soeharto hanya membutuhkan Nasution pada awal konsolidasi kekuasaan, tetapi tidak menginginkan kehadirannya sebagai mitra dalam jangka panjang.
Ketegangan antara keduanya semakin jelas ketika Nasution ikut bergabung dengan gerakan “Petisi 50” pada awal 1980-an, yang secara terbuka mengkritik penyalahgunaan kekuasaan Orde Baru. Sebagai balasan, pemerintah mencabut berbagai hak sipil dan politik para penandatangan petisi, termasuk Nasution. Ia dicekal bepergian ke luar negeri, dijauhkan dari media, dan dihapus dari daftar undangan resmi negara. Lebih jauh, akses bisnis maupun jaringan sosialnya turut dipersempit sehingga kehidupannya benar-benar terisolasi dari ruang publik. Dari tokoh yang pernah mengukuhkan Soeharto sebagai presiden, Nasution berubah menjadi musuh politik yang harus dikerdilkan (Historia.id, 2018).
Ironi besar dalam perjalanan sejarah Indonesia pasca peristiwa G30S adalah nasib yang menimpa A. H. Nasution sendiri. Pada malam 30 September 1965, ia sebenarnya menjadi target utama penculikan oleh pasukan Cakrabirawa, namun berhasil lolos meski putrinya gugur. Momen itu menempatkannya sebagai simbol korban PKI sekaligus tokoh yang paling layak memimpin perlawanan. Tetapi setelah Soeharto berhasil mengendalikan situasi dan meraih puncak kekuasaan melalui dukungan militer serta pengesahan MPRS, justru Nasution yang tersingkir. Orang yang seharusnya tampil sebagai penyelamat bangsa pasca tragedi berdarah itu malah dikhianati dan dimarginalkan oleh orang yang ia bantu naik ke kursi presiden.
Pengucilan terhadap Nasution tidak hanya bersifat administratif tetapi juga sampai pada perlakuan yang merendahkan martabatnya di hadapan publik. Salah satu insiden paling mencolok terjadi pada awal 1990-an, ketika ia menghadiri prosesi penghormatan terakhir untuk Jenderal T. B. Simatupang. Dalam momen itu, pengawal Soeharto mendorongnya keluar ruangan secara kasar, seolah melupakan posisinya sebagai salah satu tokoh penting militer Indonesia. Tindakan tersebut mempertegas bagaimana rezim tidak segan merendahkan figur senior yang pernah berjasa besar. Sejarah kemudian mencatat bahwa Nasution memang menjadi salah satu korban paling nyata dari praktik pengkhianatan politik Soeharto terhadap para jenderal yang sebelumnya mendukungnya.
Kita kembali ke tahun 1958, ketika Nasution menyampaikan pidatonya tentang “Jalan Tengah”. Ada alasan historis yang perlu digarisbawahi. Pidato itu lahir dari konteks politik pasca penyerahan kedaulatan RI 1949, ketika Angkatan Darat menerima kekuasaan sipil namun mendapati kelemahan nyata dalam sistem parlementer. Krisis politik dan pemberontakan daerah yang meluas membuat Nasution menilai bahwa militer perlu mengambil peran terbatas dalam kehidupan politik dan administrasi negara. Itulah mengapa ia menawarkan konsep “Jalan Tengah”, agar perwira bisa ikut serta dalam pengambilan keputusan strategis negara, bukan sebagai organisasi militer, melainkan sebagai individu-individu yang turut menyumbangkan pemikiran.
Dalam pidatonya ia menjelaskan, gagasan “Jalan Tengah” ini bukanlah konsep militerisme seperti kudeta yang marak di Asia, Afrika, dan Amerika Latin pada masa itu. Ia justru ingin menghindarkan Indonesia dari tradisi kudeta yang akan melahirkan kudeta-kudeta berikutnya. “Jalan Tengah” hanya memberi ruang bagi militer untuk duduk terbatas di lembaga-lembaga negara, misalnya sebagai anggota MPR, agar suara strategis Angkatan Darat dapat turut mewarnai arah kebijakan nasional. Konsep ini lahir dari semangat kekeluargaan dan gotong royong dalam Pancasila, di mana sipil tetap menjadi pengendali utama pemerintahan. Nasution sebenarnya merumuskan solusi kompromi agar militer tidak sepenuhnya dipinggirkan, tetapi juga tidak dibiarkan menguasai ranah sipil.
Namun, sepuluh tahun kemudian, Jalan Tengah Nasution dieksploitasi oleh Soeharto yang baru mengokohkan diri sebagai presiden. Soeharto mengembangkan gagasan itu menjadi doktrin Dwifungsi ABRI yang memberi legitimasi luas bagi militer untuk menguasai kekuasaan sipil. Akibatnya, selama Orde Baru berlangsung (dan masih terwarisi hingga sekarang), jabatan-jabatan strategis mulai dari menteri, gubernur, bupati, duta besar, hingga pimpinan lembaga negara hampir semuanya diborong oleh perwira aktif, khususnya Angkatan Darat. Inilah bentuk dominasi yang justru ditentang oleh Nasution sendiri, sebab gagasan awalnya hanya sekadar memberi ruang terbatas agar militer tidak terjebak pada kudeta. Distorsi itu menunjukkan bahwa Soeharto tidak hanya menyingkirkan figur Nasution secara pribadi, tetapi juga memelintir warisan intelektualnya demi memperkuat hegemoni rezim (Taliwang, 2017).
Epilog: Orde Baru, Rezim Stabil Namun Rapuh
Pada bagian sebelumnya, kita sudah membahas tentang hubungan Soeharto dengan negara Jepang, yaitu negara yang sudah memberikan kesempatan pendidikan militer hingga memiliki karir yang panjang, meskipun konteks Jepang saat itu sedang menjajah Hindia-Belanda. Sebelum dilantik menjadi Presiden, Soeharto bahkan telah menyiapkan UU Penanaman Modal Asing yang disahkan pada 10 Januari 1967. Kemudian setelah dilantik menjadi Presiden pada 27 Maret 1968, besoknya Soeharto melakukan kunjungannya ke Tokyo—dalam hal ini seperti sedang sowan ke Kaisar Hirohito—untuk meminta Jepang agar menjadi investor utama.
Akses Jepang terhadap ekonomi Indonesia difasilitasi melalui konglomerat lokal yang sudah lebih dulu berhubungan dengan Soeharto. Artinya, hubungan pribadi yang ia bangun sejak 1950-an dengan pengusaha Tionghoa menjadi jembatan penting bagi integrasi Indonesia ke dalam kapitalisme global (Yoshihara, 1988). Dari sini dapat disimpulkan bahwa jaringan bisnis lama dalam kisah hidup Soeharto bukan sekadar faktor tambahan, melainkan bagian fondasi yang memungkinkan Soeharto mengonsolidasikan Orde Baru.
Setelah Soeharto naik ke tampuk kekuasaan, Jepang menjadi negara pertama yang secara resmi menerima legitimasi pemerintahannya pada 1968. Langkah ini memperlihatkan keberanian Jepang mengambil risiko diplomatik demi menjalin hubungan erat dengan rezim baru. Dalam waktu singkat, Jepang mengikat Indonesia melalui investasi, perdagangan, dan pinjaman luar negeri. Hubungan ini memberi keuntungan strategis bagi Jepang sekaligus sokongan ekonomi besar bagi Orde Baru. Kunjungan Soeharto ke Jepang pada 1968 menjadi titik balik relasi simbiotik antara Tokyo dan Jakarta (Soesastro, 1989).
Sepanjang dekade 1970–1980-an, Jepang menjelma sebagai investor asing terbesar di Indonesia, menyokong pertumbuhan konglomerat Orde Baru. Proyek-proyek besar dalam industri kayu, mobil, baja, hingga pertambangan tidak bisa dilepaskan dari modal Jepang. Hubungan ini menciptakan kelas bisnis baru yang terikat erat dengan jaringan politik Orde Baru. Dominasi Jepang dalam investasi membuat perekonomian Indonesia sangat tergantung pada arus modal dari Tokyo. Dengan begitu, jejak Jepang dalam pembangunan Orde Baru menjadi salah satu warisan paling signifikan dalam sejarah ekonomi Indonesia (Robison, 1986). Padahal situasi ini nantinya akan memicu munculnya Peristiwa Malari pada 1974.
Selain Jepang yang menjadi mitra utama “pembangunan”, perubahan besar yang tampak dalam kebijakan ekonomi Orde Baru adalah keberadaan sekelompok ekonom lulusan University of California, Berkeley, yang kemudian disebut “Mafia Berkeley” oleh pengamat ekonomi David Ransom. Para ekonom itu didatangkan melalui jaringan akademik yang didukung USAID dan Ford Foundation sejak awal 1960-an (Elson, 2001). Tokoh-tokoh seperti Widjojo Nitisastro, Ali Wardhana, dan Emil Salim menjadi arsitek utama kebijakan stabilisasi makroekonomi. Strategi mereka menekankan penekanan inflasi, deregulasi perdagangan, dan pinjaman luar negeri. David Ransom (1970) menyoroti kelompok ini sebagai instrumen penetrasi kepentingan Amerika Serikat, karena orientasi kebijakannya sesuai dengan strategi kapitalisme global. Dapat dikatakan, pembangunan Orde Baru sejak awal memang diarahkan pada integrasi Indonesia ke dalam ekonomi dunia yang didominasi Barat.
Kebijakan teknokrat Orde Baru menekankan konsumsi teknologi daripada produksi teknologi. Dalam kerangka pembangunan ekonomi, impor mesin dan teknologi dianggap lebih efisien daripada investasi riset dalam negeri. Strategi ini membuat Indonesia bergantung pada kredit luar negeri untuk membiayai pembangunan industri. Walaupun pertumbuhan ekonomi tinggi tercatat sepanjang 1970-an, namun struktur industri tetap lemah dan didominasi sektor ekstraktif serta manufaktur berbasis impor (Ransom, 1970). Sains dan teknologi dalam negeri tidak berkembang secara mandiri, karena orientasi pembangunan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, bukan produksi. Model pembangunan ini kemudian dipuji sebagai “keajaiban Orde Baru,” tetapi pada dasarnya bersifat semu. Indonesia lebih menjadi pasar bagi produk-produk asing daripada pusat inovasi teknologi yang mandiri.
Di sisi lain, Soeharto juga membangun legitimasi melalui proyek teknologi tinggi yang dipimpin oleh B. J. Habibie. Seperti dijelaskan oleh Sulfikar Amir (2012), rezim Orde Baru menciptakan apa yang disebut technological state, yaitu negara yang menggunakan proyek teknologi tinggi sebagai simbol modernitas. Lembaga seperti BPPT dan IPTN dikembangkan bukan semata untuk ekonomi, tetapi untuk menampilkan prestise nasional. Pesawat N250, misalnya, menjadi ikon kebanggaan, meskipun secara ekonomi tidak realistis. Proyek ini lebih berfungsi sebagai alat legitimasi politik, yang memperlihatkan Soeharto sebagai pemimpin modern. Orde Baru memperlihatkan dua wajah, pembangunan ekonomi pasif yang didorong oleh para ekonom Berkeley, dan pembangunan teknologi simbolik yang dipimpin Habibie.
Meskipun berbeda arah, kedua pendekatan itu sama-sama melemahkan kapasitas mandiri Indonesia dalam sains dan teknologi. Kebijakan Mafia Berkeley membuat Indonesia terjebak dalam ketergantungan struktural pada kredit, impor, dan investasi asing. Sementara proyek teknologi Habibie, meskipun ambisius, lebih berfungsi sebagai representasi simbolis daripada kebutuhan ekonomi riil. Sulfikar Amir (2012) menekankan bahwa proyek IPTN dan sejenisnya tidak berakar pada kebutuhan real dalam negeri, sehingga bergantung sepenuhnya pada perlindungan negara. Akibatnya, perkembangan sains dan teknologi di Indonesia tidak berjalan organik, melainkan dikendalikan oleh logika politik Orde Baru. Kombinasi ini menghasilkan pembangunan semu, pertumbuhan ada, tetapi kemandirian tidak tercapai.
Dengan fondasi seperti itu, konsolidasi Orde Baru berlangsung selama tiga dekade, tetapi dengan biaya yang besar bagi masa depan Indonesia. Negara memang memperoleh legitimasi melalui pertumbuhan ekonomi, stabilitas politik, dan simbol teknologi modern. Namun, ketergantungan pada impor dan pinjaman membuat Indonesia rentan terhadap guncangan eksternal. Krisis moneter 1997 memperlihatkan rapuhnya model pembangunan ini, ketika pertumbuhan semu runtuh dalam hitungan bulan. Proyek-proyek teknologi tinggi pun tidak dapat menyelamatkan legitimasi rezim, karena basis sosial-ekonomi rakyat telah lama diabaikan. Maka dari itu, epilog dari peristiwa 1965 bukan hanya lahirnya Orde Baru, melainkan juga lahirnya sebuah rezim pembangunan yang pasif, simbolik, dan penuh ketergantungan (Ransom, 1970; Amir, 2012).
Untuk memahami sifat pasif pembangunan Orde Baru, penting membandingkannya dengan negara-negara Asia Timur lain pada periode yang sama. Korea Selatan dan Taiwan, yang juga berada dalam pengaruh Amerika Serikat, justru memanfaatkan bantuan luar negeri untuk memperkuat basis produksi. Mereka membangun industri substitusi impor, memperkuat riset dalam negeri, dan melindungi perusahaan nasional hingga siap bersaing global (Amsden, 1989). Jepang sendiri, sejak era Meiji, menekankan transfer teknologi yang segera dipadukan dengan produksi nasional. Model ini menghasilkan developmental state yang menempatkan negara sebagai penggerak industri sekaligus pelindung teknologi dalam negeri (Johnson, 1982).
Sulfikar Amir (2012) menekankan bahwa kegagalan utama Indonesia adalah tidak pernah menjadi developmental state seperti Korea Selatan atau Taiwan. Pada dasarnya Habibie adalah korban dari kebijakan pemerintah yang tidak mendukung iklim riset dan industrialisasi mandiri. Kegagalan ini terjadi karena kebijakan Orde Baru diarahkan untuk menguntungkan segelintir pihak yang membentuk oligarki ekonomi (Robison, 1986). Setelah membuka diri ke blok Barat pasca-1965, rezim Soeharto gagal mengelola bantuan keuangan yang sebenarnya cukup besar.
Sebagai negara yang ditakutkan jatuh kepada komunisme, Indonesia memperoleh pinjaman modal ekonomi strategis dari Barat (Elson, 2001). Namun berbeda dengan Korea Selatan dan Taiwan, Indonesia tidak memanfaatkannya untuk membangun basis industri nasional. Indonesia tidak pernah mencapai posisi tersebut, karena pembangunan yang terjadi sarat dengan KKN, sehingga modal pinjaman lebih banyak masuk ke kantong oligarki (Ransom, 1970). Akibatnya, perputaran ekonomi menjadi berantakan, hutang tidak pernah bisa ditutup, dan rezim justru semakin bergantung pada utang luar negeri. Pendapatan terbesar negara kemudian bukan berasal dari prestasi industrialisasi, melainkan dari pajak tinggi yang menyulitkan rakyatnya.
G30S, Peristiwa yang Tak Pernah Habis Dibahas
Lebih dari setengah abad setelah terjadinya Gerakan 30 September 1965, perdebatan tentang siapa dalang dan siapa korban masih terus berlangsung. Rezim Orde Baru menancapkan narasi resmi bahwa PKI adalah pelaku utama, sementara Soeharto tampil sebagai penyelamat bangsa. Narasi ini bertahan selama tiga dekade melalui media, kurikulum, dan propaganda visual yang masif. Namun, setelah 1998, penelitian akademik membuka ruang bagi tafsir yang berbeda. Cornell Paper, Roosa, dan Robison, misalnya, menunjukkan bahwa peristiwa ini lebih kompleks daripada sekadar kudeta PKI. Fakta-fakta lapangan menunjukkan keterlibatan perwira militer, intelijen, dan kekuatan asing. Ketidakpastian ini menjadikan G30S sebagai topik historiografis yang terus hidup. Dengan kata lain, peristiwa ini telah menjadi bagian dari politik memori bangsa.
Salah satu alasan perdebatan ini tak pernah selesai adalah karena peristiwa tersebut dipenuhi oleh lapisan kepentingan yang saling bertabrakan. Bagi militer, G30S menjadi legitimasi untuk menumpas PKI dan memperluas kekuasaan politik. Bagi Amerika Serikat dan Inggris, peristiwa ini adalah momen strategis untuk menghapus pengaruh komunis di Asia Tenggara. Jepang memandangnya sebagai peluang emas untuk kembali menguasai pasar Indonesia melalui jalur investasi. Sementara itu, bagi Soeharto, G30S adalah tangga untuk naik ke puncak kekuasaan. Kompleksitas kepentingan inilah yang membuat peristiwa ini tidak bisa ditutup dengan satu narasi resmi. Setiap aktor memiliki versi dan kepentingan yang berbeda dalam menceritakannya. Karena itu, G30S tetap menjadi arena pertempuran narasi hingga kini.
Alasan lain yang membuat peristiwa ini selalu relevan adalah kenyataan bahwa produk politik-ekonominya masih bertahan. Oligarki bisnis yang lahir dari konsolidasi Orde Baru tetap mendominasi ekonomi nasional. Struktur patronase politik yang dibangun Soeharto juga diwariskan hingga era Reformasi. Banyak figur yang pernah menjadi beneficiary Orde Baru kini masih berperan dalam politik kontemporer. Hal ini memperlihatkan bahwa G30S bukan sekadar tragedi masa lalu, melainkan fondasi dari sistem kekuasaan hari ini. Dengan kata lain, perdebatan tentang G30S juga merupakan perdebatan tentang kondisi Indonesia kontemporer. Selama warisan itu masih hidup, diskursus ini akan selalu aktual. Inilah mengapa G30S bukan hanya catatan sejarah, melainkan juga realitas politik.
Akhirnya, G30S harus dipahami bukan sebagai peristiwa tertutup, melainkan sebagai prolog dan epilog konflik yang berkelanjutan. Prolognya adalah militer warisan Jepang, kisah utamanya adalah visi misi Demokrasi Terpimpin, sementara epilognya adalah lahirnya Orde Baru. G30S 1965 bukan hanya titik balik politik, melainkan juga titik balik nasib perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Indonesia.
Ambisi nuklir Sukarno saat itu membuat bangsa ini diperhitungkan, sekaligus ditakuti. Namun momentum itu kandas bersama jatuhnya Sukarno dan lahirnya Orde Baru. G30S bukan sekadar tragedi politik, melainkan juga momen hilangnya kesempatan Indonesia untuk menjadi pemain penting dalam perlombaan sains global. Perdebatan tentang G30S tidak pernah selesai, mungkin karena hasil akhirnya tidak hanya menentukan siapa yang berkuasa, tetapi juga siapa yang berhasil mengendalikan arah masa depan industrialisasi bangsa. Selama mereka masih ada, maka narasi-narasi sejarah yang berusaha membongkar suatu peristiwa konflik dari sudut pandang lain, akan dibungkam.
Penutup: Sebuah Refleksi ke Depan
Tulisan ini saya posisikan sebagai sebuah hipotesis kritis, bukan kebenaran mutlak yang mengikat pembaca. Hipotesis ini menawarkan sudut pandang alternatif bahwa Orde Baru bisa dibaca sebagai rezim boneka, serupa dengan praktik negara klien dalam sejarah geopolitik di era 1960-an. Tulisan ini terbuka untuk diskusi karena pada dasarnya terdapat dua kelemahan utama yang harus diakui agar analisis tetap objektif dan berimbang. Pertama, memang tidak ada dokumen eksplisit yang menyebutkan keterlibatan Jepang secara langsung dalam “mencetak” Soeharto sebagai boneka. Dunia intelijen tidak akan benar-benar meninggalkan jejak arsip, maka saya yakin buku Memori Jenderal Yoga pun sebenarnya sudah disaring info-info intelijennya, sehingga narasi alternatif ini terbentuk murni dari interpretasi dari berbagai data yang tersebar di berbagai sumber primer dan sekunder.
Terlebih lagi, buku-buku sejarah sebagai sumber sekunder, pastinya ditulis oleh sejarawan yang bisa pro terhadap Sukarno, pro terhadap Soeharto, bisa juga netral, sehingga semua sumber digunakan untuk saling mengisi dan mengkritisi satu sama lain. Kedua, dinamika dalam negeri seperti perpecahan elite Angkatan Darat dan konflik dengan PKI juga berperan penting dalam terjadinya peristiwa. Dengan mengakui dua kelemahan ini, tulisan ini tetap menjaga ruang kritis, sekaligus mendorong pembaca untuk merenungkan ulang peristiwa 1965 hingga tumbangnya Orde Baru.
Meski demikian, teori geopolitik yang saya pakai memberi penjelasan masuk akal atas jatuhnya Soeharto pada 1998. Ketika sebuah rezim boneka dianggap tidak lagi patuh atau efektif, ia dapat diganti oleh aktor baru yang lebih menguntungkan (Lake, 2009). Soeharto yang pada awalnya dianggap mitra stabil, mulai menyimpang karena ide proyek mobil nasional Timor pada 1996, yang melanggar prinsip perdagangan bebas dan mengancam dominasi industri otomotif Jepang. Pada saat bersamaan, krisis finansial Asia yang bermula di Thailand menelanjangi rapuhnya ekonomi Indonesia, yang sarat KKN dan berutang besar (Haggard, 2000). Dalam kondisi demikian, kepercayaan internasional terhadap Soeharto menurun drastis, dan transisi kekuasaan dipandang sebagai jalan terbaik. Sehingga, jatuhnya Soeharto pada Mei 1998 dapat dibaca bukan semata-mata akibat krisis dalam negeri, melainkan karena ia tidak lagi memenuhi ekspektasi sponsor eksternal yang selama tiga dekade menopangnya.
Maka, rangkaian sejarah sejak 1965 hingga 1998 perlu dipahami sebagai satu garis panjang keterhubungan antara kepentingan global dan lokal. Peristiwa G30S tidak bisa dilepaskan dari kontestasi sains, teknologi, dan geopolitik, sementara tumbangnya Orde Baru memperlihatkan logika keberlanjutan yang sama. Indonesia dihadapkan pada dilema klasik negara berkembang, yakni tetap menjadi pasar konsumtif yang menguntungkan aktor eksternal, atau berusaha berdikari dengan risiko kehilangan dukungan internasional. Dengan membaca ulang sejarah dari sudut pandang ini, publik dapat lebih kritis dalam menilai siapa sebenarnya yang paling diuntungkan dari konflik-konflik besar bangsa. Peristiwa September 1965 dan krisis 1998 harus dipahami bukan hanya sebagai tragedi politik dalam negeri, tetapi juga sebagai cerminan relasi timpang dalam tatanan global.
Perkembangan mutakhir memperlihatkan arah politik luar negeri Indonesia kembali berada dalam pusaran kontestasi global. Prabowo, yang kini berkuasa, mempererat hubungan dengan Republik Rakyat Tiongkok dan memutuskan bergabung dalam aliansi BRICS sebagai strategi diversifikasi mitra internasional. Pilihan ini tentu berpotensi menimbulkan gesekan dengan blok Barat, yang sejak lama memiliki kepentingan strategis di Asia Tenggara. Menariknya, beberapa peristiwa belakangan ini—mulai dari penembakan diplomat Indonesia, keracunan dalam program MBG, hingga gelombang demonstrasi besar pada Agustus-September 2025—dapat dibaca sebagai semacam peringatan politik dari luar.
Hasil dari demonstrasi Agustus–September, yang membawa simbol warna pink dan hijau dengan tuntutan 17+8, diindikasikan sebagian kalangan telah disusupi pihak eksternal, mirip dengan pola revolusi warna di Georgia (2003), Arab Spring (2011), hingga Sunflower Movement di Taiwan (2014). Aspek ini bisa terlihat di dunia maya, ketika tiba-tiba warganet Indonesia ramai menggunakan istilah ACAB dan simbolnya, 1312, dalam menggaungkan narasi kekerasan aparat. Padahal, sebelumnya istilah ini tidak pernah populer di Indonesia, dan bukan kosakata asli dari Indonesia. Bahkan ketika publik bereaksi keras kepada kepolisian terhadap kasus Ferdy Sambo, tragedi Kanjuruhan, atau penggunaan gas air mata dalam tiap demonstrasi mahasiswa sebelumnya, tidak pernah viral istilah ACAB dan 1312.
Pola kemunculan mendadak istilah ACAB menyerupai infiltrasi simbol global yang sebelumnya digunakan dalam protes berskala internasional, seperti Black Lives Matter di Amerika Serikat pada 2020 atau aksi demonstrasi di Hong Kong pada 2019. Fenomena ini sejalan dengan analisis Snow dan Benford (1992) tentang frame alignment processes, yaitu bagaimana gerakan sosial mengadopsi simbol dan narasi global untuk memperluas resonansi. Pada saat yang sama, konsep information operation menunjukkan bahwa aktor eksternal sering menyuntikkan narasi tertentu melalui media digital untuk mengarahkan opini publik (Clark, 2021). Pola serupa juga dapat ditemukan di Asia Tenggara, seperti demonstrasi anti-kudeta di Myanmar tahun 2021 yang meminjam slogan dan taktik digital dari gerakan Hong Kong (Khor, 2024), atau aksi-aksi di Filipina yang mengadopsi narasi global people power untuk menekan legitimasi rezim (Curato, 2016). Maka, istilah ACAB bukan sekadar ungkapan spontan masyarakat Indonesia, melainkan mungkin bagian dari strategi framing yang membuat gerakan lokal tampak selaras dengan arus protes global.
Logika geopolitik memberi isyarat bahwa kekuatan global kerap menggunakan ketidakstabilan dalam negeri sebagai sarana menekan negara yang dianggap keluar dari orbit kepentingannya (Nye, 2004; Krasner, 1999). Jika arah kebijakan luar negeri Prabowo saat ini membuka diri pada BRICS dan Tiongkok, tidak tertutup kemungkinan Indonesia kembali menghadapi intervensi tidak langsung dalam bentuk tekanan politik, ekonomi, maupun mobilisasi massa. Pertanyaan yang patut direnungkan kemudian, apakah Indonesia akan mengalami lagi situasi berdarah seperti 1965 dan mobilisasi massa 1998? Atau sebaliknya, apakah kali ini bangsa ini mampu belajar dari masa lalu, dengan mengelola tekanan eksternal tanpa harus kehilangan kedaulatan dan arah pembangunan nasional? Dan pertanyaan pamungkasnya, apakah kita masih akan menyebut peristiwa September 65 sebagai G30S/PKI, atau G30S/Jepang? Biarlah waktu yang akan membuktikannya.
Senarai sumber:
Buku dan jurnal:
Anderson, B. R. O’G. (1972). Java in a Time of Revolution: Occupation and Resistance, 1944-1946. Cornell University Press
Anderson, B. R. O’G. (2000). Petrus Dadi Ratu, NLR 3, May–June 2000, DOI: doi.org/10.64590/itv
Anderson, B. R. O’G. (2008). Exit Suharto: Obituary for a mediocre tyrant. New Left Review, 50, 27–59
Anderson, B. R. O’G., & McVey, R. T. (1966). A preliminary analysis of the October 1, 1965 coup in Indonesia (Cornell Paper). Equinox, 2009
Barr, C. M. (1998). Bob Hasan, the rise of Apkindo, and the shifting dynamics of control in Indonesia’s timber sector. Indonesia, 65, 1–36. https://doi.org/10.2307/3351319
Benford, R. D., & Snow, D. A. (2000). Framing Processes and Social Movements: An Overview and Assessment. Annual Review of Sociology, 26, 611–639. http://www.jstor.org/stable/223459
Cumings, B. (1997). Korea’s place in the sun: A modern history. W. W. Norton
Clark, J. R. (2021). [Review of Active Measures: The Secret History of Disinformation and Political Warfare, by T. Rid]. American Intelligence Journal, 38(1), 185–187. https://www.jstor.org/stable/27087774
Curato, N. (2016). Politics of Anxiety, Politics of Hope: Penal Populism and Duterte’s Rise to Power. Journal of Current Southeast Asian Affairs, 35(3), 91-109. https://doi.org/10.1177/186810341603500305
Cribb, R., & Brown, C. (1995). Modern Indonesia: A History since 1945. London: Longman
Crouch, H. (1978). The army and politics in Indonesia. Cornell University Press
Dower, J. W. (1999). Embracing defeat: Japan in the wake of World War II. W. W. Norton & Company
Elson, R. E. (2008). Suharto: A Political Biography, NY: Cambridge University
Fic, V. M. (2005). Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah studi komparasi, Yayasan Pustaka Obor
Hadiz, V., & Robison, R. (2004). Reorganising Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Markets. London: Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203401453
Haggard, S., & Mo, J. (2000). The Political Economy of the Korean Financial Crisis. Review of International Political Economy, 7(2), 197–218. http://www.jstor.org/stable/4177340
Jenkins, D. (2009). Soeharto and the Japanese occupation. Indonesia, 88, file Cornell eCommons
Kahin, A. (1999). Rebellion to Integration: West Sumatra and the Indonesian
Polity, 1926-1988. Amsterdam: University of Amsterdam Press
Krasner, S. D. (1999). Sovereignty: Organized hypocrisy (Rev. ed.). Princeton University Press
Khor, Y. L. (2024). Mapping the Transnationalisation of Social Movements Through Online Media: The Case of the Milk Tea Alliance. In: Facal, G., Lafaye de Micheaux, E., Norén-Nilsson, A. (eds) The Palgrave Handbook of Political Norms in Southeast Asia. Palgrave Macmillan, Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-99-9655-1_7
Latief, A. (2000). Pledoi Kol. A. Latief: Soeharto terlibat G30S. Institut Studi Arus Informasi
Lake, D. A. (2009). Relational Authority and Legitimacy in International Relations. American Behavioral Scientist, 53(3), 331-353. https://doi.org/10.1177/0002764209338796
Liddle, R. W. (1973). National leadership and local development in Indonesia. Journal of Asian Studies, 32(2)
Liu, H. (1997). Constructing a China metaphor: Sukarno’s perception of the PRC and Indonesia’s political transformation. Journal of Southeast Asian Studies, 28(1), 27–46. https://doi.org/10.1017/S0022463400014767
Liu, H. (2010). The historicity of China’s soft power: The PRC and the cultural politics of Indonesia, 1949–65. In Y. Zheng, H. Liu, & M. Szonyi (Eds.), The Cold War in Asia: The battle for hearts and minds (pp. 147–182). Brill
May, B. (1978). The Indonesian Tragedy (1st ed.). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781032717852
McIntyre, D. (2005). Bridging the gap between research and practice. Cambridge Journal of Education, 35(3), 357–382. https://doi.org/10.1080/03057640500319065
Nasution, A. H. (1984). Memenuhi panggilan tugas (Jilid 4: Masa pancaroba II)
Nye, J. S., Jr. (2004). Soft power: The means to success in world politics. PublicAffairs
Peattie, M., Drea, E., and van de Ven, H. (2011). The Battle for China: Essays on the Military History of the Sino-Japanese War of 1937–1945. Stanford, CA: Stanford University Press, 2011. xxv + 614 pp. ISBN 978-0-8047-6206-9
Ransom, D. (1970). The Berkeley Mafia and the Indonesian Massacre. Ramparts/Noah’s Ark
Ricoeur, P. (2004). Memory, history, forgetting. University of Chicago Press
Robison, R. (1986). Indonesia: The rise of capital. Allen & Unwin
Roosa, J. (2006). Pretext for mass murder: The September 30th Movement and Suharto’s coup d’état in Indonesia. University of Wisconsin Press
Soegomo, Y. (1990). Memori Jenderal Yoga : seperti diceritakan kepada penulis (B. Wiwoho, Ed.). Bina Rena Pariwara. ISBN 979817500X
Sundhaussen, U. (1982). The road to power: Indonesian military politics, 1945–1967. Oxford University Press
Yoshihara, K. (1988). The rise of ersatz capitalism in South-East Asia. Oxford University Press
Zhou, T. (2019). Sukarno’s nuclear ambitions and China: Documents from the Chinese Foreign Ministry Archives. Indonesia, 108, 89–120. https://doi.org/10.1353/ind.2019.0014
Media massa:
Erdianto, K. 11 Maret 2016, Sepenggal Kisah Dewi Soekarno dan Tiga Opsi Tawaran Soeharto, diakses pada 25 September 2025.
Global Times. 4 Mei 2023, Exclusive: New Report Unveils How CIA Scheme Color Revolutions Around the World, diakses pada 25 September 2025.
Indrawati, T., dkk. 8 September 2023, Biografi Sudono Salim, Konglomerat yang Terdampak Penjarahan 1998, diakses pada 25 September 2025.
Sitompul, M. 1 Maret 2018, Nasib Jenderal Pembangkang di Era Soeharto, diakses pada 25 September 2025.
Sitompul, M. 6 Mei 2025, Petisi 50 Menentang Rezim Orde Baru, diakses pada 25 September 2025.
Soeharto, H.M. Masa Perjuangan : Ada yang Mau Ngapusi Saya, diakses pada 25 September 2025.
Taliwang, M. H. 30 September 2017, Mengapa Jenderal AH Nasution Disingkirkan Jenderal Soeharto?, diakses pada 25 September 2025.
Wiguna, B. A. 4 Oktober 2021, Kolonel Latief 2 Kali Temui Soeharto Soal Rencana Menjemput Jenderal TNI AD, diakses pada 25 September 2025