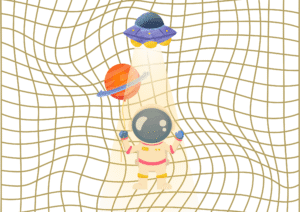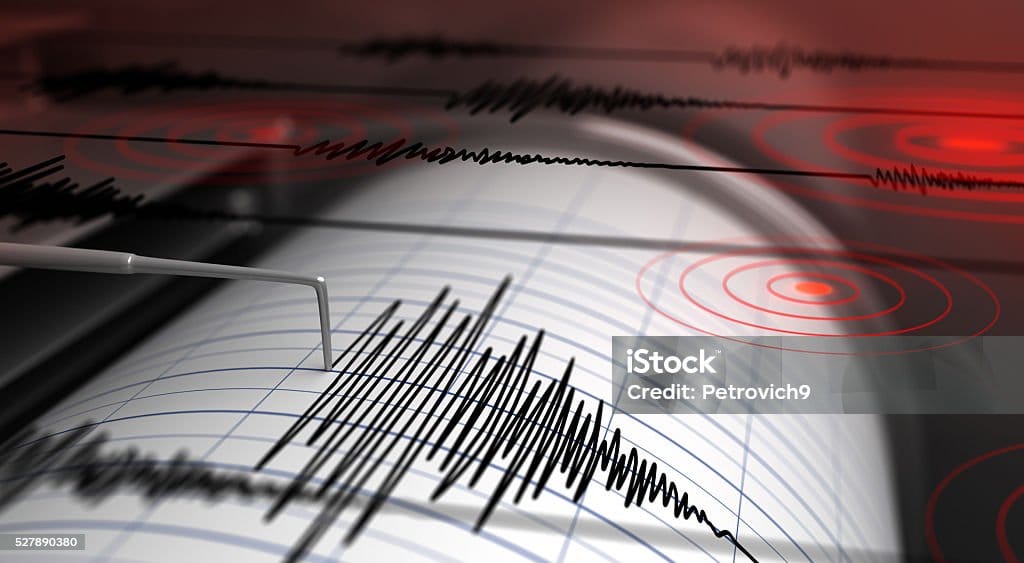Di tengah semakin meningkatnya jumlah kaum terpelajar di Indonesia, baik di tingkat pendidikan tinggi domestik maupun internasional, muncul pertanyaan mendalam: mengapa mereka gagal menjadi agen perubahan sosial yang nyata di tengah dominasi oligarki politik dan ekonomi yang semakin kuat?
Apakah ini mencerminkan kegagalan sistem pendidikan yang ada, atau ada perubahan struktural dalam kekuasaan dan ideologi yang mengubah peran kaum intelektual, menjadikannya kehilangan daya transformasi yang dulu mereka miliki?
Warisan elite modern Indonesia
Lebih dari enam dekade lalu, sejarawan Robert van Niel dalam buku Munculnya Elite Modern Indonesia (The Emergence of the Modern Indonesian Elite-Pertama kali terbit tahun 1960) menguraikan bagaimana munculnya elite terpelajar dari kalangan pribumi awal abad ke-20 merupakan produk dari perubahan besar dalam struktur sosial Hindia Belanda.
Kebijakan Politik Etis yang digagas kolonial Belanda memberi peluang kepada penduduk pribumi terpilih untuk memperoleh pendidikan Barat. Dari sinilah lahir golongan terdidik yang kemudian menjadi penggerak pergerakan nasional: kaum nasionalis, Islamis, sosialis, dan komunis. Pendidikan dalam konteks ini bukan hanya mencerdaskan secara teknis, tetapi menyulut kesadaran politik, membuka akses pada ideologi, dan menumbuhkan semangat kolektivisme.
Dalam pandangan Van Niel, elite modern bukanlah pewaris kekuasaan tradisional berbasis keturunan, kekayaan, atau jaringan patron-klien. Mereka adalah produk dari perubahan struktural dan memperoleh legitimasi dari kapasitas intelektual serta komitmen terhadap perubahan sosial. Pendidikan menjadi sumber otoritas moral dan politik.
Namun kini, dalam realitas Indonesia kontemporer, pertanyaan besar kembali muncul, ke mana arah kaum elite terpelajar saat ini? Apakah mereka masih memiliki kekuatan moral dan keberanian politik untuk mendorong transformasi sosial, sebagaimana para pendahulunya pada awal abad ke-20? Ataukah mereka telah menjadi bagian dari sistem yang dulunya ingin mereka ubah?
Kapitalisme dan perubahan paradigma kesadaran
Zaman telah berubah. Jika awal abad ke-20 adalah era ideologi, ketika nasionalisme, sosialisme, komunisme, dan Islamisme menggugah semangat kolektif di seluruh dunia, maka dunia pasca-Perang Dingin justru ditandai oleh dominasi kapitalisme dan demokrasi liberal sebagai narasi tunggal. Dalam iklim inilah elite terpelajar Indonesia dibentuk hari ini.
Kapitalisme, yang awalnya hanya dianggap sebagai sistem ekonomi, kini menjelma menjadi ideologi kultural yang mendominasi cara manusia berpikir, merasa, dan bertindak. Pendidikan pun terjerat dalam logika ini, bukan lagi proses pembentukan kesadaran kritis, melainkan sekadar investasi pribadi demi mobilitas sosial dan penguatan daya saing individual.
Lulusan universitas, termasuk dari institusi luar negeri, didorong untuk menjadi teknokrat efisien, inovator bisnis, atau profesional berprestasi dalam dunia korporasi global. Etos self-branding dan pencapaian individu menggantikan semangat kolektivitas dan keberpihakan pada rakyat banyak. Bahkan aktivisme sosial telah dikomodifikasi, dari perjuangan ideologis menjadi proyek-proyek donor, startup sosial, hingga konten yang viral.
Dalam iklim seperti ini, kesadaran ideologis justru dianggap kuno atau bahkan berbahaya. Sosialisme diasosiasikan dengan kemiskinan dan otoritarianisme; Islamisme dengan ekstremisme; nasionalisme dengan konservatisme; dan komunisme dengan kekerasan sejarah. Kaum terpelajar menjauh dari ideologi bukan karena mereka tak relevan, tetapi karena mereka kehilangan ruang untuk diperdebatkan dan diperjuangkan secara serius.
Kapitalisme: sumber kemajuan, tapi juga tantangan
Namun, harus diakui, kapitalisme bukan semata-mata momok. Justru banyak kemajuan penting yang diperoleh manusia modern berkat mekanisme pasar kapitalis, inovasi teknologi, peningkatan produktivitas, pertumbuhan ekonomi, hingga dana besar untuk riset dan pengembangan pendidikan.
Banyak universitas terbaik dunia tumbuh dalam lingkungan kapitalisme, dan tak sedikit program beasiswa, hibah penelitian, serta kegiatan akademik yang didanai oleh sektor swasta atau yayasan kapitalis.
Masalahnya bukan pada keberadaan kapitalisme, tetapi pada dominasinya yang nyaris total dan tidak dikritisi. Ketika seluruh aspek kehidupan, termasuk pendidikan, kesehatan, politik, bahkan nilai-nilai moral, ditentukan oleh logika pasar, maka ruang untuk memperjuangkan keadilan sosial dan kesetaraan akan semakin menyempit.
Sistem ini secara perlahan menciptakan ketimpangan ekstrem, mempersempit partisipasi politik, dan melahirkan generasi terpelajar yang cerdas secara teknis, tetapi miskin keberpihakan.
Lebih parahnya, kapitalisme juga membentuk cara pandang generasi muda yang nyaris apolitis. Kritik terhadap sistem dianggap tidak realistis, sementara ketundukan terhadap status quo dibalut dengan narasi meritokrasi dan kesuksesan individu. Dalam kondisi seperti ini, pendidikan justru berisiko menjadi alat untuk mereproduksi ketimpangan, bukan membongkarnya.
Elite terpelajar: terkooptasi dan terfragmentasi
Dalam sistem politik Indonesia yang didominasi oleh oligarki, banyak kaum terpelajar justru masuk ke dalam birokrasi atau lembaga-lembaga negara bukan sebagai pembaharu, tetapi sebagai pemoles legitimasi teknokratik. Harapan bahwa perubahan bisa dilakukan “dari dalam” seringkali kandas di tengah realitas sistem politik yang transaksional, hirarkis, dan penuh kompromi pragmatis. Tidak sedikit yang akhirnya memilih diam, apatis, atau justru menikmati kenyamanan struktural yang mereka tempati.
Di sisi lain, mereka yang tetap kritis dan memilih jalur independen sering kali tidak memiliki cukup ruang untuk bersuara secara efektif. Gerakan intelektual menjadi terfragmentasi, kehilangan basis kolektif, dan tersebar dalam bentuk-bentuk yang tidak solid. Banyak pemikir dan aktivis yang hadir di ruang publik digital, namun narasi mereka tenggelam dalam arus konten cepat saji dan logika viral. Akibatnya, pemikiran kritis jarang menghasilkan gerakan sosial yang berkelanjutan.
Ruang politik formal pun semakin tertutup. Partai politik tidak menjaring elite berdasarkan kapasitas intelektual atau keberpihakan ideologis, melainkan berdasarkan koneksi, kekayaan, dan elektabilitas. Hal ini membuat banyak intelektual enggan masuk ke dalam politik praktis. Tapi di luar sistem pun, mereka tak memiliki cukup kekuatan untuk mendorong perubahan struktural. Mereka terjebak dalam paradox, terlalu idealis untuk masuk ke sistem, terlalu lemah untuk mengubahnya dari luar.
Ideologi yang terpinggirkan, masa depan tak terarah
Pembeda kaum terpelajar masa lalu dengan masa kini bukan sekadar kualitas pendidikan, melainkan keberadaan ideologi yang menjadi arah perjuangan mereka. Di masa lalu, kaum intelektual bersatu dalam semangat pembebasan melawan kolonialisme, memperjuangkan keadilan sosial, dan membangun masyarakat baru. Hari ini, semangat itu tergantikan oleh ambisi individu, prestasi akademik, dan strategi karier.
Tanpa ideologi, pendidikan hanya melahirkan tenaga profesional, bukan pemimpin perubahan. Tanpa ideologi, kritik menjadi sekadar opini pribadi, bukan alat transformasi. Dan tanpa ideologi, elite terpelajar justru menjadi alat pelestari sistem, bukan penggugatnya.
Sebagian orang percaya kita hidup di era pasca-ideologi, namun kenyataannya yang terjadi adalah dominasi satu ideologi tunggal, kapitalisme. Tantangan kita hari ini bukan hanya menghidupkan kembali ideologi lama, tetapi menciptakan ideologi baru yang relevan dengan konteks global dan lokal: ideologi yang menggabungkan keadilan sosial, keberlanjutan lingkungan, distribusi pengetahuan, dan perlawanan terhadap dominasi korporasi global.
Antara Pancasilais dan kenyataan
Lebih ironis lagi, banyak elite terpelajar Indonesia hari ini dengan mudah menyebut dirinya “Pancasilais”, sebuah klaim ideologis yang seolah menjadi jaminan moral. Namun jika kita cermati nilai-nilai dasar Pancasila secara praksis, sangat sedikit dari mereka yang sungguh-sungguh menghidupkan substansi ideologi itu.
Ketuhanan, kemanusiaan, keadilan sosial, dan musyawarah, semuanya terpinggirkan oleh praktik kekuasaan yang transaksional, pembangunan yang eksploitatif, dan gaya hidup yang hedonistik. Dalam nama Pancasila, bahkan praktik-praktik yang anti-Pancasila dilegalkan dan dibungkam.
Pancasila tidak gagal sebagai ideologi. Kegagalan ada pada mereka yang mengaku menjunjungnya, tetapi dalam praktik justru mencederainya setiap hari. Dalam konteks ini, elite terpelajar Indonesia telah menjadi cermin dari kemunafikan structural, fasih berbicara tentang nilai luhur, tetapi takluk pada logika pasar dan kompromi politik.
Panggilan untuk generasi terpelajar
Indonesia berada dalam persimpangan sejarah yang menuntut keberanian moral dan intelektual. Di tengah krisis ekologi, ketimpangan ekonomi, dan melemahnya etika publik, perubahan tidak akan datang dari teknologi atau pasar semata. Perubahan memerlukan kesadaran kritis, imajinasi politik, dan keberanian untuk membangun alternatif.
Kaum terpelajar seharusnya menjadi ujung tombak perubahan itu. Namun peran ini tidak akan terwujud jika mereka terus terperangkap dalam zona nyaman profesionalisme dan ketakutan akan ketidakpastian politik. Pendidikan yang mereka tempuh, baik di dalam maupun luar negeri harusnya melahirkan kesadaran, bukan sekadar keterampilan.
Pertanyaannya sekarang, apakah generasi terpelajar hari ini siap keluar dari jebakan individualisme dan kembali menata ulang komitmen ideologisnya? Apakah mereka bersedia membangun gerakan bersama yang melampaui algoritma media sosial dan batas-batas akademik? Apakah mereka cukup berani untuk tidak sekadar “menyesuaikan diri” dengan sistem, tetapi juga membongkarnya dan membangunnya kembali?
Pendidikan sejatinya adalah medan perjuangan. Dan elite terpelajar, sebagaimana ditunjukkan oleh sejarah pergerakan nasional, hanya berarti sejauh mereka mampu menggunakan pengetahuan dan kesadarannya untuk membela yang lemah, memperjuangkan keadilan, dan menantang kekuasaan yang menindas.
Jika tidak, maka mereka bukanlah penerus elite modern seperti yang dimaksud Robert van Niel, melainkan hanya sekumpulan teknokrat cerdas yang tersesat dalam kebisingan kapitalisme dan lupa arah sejarah bangsanya.