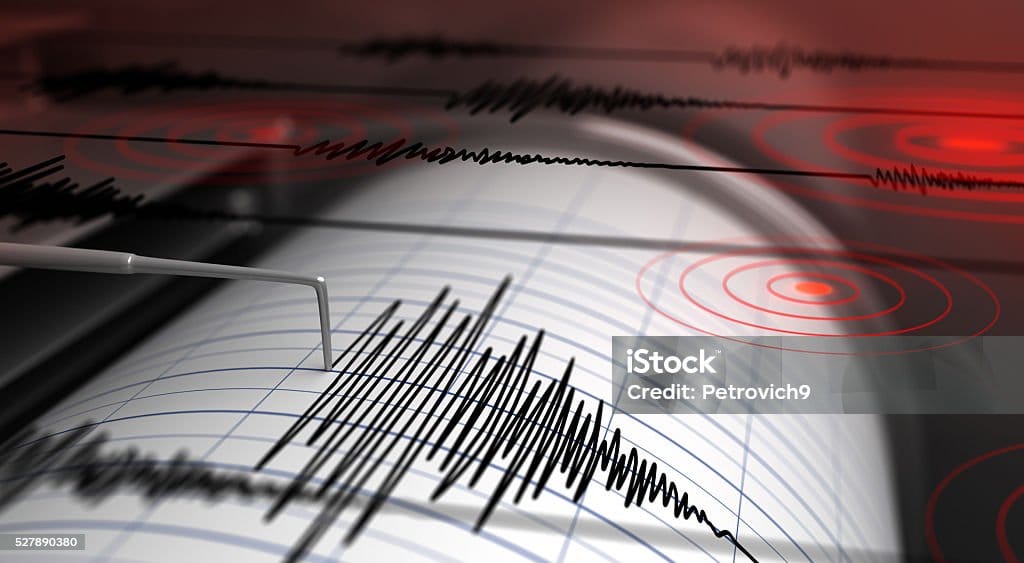Gelombang protes rakyat sepanjang Agustus 2025 lebih dari sekadar letupan ketidakpuasan. Ia adalah ekspresi kolektif dari kejenuhan atas sistem yang terus-menerus gagal mendengar dan memahami suara dari bawah.
Ribuan orang dari berbagai latar belakang mulai buruh, petani, mahasiswa, pengangguran, warga urban miskin, hingga kalangan kelas menengah turun ke jalan bukan karena mereka ingin merusak, tetapi karena mereka tak lagi memiliki ruang untuk didengar. Ketika saluran demokrasi formal mandek, dan janji-janji elektoral menjelma menjadi jebakan legitimasi kekuasaan, maka jalanan menjadi satu-satunya ruang politis yang tersisa.
Namun, alih-alih membaca protes ini sebagai sinyal kegagalan sistemik, Presiden Prabowo Subianto dan pemerintahannya memilih pendekatan yang justru mencerminkan ketakutan struktural atas hilangnya kendali. Ketimbang membuka dialog, kekuasaan merespons dengan represi.
Ketimbang mendengar, ia malah menunjuk dan menuduh. Tuduhan “makar”, “adu domba”, bahkan “terorisme” dilemparkan bukan untuk mencari kebenaran, tapi untuk mempertahankan monopoli atas narasi. Di sinilah letak kegagalan utamanya, Presiden Prabowo tidak hanya gagal memahami protes, tetapi juga gagal memahami rakyat sebagai subjek yang otonom, bukan objek yang harus dikendalikan.
Retorika kekuasaan: alat pelanggeng hegemoni
Dalam setiap kesempatan, Presiden Prabowo selalu menggunakan diksi yang mempertegas satu hal “negara berada dalam ancaman”. Baik dari dalam, maupun dari luar. Ancaman ini, menurut pemerintah, datang dari “kelompok radikal”, “aktor asing”, atau “provokator bayaran” yang ingin memecah belah bangsa.
Dalam narasi semacam ini, rakyat yang turun ke jalan tidak lagi dipandang sebagai individu-individu sadar yang menuntut keadilan, melainkan massa yang dipolitisasi, dimanipulasi, atau bahkan dimanfaatkan oleh kekuatan gelap.
Retorika ini bukan hal baru. Dalam banyak rezim otoriter, logika serupa digunakan untuk menciptakan ketakutan kolektif, sehingga pembungkaman bisa dibenarkan demi “stabilitas”. Ini adalah strategi kekuasaan yang berulang, ketika keabsahan mulai goyah, maka kontrol atas narasi menjadi senjata utama.
Tapi yang luput disadari adalah narasi hegemonik semacam ini justru menelanjangi ketakutan penguasa terhadap hilangnya otoritas moral. Sebab, kekuasaan yang sejati tidak membutuhkan senjata atau propaganda untuk mempertahankan kepercayaan; ia hadir melalui kesepahaman bersama yang lahir dari keadilan dan partisipasi sejati.
Negara gagal membaca rakyat sebagai subjek
Yang paling menyedihkan dari respons pemerintah adalah kegagalannya membaca bahwa protes ini bukan sekadar tentang kebijakan tertentu, tetapi tentang struktur relasi kekuasaan yang timpang.
Rakyat tidak hanya menolak satu kebijakan, tapi keseluruhan pola di mana pengambilan keputusan dilakukan dari atas ke bawah, tanpa partisipasi sejati dari mereka yang terdampak.
Dalam perspektif ini, kritik terhadap negara bukan hanya soal siapa yang berkuasa, tapi juga bagaimana kekuasaan itu bekerja. Sistem politik yang berlandaskan hierarki, birokrasi yang kaku, dan dominasi elite terhadap proses legislatif adalah akar dari ketidakadilan.
Banyak yang belum menyadari bahwa problemnya bukan hanya pada Prabowo, atau Jokowi, atau siapapun presiden yang berkuasa, tapi pada struktur kekuasaan itu sendiri yang memungkinkan terjadinya dominasi dan ketimpangan.
Inilah yang menjadi esensi dari tuntutan tak terucap dalam protes rakyat, yakni harus ada desentralisasi kekuasaan, otonomi komunitas dalam menentukan kehidupan yang layak bagi lingkungannya, dan penghapusan dominasi struktural.
Rakyat tidak hanya ingin didengar, mereka ingin turut menentukan. Bukan sebagai objek dalam sistem perwakilan semu, tetapi sebagai subjek yang sepenuhnya otonom.
Ketimpangan dan ketidakadilan struktural: Warisan yang dibiarkan membusuk
Krisis sosial yang meledak dalam bentuk protes sepanjang Agustus bukanlah hasil dari satu-dua kebijakan keliru. Ini adalah akumulasi dari ketimpangan sistemik yang selama ini dianggap normal.
Pembangunan infrastruktur yang diglorifikasi oleh pemerintahan sebelumnya, misalnya, ternyata lebih banyak menguntungkan investor dan elite politik-ekonomi dibanding masyarakat menengah bawah. Harga kebutuhan pokok meroket, upah buruh stagnan, dan penggusuran serta perampasan ruang hidup rakyat atas nama proyek-proyek pembangunan makin menjadi-jadi.
Sementara itu, UU Cipta Kerja yang sudah sejak awal ditolak oleh masyarakat sipil dan buruh tetap dipertahankan, bahkan terus diperkuat melalui peraturan turunan. UU ini adalah contoh nyata dari pengabaian hak kolektif demi efisiensi kapitalis. Di balik dalih menciptakan lapangan kerja, ada penghilangan atas jaminan hidup layak, stabilitas kerja, dan kekuatan negosiasi buruh.
Situasi ini diperparah oleh penegakan hukum yang diskriminatif. Korupsi di kalangan elite dibiarkan, sementara pelanggaran kecil oleh rakyat kecil segera diadili.
Ketika hukum menjadi alat kekuasaan, bukan alat keadilan, maka wajar bila kepercayaan pada negara runtuh. Dan ketika negara tak lagi dipercaya, maka rakyat mencari bentuk-bentuk organisasi alternatif berbasis solidaritas, bukan otoritas.
Politik akar rumput dan kemandirian kolektif
Meski tidak selalu disadari, semangat baru mulai tumbuh di tengah protes. Ia lahir dalam bentuk pengorganisasian akar rumput berupa forum-forum diskusi mandiri, logistik berbasis swadaya, sistem distribusi bantuan yang terdesentralisasi yang semua dikelola secara kolektif.
Semua dilakukan tanpa struktur komando, tanpa pemimpin tunggal, dan tanpa ketergantungan pada lembaga formal.
Itu adalah eksperimen sosial yang membuktikan bahwa masyarakat mampu mengorganisasi diri tanpa kontrol dari atas. Ini bukan hanya bentuk perlawanan terhadap sistem lama, tapi juga prototipe masa depan, di mana solidaritas menggantikan dominasi, dan kerja sama menggantikan kompetisi.
Dalam situasi krisis, masyarakat menemukan kekuatannya sendiri. Bukan melalui pemilihan umum, bukan melalui perantara elite, tapi lewat aksi langsung yang lahir dari kebutuhan dan keberanian bersama. Di tengah kegagalan negara, muncul bentuk-bentuk alternatif pengelolaan sosial-politik yang lebih setara dan berbasis kebutuhan riil komunitas.
Negara yang menjadi ancaman bagi masyarakatnya sendiri
Respons negara terhadap protes ini semakin mempertegas krisis legitimasi. Penangkapan aktivis, pelabelan terhadap demonstran, sensor media sosial, dan represi aparat bukan hanya tindakan taktis; itu adalah tanda bahwa negara melihat rakyatnya sendiri sebagai ancaman.
Ketika kekuasaan lebih takut pada warganya daripada pada ketidakadilan, maka ia telah kehilangan dasar moral untuk memerintah.
Tindakan seperti menaikkan tunjangan DPR di tengah penderitaan rakyat adalah bentuk penghinaan terbuka terhadap keadilan. Ini menunjukkan bahwa kekuasaan telah tercerabut dari realitas sosial, hidup dalam gelembung elite yang tidak tersentuh.
Dan ketika rakyat meminta pertanggungjawaban, jawaban yang datang justru berupa brutalitas aparat hukum dengan memuntahkan peluru dan gas air mata, bahkan dibunuh dengan cara dilindas dengan kendaraan taktis.
Mencari jalan di luar sistem yang gagal
Tepat di bawah semua janji yang tak terpenuhi, di balik retorika persatuan yang justru memecah, dan di antara tindakan-tindakan represif yang menyamar sebagai perlindungan, ada satu pertanyaan besar yang tak bisa dihindari: Apakah struktur kekuasaan yang ada masih relevan untuk menyelesaikan persoalan bangsa?
Jika jawabannya tidak, maka kita perlu membayangkan ulang bagaimana masyarakat bisa berjalan tanpa harus terus-menerus menyerahkan kendali pada segelintir orang di atas. Kita perlu membuka ruang bagi cara hidup yang lebih setara, di mana kekuasaan tidak dimonopoli, melainkan dibagi secara adil; di mana rakyat tidak dimobilisasi, tapi memobilisasi diri mereka sendiri.
Indonesia tidak akan berubah hanya karena pergantian pemimpin. Ia akan berubah ketika rakyat menyadari bahwa kekuatan sesungguhnya tidak datang dari atas, tapi tumbuh dari bawah, dari keberanian untuk membangun ulang segalanya, mulai dari komunitas terkecil.