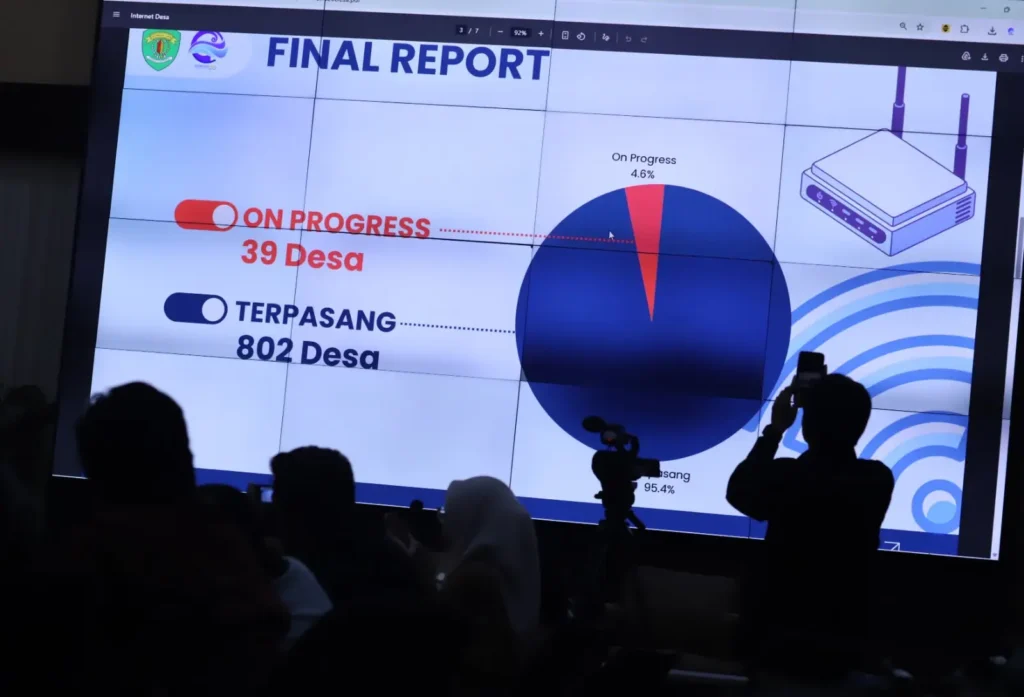Catatan redaksi: Tahun 2024 ini kelahiran AA Navis sudah 100 tahun. Untuk mengenangnya, redaksi menerbitkan arsip tulisan sastrawan terkemuka itu yang terbit di Kompas, Selasa, 15 Juli 1997.
Oleh: A A Navis
SEPERTI batu dilemparkan ke kolam, gempita Pemilu 97 yang lalu tak ubahnya dengan riak air yang radius kian meluas dan menghalus. Untuk selanjutnya permukaan kolam itu kelihatan akan tenang lagi. Bolehlah kita dapat tidur nyenyak dengan bermimpi atau tidak. Namun perumpamaan itu tidaklah begitu tepat apabila meninjau gejolak yang ditumbuhkan selama kampanye dan setelah pemilu usai.
Para politisi mengiaskan pemilu sebagai “pesta demokrasi”. Jika dilihat pada kejadiannya akan lebih tepat dikatakan “kecamuk pesta” tanpa embelan demokrasi. Yang berakar dari kondisi sosial masyarakat karena emosinya tidak tersalurkan. Kecamuk dapat saja terjadi di mana-mana, terutama pada watak dari masyarakat daerah yang berperilaku suka meledak bila sanubarinya tertindih. Antara lain seperti Aceh, Bugis, Madura atau Banjar. Masyarakat Jawa sendiri, yang oleh antropolog Belanda masa lalu dikatakan sebagai het zachte volk der arde atau bangsa yang terlembut di dunia itu, ternyata memiliki tradisi beringas massal juga dalam catatan sejarah. Merujuk kepustakaan sikap beringas tersebut dinamakan sebagai amouk partij atau pengamukan massal.
* * *
AMOUK partij sudah berlangsung sejak awal abad ini. Dalam catatan sejarah biasanya peristiwa itu bermula dari Solo. Lalu merembes ke timur sampai Surabaya. Dari sana berlanjut ke kota-kota pantai utara. Amouk partij tidak bersifat politik menentang pemerintah. Sebagaimana halnya dalam catatan sejarah, bahwa rakyat di Jawa tidak punya tradisi melawan raja atau pemberontakan terhadap pemerintah. Karena raja sangat dihormati oleh anggapan sebagai titisan dewa atau wakil dari Tuhan yang mereka sembah.
Sang raja atau bangsawan yang berkuasa di daerah cenderung berpe- rilaku gemar berpesta untuk memelihara martabat atau berfoya-foya karena memang merasa berkuasa. Untuk memenuhi tuntutan salah satu atau kedua-duanya mereka memerlukan uang yang banyak. Mereka tidak mungkin mengambil dari rakyatnya yang miskin. Mereka mengambilnya dari pedagang atau pengusaha nonpri. Katakanlah sama dengan kolusi antara penguasa dengan pengusaha. Agar usahanya tidak rugi, sang pengusaha meraup keringat rakyat yang jadi kawula raja. Rakyat yang tertekan tidak bisa bersuara atau berbuat apa pun karena takut kualat. Akan tetapi bila terjadi insiden, di mana pengusaha yang nonpri sampai mencederai seorang rakyat, maka terjadilah amouk partij yang memang mengerikan itu. Sasaran penghancuran hanya milik nonpri, bahkan adakalanya juga sampai terjadi pembunuhan.
Tentu saja ada tokoh pemicu yang mempunyai kepentingan tertentu. Di mana-mana dan di segala zaman selalu ada tokoh pemicu. Namun pemicu tidak akan berhasil apabila kondisi dan situasi penyebabnya tidak matang. Pemicu akan berhasil apabila situasi runyam tanpa ada tangan yang mampu mengantisipasinya.
Amouk partij selalu datang berulang, terutama di Jawa. Sampai pada kurun waktu Orde Lama, bahkan sampai kini. Peristiwa yang berlangsung jauh sebelum kampanye Pemilu sampai sesudahnya adalah tidak lain dari situasi yang matang bagi tumbuhnya amouk partij. Kondisinya memang tidak sepenuhnya sama dengan zaman Hindia Belanda, namun situasinya yang menumbuhkannya tidak banyak berbeda.
Situasi yang berlangsung sebelum kampanye pemilu sampai sesudahnya, bukanlah tersebab kampanye itu sendiri. Jika memakai perbandingan dengan kampanye Pemilu 1955, ketika pertentangan partai politik yang jauh lebih tajam, kecamuk pesta demokrasi tidak sampai me-makan korban jiwa atau harta. Lalu kenapa pada kampanye pemilu ketika semua kontestan adalah partai yang sana pendukung pemerintah, tradisi amouk partij tetap berlanjut? Siapa pemicunya? Orang perorang atau golongan tertentu yang subversif atau antipemerintah, sebagaimana yang disinyalir aparat negara pada umumnya?
Menurut saya, yang menjadi pematangan kondisi dan situasi penyebab terjadi kecamuk pada pesta demokrasi itu, selain dari penyebab timbulnya tradisi amouk partij yang masih belum habis terkikis, juga adalah karena ambisi yang berlebihan dari salah satu kontestan pemilu itu sendiri. Bahwa setiap OPP sebagai kontestan, adalah lumrah apabila ingin memperoleh kursi lebih banyak. Akan tetapi apabila salah satu kontestan yang sejak Orde Baru telah menjadi mayoritas tunggal di DPR, ingin lebih banyak lagi memperoleh kursi, sehingga OPP lain bakal mungkin tidak kebagian kursi, bisa membuat geleng kepala. Perilaku OPP itu sama saja dengan perilaku dari para konglomerat yang ingin meraup laba lebih banyak, lalu membuat target pemasukan lebih banyak lagi dari tahun lalu, tanpa memikirkan konglomerat lain menjadi sekarat.
* * *
NEGARAWAN masa lalu selalu mengatakan bahwa politik itu kotor. Kotornya karena ingin memenangkan partainya sendiri, meski berakibat yang lain sekarat. Pengamat politik pada umumnya berpendapat bahwa untuk masa yang masih panjang OPP pemilik mayoritas kursi DPR masih akan unggul. Namun pimpinannya masih berambisi dengan menaikkan jumlah kursi yang diperolehnya. Bahkan di suatu daerah ditargetkan perolehan suara sampai lebih dari 80 persen, sedangkan sebelumnya targetnya cuma 75 persen.
Teoretis, suatu target yang diinginkan pada lazimnya dilakukan oleh OPP yang tidak duduk di pemerintahan. OPP yang telah menduduki posisi mayoritas tunggal lazimnya memerlukan status quo. Jika mereka toh berambisi menaikkan target karena “kecurigaan” pada dirinya sendiri karena akan kecolongan, yang disebabkan kondisi dan situasi yang sangat tidak menguntungkan. Jika memang demikian alasannya, memakai dalil bahwa politik itu kotor adalah sah saja dalam permainan, seperti umumnya dilakukan oleh pemerintah di negara berkembang.
Kekotoran permainan politik berakibat fatal di Sampang, Madura. Aparat keamanan menuding pihak tertentu yang menjadi pemicunya. Padahal yang memungkinkan pihak tertentu itu memicu adalah “permainan politik yang kotor” yang menjadi sumbunya. Saya sendiri kurang tahu apa yang berlaku di daerah tempat saya bermukim. Akan tetapi pada Pemilu 1987, sepuluh tahun yang lalu, saya mengetahui pasti permainan kotor pada kotak-kotak suara. Saya temui Gubernur Azwar Anas, bukan untuk memprotes, melainkan bertanya: “Kenapa petugas TPS mesti disumpah memakai nama Allah kalau mereka disuruh melakukan kecurangan?”
Pertanyaan saya timbul bukan karena telah terjadi permainan kotor dalam usaha memenangkan politik. Melainkan oleh karena jutaan petugas TPS disumpah oleh negara dengan nama Allah, namun mereka disuruh berbuat curang untuk memenangkan salah satu OPP. Akan bagaimana watak bangsa dan turunannya yang membiasakan sumpah dengan nama Allah untuk melakukan perbuatan curang?
AA Navis, sastrawan; tinggal di Padang, Sumatera Barat
***
Baca juga: