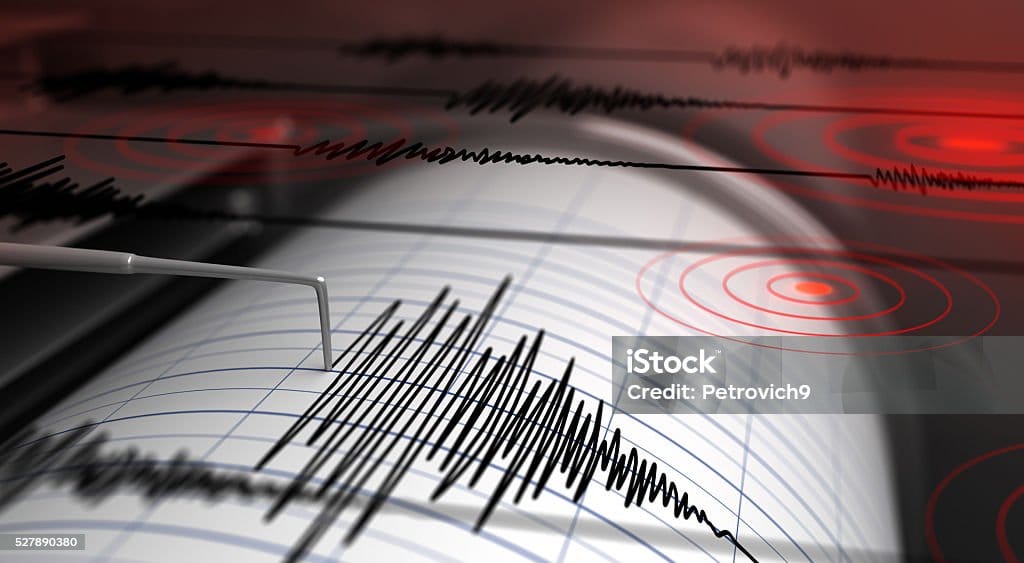Membangun Mimpi Poros Maritim Dunia
Sebagai negara maritim dengan kekayaan laut yang luar biasa, laut Indonesia bukan hanya sumber daya alam tetapi juga ruang hidup bagi jutaan orang yang menggantungkan nasibnya di sektor perikanan. Badan Pusat Statistik tahun 2022 mencatat jumlah nelayan tangkap dan pembudidaya ikan mencapai lebih dari dua juta orang. Namun, di balik angka besar itu, terdapat kenyataan pahit: sebagian besar dari mereka berstatus buruh nelayan, awak kapal perikanan, dan pekerja pengolahan hasil laut yang sering kali bekerja tanpa jaminan perlindungan yang memadai.
Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia memperkenalkan berbagai regulasi yang ditujukan untuk meningkatkan tata kelola sektor perikanan. Salah satu kebijakan besar adalah pergeseran dari sistem perizinan berbasis kapal ke sistem berbasis kuota yang diklaim lebih adil dan berkelanjutan. Regulasi ini diproyeksikan untuk meningkatkan penerimaan negara melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak, sekaligus mengurangi praktik penangkapan ikan ilegal. Akan tetapi, di lapangan, dampaknya bagi kelompok pekerja perikanan jauh dari ideal. Banyak nelayan kecil yang merasa semakin terpinggirkan, sementara buruh migran di kapal asing masih menghadapi persoalan eksploitasi dan perbudakan modern.
Ironisnya, kebijakan yang di atas kertas terlihat menjanjikan sering kali tidak memberi ruang cukup bagi suara pekerja yang paling terdampak. Diskusi publik lebih sering didominasi oleh negara dan pelaku industri besar, sementara serikat pekerja di sektor kelautan hampir tidak terdengar. Padahal, keberadaan mereka sangat penting untuk memastikan kebijakan tidak sekadar menguntungkan negara dan korporasi, tetapi juga melindungi manusia yang bekerja keras di balik rantai pasok perikanan.
Tulisan ini mencoba menelaah mengapa posisi buruh di sektor perikanan cenderung lemah dalam lanskap kebijakan maritim Indonesia. Ada beberapa faktor yang perlu dibongkar, mulai dari logika maritime exceptionalism yang memberi ruang khusus pada sektor ini, kepentingan negara dalam menjaga status quo, absennya serikat pekerja, hingga tumpang tindih kewenangan di lapangan. Tulisan ini ingin menggarisbawahi pentingnya pemerintah bertransformasi dari sekadar regulator menjadi fasilitator suara buruh, agar representasi keadilan bisa benar-benar terwujud.
Maritime Exceptionalism: Ruang Khusus yang Menghasilkan Kerentanan

Konsep maritime exceptionalism merujuk pada pandangan bahwa sektor kelautan dan perikanan berada dalam posisi yang unik sehingga membutuhkan perlakuan regulasi yang berbeda dari sektor lainnya. Pendekatan ini sering digunakan untuk menjelaskan mengapa aturan-aturan yang berlaku di darat tidak selalu diterapkan dengan cara yang sama di laut. Dalam konteks Indonesia, maritime exceptionalism lahir dari narasi historis dan geopolitik bahwa laut adalah identitas bangsa sekaligus arena perebutan ekonomi global.
Namun, keunikan yang dilekatkan pada sektor ini justru membuka ruang kerentanan. Dengan alasan bahwa laut berbeda dari darat, negara cenderung memberi kelonggaran yang lebih besar pada pelaku industri untuk mengatur dirinya sendiri. Misalnya, praktik penggunaan awak kapal perikanan migran di kapal asing sering kali luput dari pengawasan ketat karena dianggap bagian dari dinamika global yang kompleks. Pada akhirnya, logika pengecualian ini membuat buruh di sektor kelautan beroperasi di ruang hukum yang kabur, di mana perlindungan tenaga kerja tidak setegas sektor-sektor lain.
Penerapan maritime exceptionalism di Indonesia terlihat jelas dalam kebijakan perikanan berbasis kuota. Pemerintah menekankan pentingnya menjaga keberlanjutan stok ikan dan penerimaan negara, tetapi tidak cukup menaruh perhatian pada kesejahteraan buruh yang terlibat. Dengan logika exceptional, suara nelayan kecil sering dianggap kurang relevan dibandingkan kepentingan nasional yang lebih besar. Padahal, dalam kenyataannya, kebijakan ini sering kali meminggirkan mereka dari akses terhadap sumber daya yang justru menjadi sandaran hidup sehari-hari.
Selain itu, maritime exceptionalism memperkuat ketimpangan dalam rantai pasok global seafood. Indonesia yang menjadi salah satu eksportir utama tuna dan udang ke pasar Amerika Serikat dan Uni Eropa sering terjebak pada tuntutan standar internasional. Namun, implementasi standar itu lebih menekan pekerja di hilir daripada memberi manfaat bagi kesejahteraan mereka. Dalam kondisi demikian, buruh perikanan berada di persimpangan yang rawan: mereka dituntut untuk memenuhi syarat global, tetapi tidak cukup dilindungi oleh kebijakan domestik.
Status Quo Pemerintah di Sektor Kelautan

Dari sudut pandang pemerintah, regulasi perikanan berbasis kuota memberi keuntungan strategis. Kebijakan ini dipandang sebagai cara untuk menutup celah kebocoran sekaligus meningkatkan penerimaan negara dari sektor yang selama ini rawan praktik ilegal. Dengan mekanisme kuota yang terukur, pemerintah dapat memastikan kontribusi langsung industri besar terhadap kas negara. Selain itu, regulasi ini juga memperkuat posisi Indonesia dalam diplomasi maritim internasional, karena menunjukkan komitmen pada pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan di mata mitra dagang global.
Kepentingan devisa dan ekspor menjadi alasan utama status quo dipertahankan. Industri perikanan merupakan penyumbang devisa signifikan, terutama dari komoditas seperti tuna, udang, dan produk seafood olahan. Pada 2024 nilai ekspor perikanan mencapai hampir USD 6 miliar, naik dibandingkan tahun sebelumnya. Angka ini dipakai sebagai indikator keberhasilan pemerintah dalam menjaga kinerja sektor kelautan. Regulasi yang terlalu ketat terhadap kondisi kerja awak kapal dan nelayan kecil dikhawatirkan akan menurunkan daya saing produk Indonesia di pasar global. Dengan logika ini, perlindungan buruh sering kali ditempatkan sebagai prioritas sekunder.
Selain itu, hubungan erat antara pemerintah dengan asosiasi pengusaha dan juragan kapal juga turut memengaruhi arah kebijakan. Di banyak daerah pesisir, pemerintah daerah menjalin kedekatan dengan perusahaan eksportir yang dianggap mampu menciptakan lapangan kerja sekaligus meningkatkan pendapatan asli daerah. Relasi semacam ini membuat perlindungan pekerja dipandang sebagai “biaya tambahan” yang bisa mengurangi minat investor. Akibatnya, regulasi ketenagakerjaan untuk buruh laut sering kali dipinggirkan demi menjaga aliran investasi dan kestabilan politik lokal.
Beban administratif juga menjadi faktor penghambat reformasi. Mengintegrasikan perlindungan buruh laut dengan standar ketenagakerjaan nasional berarti pemerintah harus menyusun ulang mekanisme lintas kementerian, mulai dari Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, hingga Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Proses ini tidak hanya rumit secara birokrasi, tetapi juga mahal secara politik. Pemerintah khawatir reformasi besar semacam itu dapat menimbulkan resistensi dari pelaku industri sekaligus memperlambat kinerja birokrasi di lapangan.
Status quo dipertahankan karena dianggap lebih aman dari sisi fiskal, geopolitik, dan politik domestik. Kritik dari serikat nelayan atau organisasi masyarakat sipil kerap diposisikan sebagai gangguan terhadap narasi besar keberhasilan pemerintah dalam mengelola laut. Dalam kerangka ini, buruh dan nelayan kecil tidak lagi dipandang sebagai subjek utama pembangunan, melainkan sekadar angka pendukung statistik. Regulasi berbasis kuota kemudian dimaknai bukan hanya sebagai instrumen pengelolaan sumber daya, tetapi juga sebagai alat untuk menjaga legitimasi politik pemerintah dengan menampilkan diri sebagai pengelola laut modern yang sejalan dengan agenda global seperti SDG 14 tentang konservasi laut.
Ketiadaan Serikat Pekerja di Sektor Kelautan

Di sektor industri darat, serikat pekerja memainkan peran penting dalam memperjuangkan hak buruh. Namun dalam sektor kelautan, keterlibatan serikat pekerja jauh lebih lemah. Hal itu bukan tanpa alasan. Sifat kerja sektor perikanan sangat terfragmentasi. Nelayan bekerja dalam unit kecil berbasis komunitas, tidak terkonsentrasi di satu lokasi seperti buruh pabrik. Mereka berangkat dan kembali dalam ritme yang berbeda, sehingga solidaritas kelas sulit terbentuk. Mobilitas tinggi di laut juga membuat pembentukan jaringan kolektif menjadi tantangan besar.
Selain terfragmentasi, budaya patronase memperlemah semangat berserikat. Relasi antara juragan kapal dan anak buah kerap dibangun atas dasar loyalitas personal, bukan solidaritas kolektif. Nelayan atau awak kapal perikanan merasa lebih terikat secara emosional dan ekonomi dengan juragan dibanding dengan sesama buruh.
Dalam banyak kasus, juragan menyediakan akses modal, peralatan, hingga kebutuhan dasar, sehingga buruh memandang juragan sebagai pelindung sekaligus pemberi rezeki. Kondisi ini melemahkan dorongan untuk bersatu sebagai kelas pekerja yang independen. Beberapa nelayan bahkan masih ada yang takut bergabung ke dalam serikat pekerja karena akan dicap sebagai komunis. Tentu ini merupakan disinformasi yang harus mendapatkan perhatian dan sosialisasi yang tepat.
Status hukum pekerja laut yang buram juga membuat serikat kesulitan masuk. Banyak nelayan diposisikan sebagai “mitra usaha” atau bahkan bagian dari “keluarga usaha,” bukan sebagai pekerja formal. Istilah-istilah ini melemahkan pijakan hukum bagi serikat buruh untuk melakukan rekrutmen dan advokasi. Tanpa definisi yang jelas mengenai status pekerja laut, serikat besar kehilangan dasar legal untuk menuntut perlindungan yang lebih kuat.
Dan yang utama, isu-isu buruh perikanan sering lebih dulu ditangani oleh LSM, NGO, organisasi keagamaan, atau koperasi nelayan. Lembaga-lembaga ini sudah lama aktif dalam mengadvokasi hak nelayan, mulai dari akses bahan bakar, tata niaga hasil tangkapan, hingga isu lingkungan.
Serikat pekerja yang datang belakangan sering kali terlambat membangun basis dukungan di komunitas pesisir, sehingga ruang advokasi mereka semakin sempit. Persaingan ini bukan hanya soal legitimasi, tetapi juga soal kepercayaan. Nelayan cenderung mendekat ke organisasi yang sudah lebih dulu hadir dalam kehidupan sehari-hari mereka.
Akibat faktor-faktor itu, berimplikasi langsung pada lemahnya daya tawar buruh perikanan. Banyak kasus eksploitasi di kapal asing, seperti laporan International Labour Organization pada 2023 mengenai pekerja Indonesia di kapal Taiwan, tidak mendapat respons signifikan dari serikat buruh nasional. Situasi ini memperkuat kesan bahwa buruh perikanan adalah kelompok yang terisolasi, bekerja di ruang hukum yang abu-abu, dan nyaris tanpa perwakilan yang efektif dalam percaturan politik ketenagakerjaan nasional.
Tumpang Tindih Kebijakan Lembaga Pemerintah
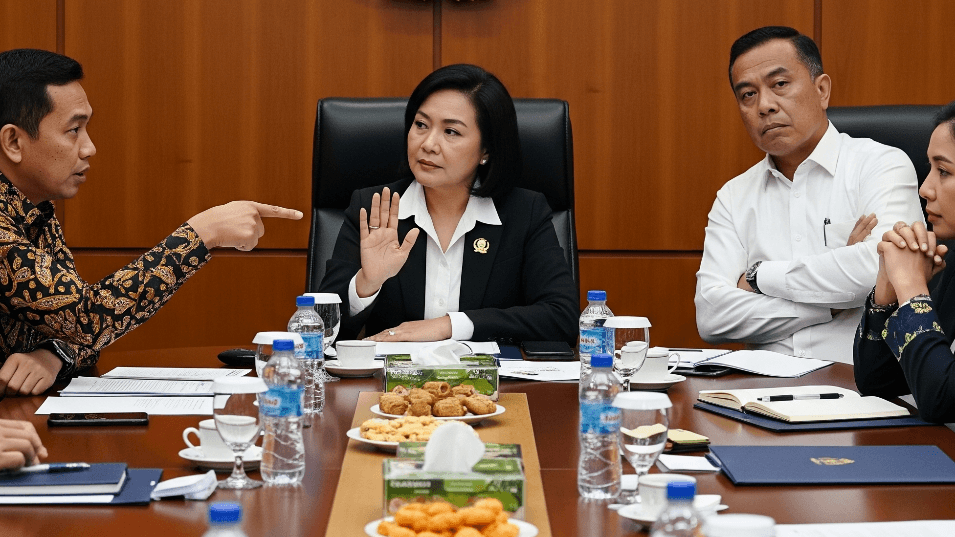
Tumpang tindih kewenangan antar lembaga pemerintah ikut memperumit situasi di sektor perikanan. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berfokus pada pengelolaan sumber daya dan industri, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memiliki mandat untuk melindungi tenaga kerja, sementara Komisi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI, dulu BP2MI) berwenang melindungi pekerja migran yang banyak berkarier di kapal asing.
Tidak kalah penting, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berperan dalam sertifikasi dan keselamatan pelayaran, serta Kementerian Luar Negeri (Kemlu) yang kerap harus turun tangan ketika kasus menyangkut yurisdiksi internasional. Banyaknya aktor ini menciptakan fragmentasi kebijakan dan kebingungan di tingkat implementasi.
Contoh konkret dapat ditemukan ketika seorang awak kapal perikanan (AKP) migran mengalami kekerasan di kapal Taiwan. Pertanyaannya kemudian muncul, apakah aduan tersebut harus ditangani KKP, Kemnaker, KP2MI, atau Kemlu? Tidak jarang, laporan serupa justru terombang-ambing karena masing-masing kementerian menganggap persoalan itu bukan ranahnya. Situasi serupa terjadi pada nelayan buruh lokal yang tidak menerima upah layak. Apakah perlindungan bagi mereka diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Perikanan, ataukah sekadar bergantung pada itikad baik juragan kapal? Kasus-kasus seperti ini memperlihatkan betapa buruh nelayan kerap tidak tahu pintu mana yang harus diketuk untuk mendapatkan keadilan.
Ketidakjelasan koordinasi antar lembaga ini sering berujung pada lemahnya implementasi perlindungan di lapangan. Akibatnya, meski Indonesia telah meratifikasi berbagai konvensi internasional terkait perlindungan buruh perikanan, penerapannya masih jauh dari harapan. Buruh nelayan tetap menghadapi jam kerja panjang, upah rendah, hingga kekerasan di laut. Sementara itu, negara gagal memberi perlindungan yang konsisten karena absennya mekanisme terpadu.
Seandainya tiap institusi memiliki keberanian politik dan bisa menahan ego sektoral masing-masing, solusi bersama dapat tercapai. Solusi yang dapat dicoba adalah membangun mekanisme perlindungan terpadu di bawah satu atap, yang mengintegrasikan fungsi KKP, Kemnaker, KP2MI, Kemenhub, dan Kemlu.
Model ini memungkinkan pekerja hanya perlu mengakses satu pintu untuk melaporkan kasus atau menyampaikan aspirasi. Selain itu, keberadaan inspektur ketenagakerjaan khusus sektor perikanan di pelabuhan besar akan menjadi langkah penting dalam memastikan pengawasan berlangsung efektif di titik paling dekat dengan aktivitas nelayan. Sistem pengaduan digital lintas lembaga juga dapat mempercepat respons dan mencegah praktik saling lempar tanggung jawab.
Tanpa perombakan struktural seperti itu, tumpang tindih kewenangan hanya akan melanggengkan status quo yang merugikan pekerja. Negara harus berani menegaskan siapa yang menjadi sektor utama dalam isu buruh perikanan, sekaligus memastikan lembaga lain mendukungnya secara operasional. Dengan demikian, buruh nelayan tidak lagi terjebak dalam kerumitan birokrasi, tetapi benar-benar merasakan hadirnya negara dalam melindungi mereka.
Ubah Peran dari Regulator Menjadi Fasilitator

Selama ini, peran pemerintah dalam sektor perikanan lebih dominan sebagai regulator yang menetapkan aturan main. Regulasi memang diperlukan untuk menjaga ketertiban industri, tetapi kondisi lapangan yang kompleks menuntut pergeseran peran menjadi fasilitator.
Artinya, negara tidak cukup hanya mengatur, tetapi juga harus memastikan suara buruh nelayan dan pekerja pengolahan seafood benar-benar terwakili. Pergeseran ini penting untuk menjembatani kesenjangan antara kepentingan negara, industri, dan kelompok pekerja yang seringkali tidak berada pada posisi setara dalam pengambilan keputusan.
Salah satu langkah strategis adalah memperkuat regulasi dan payung hukum yang selama ini masih timpang. Ratifikasi Konvensi ILO 188 tentang Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan akan menjadi pijakan penting agar standar internasional berlaku di Indonesia. Selain itu, definisi hukum mengenai status nelayan buruh juga perlu direvisi. Selama ini, mereka kerap dianggap sekadar “mitra” juragan kapal, bukan pekerja dengan hak ketenagakerjaan penuh. Jika pengakuan legal ini diperbaiki, maka buruh perikanan dapat memperoleh perlindungan yang sama dengan pekerja di sektor lain.
Perubahan peran pemerintah juga harus tampak dalam kelembagaan partisipatif. Forum tripartit yang selama ini berfokus pada sektor manufaktur atau formal perlu diperluas khusus untuk sektor perikanan. Keterwakilan buruh nelayan harus dijamin dalam Dewan Pengupahan maupun forum kebijakan maritim lainnya.
Dengan cara ini, pekerja tidak lagi sekadar objek kebijakan, melainkan subjek yang ikut menentukan arah. Ruang dialog formal yang dihadirkan pemerintah tidak boleh berhenti pada simbolisme konsultasi, tetapi harus menjamin masukan dari basis nelayan benar-benar terakomodasi dalam kebijakan akhir.
Penguatan organisasi basis menjadi elemen penting yang tak boleh terabaikan. Pemerintah dapat memfasilitasi pembentukan serikat atau organisasi buruh nelayan yang selama ini masih lemah. Program pelatihan advokasi, literasi hukum, dan pendampingan finansial perlu diberikan secara terstruktur agar komunitas pesisir mampu memperjuangkan haknya secara kolektif. Ketika serikat buruh perikanan semakin kuat, mereka akan lebih efektif dalam menegosiasikan kontrak kerja, standar upah, maupun jaminan sosial.
Dimensi lain yang juga krusial adalah perlindungan bagi pekerja migran dan rantai pasok global. Ribuan awak kapal perikanan Indonesia bekerja di kapal asing dengan risiko eksploitasi yang tinggi. Pemerintah harus memperkuat perlindungan melalui perjanjian bilateral dengan negara tujuan, termasuk memastikan adanya mekanisme pengaduan yang jelas.
Di sisi lain, industri pengolahan seafood di dalam negeri juga harus diawasi dengan audit ketenagakerjaan agar tidak ada praktik kerja paksa atau eksploitasi buruh perempuan. Dengan cara ini, rantai pasok Indonesia bisa memenuhi standar global sekaligus melindungi pekerjanya.
Langkah terakhir adalah pengawasan dan penegakan hukum yang lebih tegas. Inspektur ketenagakerjaan sektor maritim perlu ditempatkan di pelabuhan-pelabuhan besar untuk memastikan standar ketenagakerjaan dipatuhi. Kehadiran lembaga khusus, semacam ombudsman kelautan, juga dapat menjadi mekanisme independen untuk menindak pelanggaran dan memberikan akses keadilan yang lebih cepat. Tanpa perangkat pengawasan yang kuat, regulasi hanya akan menjadi teks hukum tanpa daya.
Dengan strategi-strategi ini, pemerintah tidak hanya menjalankan fungsi regulatif, tetapi juga menjadi fasilitator partisipasi buruh dalam pengambilan keputusan. Orientasi kebijakan pun bergeser dari sekadar pertumbuhan ekonomi maritim menuju keadilan sosial bagi komunitas nelayan. Hanya dengan cara ini, jargon Indonesia sebagai poros maritim dunia dapat berdiri di atas pondasi yang kokoh dan berkeadilan, bukan di atas kerja keras buruh yang terabaikan.
Menuju Representasi yang Adil

Masa depan sektor perikanan Indonesia tidak hanya ditentukan oleh kebijakan negara atau strategi industri, tetapi juga oleh sejauh mana buruh mendapatkan ruang untuk bersuara. Representasi yang adil berarti memastikan bahwa buruh nelayan, awak kapal perikanan, dan pekerja pengolahan seafood dilibatkan secara bermakna dalam proses pengambilan keputusan.
Untuk itu, diperlukan reformasi menyeluruh yang mencakup harmonisasi regulasi, penguatan serikat pekerja, dan keberanian politik pemerintah untuk menempatkan perlindungan buruh sebagai prioritas. Representasi tidak bisa hanya berhenti pada forum konsultasi, melainkan harus terinstitusionalisasi dalam mekanisme legislasi dan peraturan turunan yang mengikat.
Tentu saja, langkah ini tidak mudah. Akan selalu ada resistensi dari pihak-pihak yang sudah nyaman dengan status quo, termasuk industri besar dan birokrasi yang terbiasa dengan logika maritime exceptionalism. Namun, jika Indonesia sungguh ingin dikenal sebagai bangsa maritim, maka ukurannya bukan hanya besarnya penerimaan negara atau kuatnya armada industri, melainkan juga sejauh mana keadilan dinikmati oleh mereka yang bekerja keras di laut.
Pada akhirnya, representasi buruh di sektor kelautan bukan hanya soal hak asasi manusia, tetapi juga fondasi keberlanjutan industri itu sendiri. Industri perikanan yang mengabaikan kesejahteraan buruh akan sulit bertahan dalam jangka panjang, terutama ketika pasar global semakin menuntut standar ketenagakerjaan yang adil. Dengan memastikan suara buruh terdengar, Indonesia bukan hanya menjaga martabat pekerjanya, tetapi juga memperkuat daya saing maritim di kancah internasional.