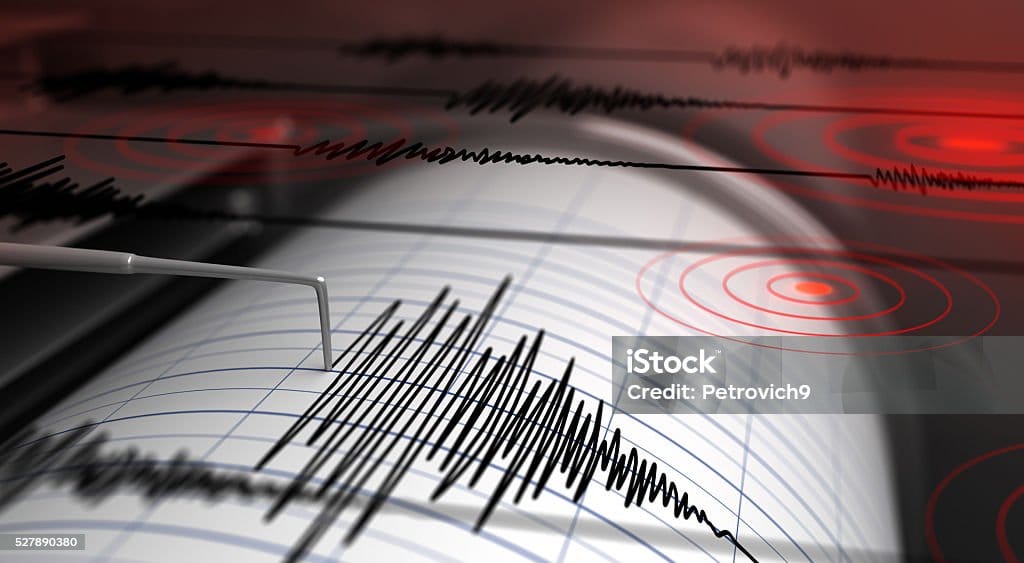Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan sebagai prioritas nasional oleh pemerintah Indonesia tampaknya datang dengan janji yang tak bisa ditolak, dengan argumen dapat menyelesaikan masalah stunting, memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM), serta membangun generasi emas Indonesia 2045. Dengan alokasi anggaran fantastis yang dikabarkan dapat mencapai puluhan triliun rupiah per tahun, MBG tampak seperti intervensi negara yang berani dan penuh komitmen. Namun, di balik narasi kemanusiaan yang mengharukan ini, program MBG menyimpan sejumlah persoalan serius yang harus dikritisi secara jujur, baik dari sisi tata kelola anggaran, orientasi kebijakan, hingga dampak jangka panjang terhadap struktur pangan dan ekologi nasional.
Dalam lanskap politik ekonomi Indonesia yang kompleks, program MBG berpotensi menjadi solusi parsial yang justru menutupi luka struktural yang lebih dalam. Dalam bukunya “Seeing Like a State” (1998), James C. Scott menyebut negara sering kali menggunakan skema terpusat untuk menyederhanakan realitas sosial yang kompleks. MBG mencerminkan kecenderungan ini, sebuah pendekatan teknokratik yang menyamaratakan kebutuhan gizi lintas wilayah dengan latar belakang sosial-ekologis yang sangat berbeda. Alih-alih memperkuat sistem pangan lokal yang kontekstual dan berkelanjutan, MBG hadir sebagai proyek sentralistik dengan logika distribusi massal dan kontrak pengadaan yang rentan terhadap praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Indikasi kerentanan terhadap KKN dalam pelaksanaan MBG bukanlah asumsi semata. Transparency International Indonesia (TII) dan Indonesia Corruption Watch (ICW) telah mengeluarkan pernyataan yang menyoroti potensi sistemik korupsi dalam proyek-proyek bantuan sosial berskala besar, terutama yang minim transparansi dan diawasi secara longgar.
Dugaan afiliasi antara penyedia jasa makan dengan lingkaran elite politik, lemahnya mekanisme penunjukan mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), serta ketiadaan regulasi publik yang kuat selain petunjuk teknis internal, menguatkan sinyal bahwa proyek ini bukan sekadar intervensi gizi, tetapi juga arena baru untuk distribusi rente. Kasus keracunan makanan di sejumlah daerah, meskipun diklaim sebagai insiden teknis, mencerminkan lemahnya pengawasan kualitas dan potensi pengorbanan mutu demi efisiensi anggaran atau keuntungan mitra swasta.
Krisis lingkungan dan kedaulatan pangan
Namun, fokus pada aspek teknis dan korupsi saja tidak cukup. Masalah struktural yang paling krusial, dan yang secara efektif “dibersihkan” dari diskusi publik oleh gemerlap MBG, adalah krisis lingkungan dan kedaulatan pangan. Indonesia adalah negara megabiodiversitas. Alamnya secara historis adalah gudang “makanan bergizi gratis.” Hutan, perairan, dan lahan pekarangan tradisional menyediakan beragam sumber protein hewani, vitamin, dan mineral dari tanaman, umbi, dan ikan endemik.
Kekayaan pangan lokal ini merupakan basis gizi seimbang secara ekologis dan budaya. Sayangnya, sumber daya pangan gratis ini telah dirampas secara sistemik melalui kebijakan pembangunan yang berorientasi pada eksploitasi dan ekspor komoditas. Peneliti politik lingkungan seperti Philip McMichael dalam karya “Food Regimes and Agrarian Questions” (2013) mengingatkan bahwa sistem pangan global kini dikendalikan oleh logika kapitalisme agribisnis, yang menciptakan ketimpangan akses pangan sekaligus merusak keberlanjutan ekologi lokal.
Indonesia bukan pengecualian. Ekspansi monokultur skala besar, terutama perkebunan kelapa sawit, bersama dengan operasi pertambangan, telah menelan jutaan hektar lahan komunal. Kebijakan ini tidak hanya merusak ekosistem dengan menghilangkan hutan sebagai penyedia air, obat, dan pangan, tapi juga menghancurkan sistem pengetahuan lokal mengenai pangan.
Ketika masyarakat desa dipaksa kehilangan akses terhadap hutan dan lahan, mereka kehilangan pengetahuan tentang pangan alternatif yang bergizi tinggi (seperti sagu, sukun, atau tanaman kelor lokal) dan terpaksa beralih menjadi konsumen produk pangan olahan yang murah, mudah diakses, namun tinggi gula, garam, dan lemak (ultra-proses). Dengan kata lain, pemerintah telah menciptakan penyakit struktural “kemiskinan pangan” di mana uang ada, tetapi sumber gizi sejati hilang dan kini mengobatinya dengan “proyek makanan” yang mahal. Kondisi ini yang disebut oleh Vandana Shiva, dalam bukunya “Soil Not Oil” (2007) sebagai “kemiskinan pangan yang dibangun oleh kebijakan.”
Ironisnya, MBG hadir justru dalam konteks tersebut. Sebagai intervensi negara terhadap problem gizi, program ini seolah mengobati gejala sambil mengabaikan penyebab. Ketika negara menyediakan makanan gratis dalam bentuk paket standar, sering kali tanpa melibatkan pengetahuan lokal. Diversitas pangan tradisional kian terkikis.
MBG, yang tidak disertai dengan reformasi agraria, perlindungan hutan adat, dan penguatan produksi pangan lokal, justru dapat memperdalam ketergantungan desa terhadap sistem pangan terpusat yang dikendalikan oleh negara dan mitra swasta. Ini adalah bentuk baru dari kolonisasi pangan, bukan pembebasan.
Penting untuk dicatat bahwa tidak semua elemen dalam MBG harus ditolak mentah-mentah. Dalam situasi darurat, seperti daerah dengan prevalensi stunting ekstrem atau wilayah yang dilanda bencana, penyediaan makan siang gratis tentu dapat menyelamatkan generasi muda dari malnutrisi akut.
Namun, menjadikan MBG sebagai strategi utama tanpa disertai restrukturisasi sistem pangan nasional adalah bentuk kegagalan visi. Kualitas gizi tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial dan budaya setempat. Menu yang diseragamkan, terutama yang tidak mempertimbangkan ketersediaan dan preferensi lokal, sering kali tidak diterima secara sosial dan bahkan bisa menjadi beban logistik yang mahal dan mubazir.
Anggaran, literasi gizi, dan MBG
Dari sisi fiskal, program MBG juga menimbulkan pertanyaan serius. Dengan anggaran yang berpotensi menyaingi total belanja perlindungan sosial lainnya, MBG menjadi beban berat bagi APBN. Dalam situasi fiskal yang rapuh akibat utang dan tekanan ekonomi global, penggunaan anggaran sebesar ini untuk program konsumsi jangka pendek terkesan tidak bijak jika tidak dibarengi dengan investasi struktural jangka panjang. Apalagi jika pelaksanaannya tidak transparan dan minim akuntabilitas, sebagaimana kritik terhadap proyek-proyek serupa di masa lalu, seperti kasus bantuan sosial tunai yang dikorupsi di masa pandemi.
Lebih dari itu, MBG juga gagal mengatasi satu dimensi penting lain dari kualitas SDM yaitu pendidikan dan literasi gizi. Ketika sistem pendidikan nasional masih belum mampu menanamkan pengetahuan dasar tentang pentingnya pola makan sehat, pengenalan pangan lokal, dan pertanian berkelanjutan, maka makan siang gratis hanya akan menjadi konsumsi pasif, bukan alat transformasi budaya pangan.
Generasi muda Indonesia harus diberdayakan untuk menjadi produsen dan pemilih pangan yang sadar, bukan sekadar penerima manfaat dari sistem distribusi negara. Tanpa reformasi pendidikan dan ekonomi lokal, program seperti MBG hanya menyelesaikan sebagian kecil dari masalah yang bersifat sistemik.
Solusi atas krisis ini tidak dapat bergantung pada proyek berskala besar yang bersifat simbolik dan populis. Pemerintah seharusnya mengalokasikan sebagian besar anggaran MBG untuk kebijakan hulu yang berakar pada tiga prinsip utama:
(1) Reformasi agraria sejati yang mengembalikan hak kelola lahan kepada petani dan masyarakat adat,
(2) Perlindungan ketat terhadap ekosistem dan hutan adat dari ekspansi industri ekstraktif, dan
(3) Penguatan pertanian ekologis dan sistem pangan lokal berbasis komunitas.
Ketiga langkah ini bukan sekadar solusi teknis, melainkan upaya rekonstruksi ulang relasi negara, rakyat, dan alam.
Akhirnya, jika pemerintah benar-benar ingin mencetak generasi emas, yang dibutuhkan bukan sekadar memberi makan, melainkan menciptakan sistem yang memungkinkan masyarakat hidup dengan bermartabat, sehat, dan mandiri. Seperti yang dikatakan oleh Amartya Sen dalam “Development as Freedom” (1999), pembangunan sejati adalah yang memperluas kebebasan dan kapasitas masyarakat untuk mengontrol hidup mereka sendiri, termasuk dalam hal pangan.
MBG, dalam bentuknya yang sekarang, masih jauh dari visi tersebut. Ia bukanlah tujuan akhir, melainkan sinyal bahwa kita membutuhkan perubahan mendasar dalam cara kita memandang pangan, pembangunan, dan keadilan sosial-ekologis.