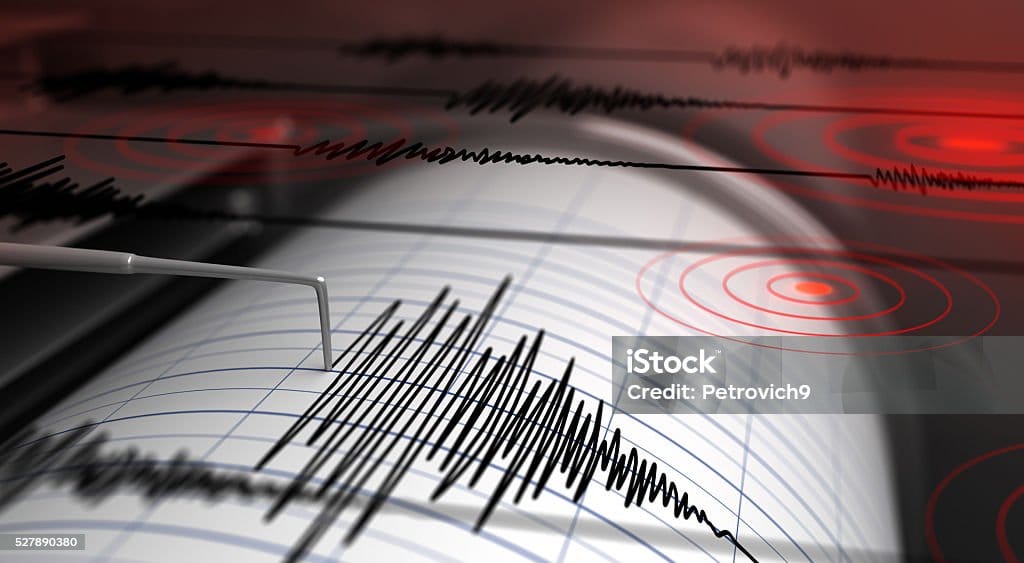Negeri ini selalu semarak saat pesta demokrasi yang rutin digelar lima tahunan. Namun, Indonesia masih berkutat dengan kenyataan getir bahwa demokrasi kita belum sepenuhnya hidup dalam substansi.
Demokrasi prosedural memang berjalan: Kita punya pemilu, DPR, dan lembaga-lembaga formal lainnya. Tetapi partisipasi bermakna, diskusi publik yang rasional, dan kesetaraan dalam pengambilan keputusan masih sangat terbatas.
Salah satu penghalang besar di balik stagnasi ini adalah budaya feodalisme yang tidak hanya dilestarikan oleh elite, tetapi juga secara aktif, dan sering kali tanpa sadar dipertahankan oleh masyarakat sendiri.
Fenomena ini terlihat di berbagai lapisan kehidupan sosial-politik. Banyak masyarakat yang mengeluh tentang ketidakadilan, korupsi, dan penyalahgunaan kekuasaan. Namun, ketika diajak untuk berpikir kritis, menyuarakan pendapat, atau terlibat dalam gerakan kolektif, sebagian besar memilih diam, menghindar, atau bahkan mencibir.
Mereka yang berani bersuara sering dianggap “cari masalah”, “tidak tahu sopan santun”, “melawan atasan” atau lebih parah “tindakan makar”. Akibatnya, budaya tunduk dan pasrah tetap subur, bahkan di era ketika akses informasi dan ruang ekspresi sudah terbuka lebar.
Warisan Kolonial yang Tak Usai
Untuk memahami akar masalah ini, kita harus kembali pada sejarah panjang kolonialisme dan struktur sosial yang diwariskannya. Kolonialisme bukan hanya penaklukan fisik, tetapi juga pembentukan mentalitas masyarakat yang tunduk dan terpinggirkan. Dalam konteks Indonesia, struktur sosial kolonial melahirkan sistem kekuasaan yang sangat hierarkis dan eksklusif, yang kemudian dilanjutkan oleh penguasa lokal setelah kemerdekaan.
Pemikir seperti Frantz Fanon (1961) menegaskan bahwa negara pasca-kolonial sering kali terjebak dalam reproduksi struktur kolonial dalam bentuk baru, elite nasional menggantikan penjajah, tetapi dengan pola kekuasaan yang tetap menindas. Feodalisme bukan semata warisan masa kerajaan, tetapi bentuk relasi kuasa vertikal yang menjadikan masyarakat sebagai objek, bukan subjek politik.
Sayangnya, warisan ini tidak hanya dipertahankan oleh elite yang menikmati kuasa, tetapi juga diinternalisasi oleh rakyat. Paulo Freire (1985) menyebutnya sebagai “mentalitas terjajah”, sebuah kondisi psikologis di mana korban penindasan tanpa sadar mulai mengidentifikasi diri dengan nilai-nilai penindasnya. Ketika masyarakat menganggap wajar untuk tidak membantah pemimpin, ketika kritik dianggap tidak sopan, dan ketika suara rakyat diredam oleh rasa takut atau rendah diri, maka demokrasi deliberatif menjadi sangat sulit tumbuh.
Ruang Publik yang Tidak Bebas
Demokrasi deliberatif, sebagaimana dikembangkan oleh Jürgen Habermas (dalam Hardiman: 2009), menekankan pentingnya ruang publik yang memungkinkan warga berdiskusi secara terbuka, rasional, dan setara. Dalam model ini, keputusan politik idealnya lahir dari proses pertukaran argumen yang masuk akal, bukan dari tekanan kekuasaan atau kekuatan uang. Namun di Indonesia, ruang publik masih tersandera oleh berbagai bentuk dominasi, baik oleh elite politik, penguasa ekonomi, maupun norma sosial yang represif.
Media massa arus utama sebagian besar masih dikuasai oleh kelompok oligarki yang berkepentingan mempertahankan status quo. Sementara itu, ruang digital meskipun lebih terbuka sering kali dipenuhi polarisasi, ujaran kebencian, dan disinformasi. Warga yang mencoba menyampaikan pendapat dengan nalar sering tersisih oleh narasi emosional atau serangan personal. Dalam iklim seperti ini, deliberasi sebagai proses pertimbangan rasional menjadi barang langka.
Bukan hanya soal media, struktur partisipasi politik formal juga belum sepenuhnya mendukung demokrasi deliberatif. Forum-forum seperti musyawarah desa, musrenbang, hingga rapat dengar pendapat di parlemen kerap menjadi formalitas belaka, tanpa ruang diskusi yang sejati. Partai politik lebih sibuk dengan urusan elektoral dan transaksi kekuasaan, ketimbang menjadi saluran aspirasi rakyat.
Budaya Politik yang Anti-Kritis
Masalah yang tak kalah serius adalah rendahnya literasi politik dan terbatasnya ruang untuk belajar berpikir kritis. Pendidikan kita, dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi, lebih banyak mengajarkan kepatuhan daripada pertanyaan.
Siswa diajarkan untuk menghafal, bukan berdebat. Guru dan dosen sering dianggap otoritas mutlak yang tidak boleh dibantah. Tidak mengherankan jika masyarakat kemudian terbiasa tunduk pada kekuasaan, bukan berdiskusi dengannya.
Di ruang sosial, budaya malu, takut berbeda, dan tunduk pada senioritas memperparah kondisi. Orang muda yang kritis sering dicap kurang ajar. Warga yang mengorganisir protes dianggap mengganggu ketertiban.
Bahkan di lingkungan keluarga, nilai-nilai demokrasi seperti mendengar pendapat anak atau berdiskusi terbuka belum menjadi praktik umum. Demokrasi, dalam banyak hal, belum menjadi budaya, melainkan hanya mekanisme teknis.
Jalan Panjang Mewujudkan Demokrasi Substansial
Namun, kondisi ini bukan alasan untuk menyerah. Demokrasi deliberatif bukan utopia, tetapi proyek politik jangka panjang. Ia hanya bisa dibangun jika kita secara kolektif mulai mengikis sisa-sisa feodalisme yang tertanam dalam cara berpikir dan bertindak kita sehari-hari.
Ini bukan hanya tugas elite politik atau akademisi, tetapi juga tanggung jawab warga biasa, membuka ruang diskusi di lingkungan, melatih keberanian berbicara, dan membangun solidaritas berbasis kesadaran, bukan sekadar kepatuhan.
Kita juga membutuhkan lebih banyak teladan pemimpin anti-feodal, baik di tingkat nasional maupun lokal, pemimpin yang mendengarkan, yang membuka ruang partisipasi, dan tidak menjadikan kekuasaan sebagai alat untuk mengontrol. Di sisi lain, gerakan masyarakat sipil harus tetap menjadi ruang kritis yang merawat benih-benih deliberasi, meski kecil, meski sering sendiri.
Dalam konteks ini, menyalahkan rakyat karena pasif memang bisa jadi terdengar wajar, tetapi jauh lebih penting untuk menyadarkan dan membebaskan mereka dari belenggu budaya yang menindas. Sebab pada akhirnya, feodalisme akan runtuh bukan ketika elite berubah, tapi ketika rakyat berhenti percaya bahwa mereka harus selalu tunduk.
Keberanian di Tengah Risiko: Refleksi Manusiawi
Namun, pertanyaan penting yang sering muncul adalah “Apakah keberanian untuk tidak tunduk ini realistis dalam kondisi Indonesia saat ini, di mana kritik dan perlawanan bisa berujung kriminalisasi, intimidasi, bahkan ancaman fisik?”.
Jawabannya: Ya, risiko itu nyata dan tidak bisa diabaikan. Banyak aktivis, jurnalis, dan warga biasa mengalami tekanan, dipenjara, atau dibungkam karena menyuarakan kebenaran. Keberanian untuk berbicara atau bertindak tidak berarti bebas risiko. Namun, sejarah perubahan sosial dan politik membuktikan bahwa tanpa keberanian, perubahan mustahil terjadi.
Keberanian harus strategis dan kolektif, bukan sekadar nekat dan individualistis. Dengan solidaritas dan strategi yang cermat, ruang untuk menyuarakan pendapat dan melakukan kritik dapat diperluas meski dalam keterbatasan.
Keberanian bukan berarti menantang kekuasaan secara membabi buta, tetapi menolak normalisasi ketidakadilan dalam kehidupan sehari-hari, membuka ruang diskusi, dan membangun jaringan yang saling menguatkan.
Memang, keberanian membawa risiko tersingkir atau dikriminalisasi, tapi diam juga bukan tanpa risiko. Tunduk dan pasrah menimbulkan luka sosial yang lebih dalam dan menunda harapan demokrasi sejati bagi generasi mendatang.
Indonesia bisa menjadi ruang demokrasi yang lebih hidup, substantif, dan adil hanya jika kita berani meninggalkan warisan ketundukan dan menggantinya dengan keberanian untuk berpikir, berbicara, dan bertindak. Demokrasi deliberatif menuntut ruang, pendidikan, dan keteladanan. Tapi lebih dari itu, ia menuntut keberanian yang cerdas dan kolektif untuk tidak lagi tunduk, walaupun risiko itu selalu ada.