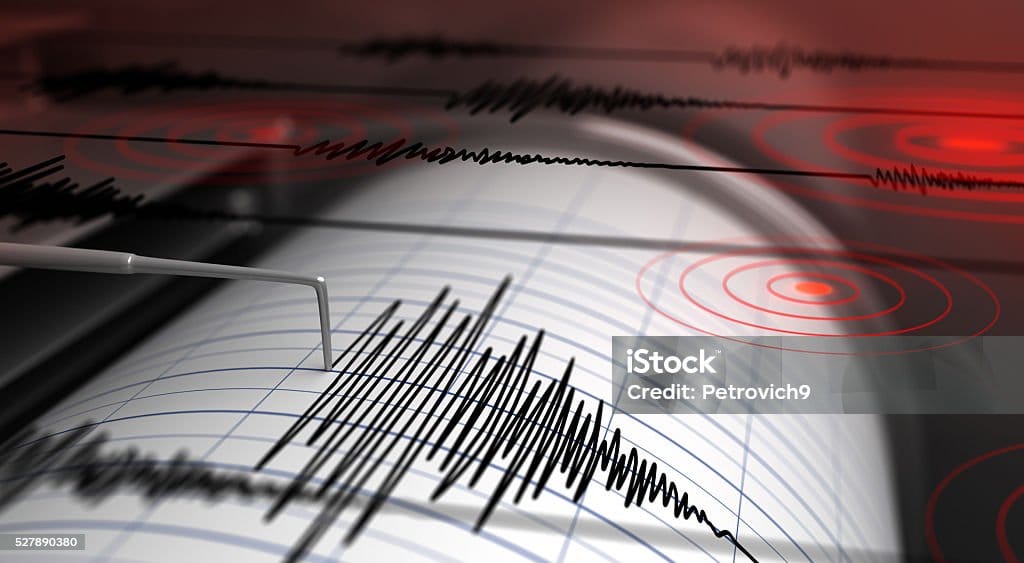Gelombang protes rakyat yang mengguncang Indonesia sejak akhir Agustus hingga awal September 2025 meninggalkan banyak pelajaran penting. Ribuan orang dari berbagai kota turun ke jalan, membawa tuntutan yang terang, mulai dari penarikan TNI dari pengamanan sipil, pembentukan tim investigasi independen atas korban kekerasan aparat, penghentian kenaikan gaji DPR, hingga reformasi partai politik dan perlindungan buruh.
Semua terangkum dalam 17 tuntutan jangka pendek dan 8 tuntutan jangka panjang yang berusaha memetakan arah baru demokrasi Indonesia.
Namun, di tengah pekikan massa, ada satu suara yang justru hilang: suara para intelektual publik. Orang-orang yang selama ini digadang sebagai penjaga nurani bangsa—tokoh agama, akademisi, pemimpin ormas, bahkan ketua partai—justru lenyap dari gelanggang, atau hadir hanya untuk menenangkan situasi demi kepentingan penguasa.
Diamnya para penjaga moral
Sepanjang protes, masyarakat melihat bagaimana tokoh agama besar memilih duduk di samping pejabat negara. Mereka tampil di televisi bukan untuk menegur kekuasaan, melainkan untuk mengimbau rakyat agar “menjaga kedamaian” dan “tidak mudah terprovokasi”. Kata-kata yang dilontarkan lebih mirip doa legitimasi ketimbang kritik moral.
Di kampus, ruang intelektual pun senyap. Jarang terdengar pernyataan sikap keras dari guru besar atau asosiasi akademik. Forum-forum diskusi lebih banyak berbicara tentang teknis pembangunan ketimbang menyelami jeritan rakyat. Sebagian bahkan larut dalam kenyamanan proyek dan jabatan, melupakan tugas dasar universitas sebagai pengawal kebenaran.
Ironisnya, partai politik—yang justru lahir dari mandat rakyat—lebih sibuk menjaga harmoni dengan pemerintah. Para ketua partai duduk di meja kekuasaan, bernegosiasi dalam ruangan tertutup, bukan di tengah massa yang mempercayakan suara. Rakyat pun semakin dikhianati, mandat yang diberikan di bilik suara ternyata hanya tiket masuk ke lingkaran elite, bukan komitmen membela kepentingan publik.
Hastinapura yang terulang
Fenomena ini mengingatkan pada kisah kelam Mahabharata. Di aula megah Hastinapura, Drupadi dipermalukan di depan para ksatria besar. Durna, Bisma, Widura, dan Kripacharya hadir, tetapi semua memilih diam. Tidak satu pun berani menegur penguasa, dan sunyi itu justru menjadi restu bagi kejahatan.
Kini, rakyat Indonesia seolah menjadi Drupadi. Kehormatannya dipertaruhkan di meja dadu politik, ditelanjangi oleh kebijakan yang tak adil dan keserakahan elite. Para ulama, akademisi, dan pemimpin ormas yang seharusnya berdiri sebagai perisai justru memilih bungkam, atau malah menjadi pembaca doa di upacara peresmian kebijakan yang menyakiti rakyat.
Seperti Hastinapura yang runtuh dalam perang Kurukshetra, negeri ini juga bisa tergelincir ke jurang kehancuran jika suara moral terus bungkam. Sunyi yang terlihat netral sejatinya bukanlah ketidakberpihakan, melainkan keberpihakan kepada yang zalim.
Lahirnya suara dari bawah
Namun, ketika intelektual formal bungkam, suara lain justru lahir dari bawah. Sosok-sosok baru bermunculan, bukan dari podium kampus atau mimbar ormas, melainkan dari ruang digital. Mereka bukan profesor, bukan ketua partai, melainkan individu-individu yang berangkat dari kegelisahan sehari-hari.
Nama-nama seperti Jerome Polin dan Ferry Irwandi mencuat karena mampu merumuskan keresahan rakyat dalam bahasa sederhana bersama masyarakat sipil. Dengan unggahan, siaran langsung, dan narasi digital, mereka menyatukan keresahan yang tercerai-berai menjadi tuntutan bersama.
Dari mereka lahir istilah 17+8 Tuntutan Rakyat, yang kemudian menyebar ke berbagai kota dan menjadi benang merah protes nasional.
Fenomena ini menunjukkan bahwa kepemimpinan rakyat telah terdesentralisasi. Tidak ada satu tokoh kharismatik yang bisa ditangkap untuk mematahkan gerakan. Protes ini cair, menyebar, dan tumbuh dari bawah. Inilah wajah baru perlawanan berupa jaringan horizontal yang tidak bergantung pada struktur hierarkis, tetapi bertahan melalui solidaritas dan kepercayaan.
Kekuatan dan kerentanan
Kepemimpinan desentralisasi membawa keuntungan besar. Ia sulit ditunggangi oleh kepentingan sempit, sulit dipatahkan dengan sekadar membungkam satu figur, dan memberi ruang bagi partisipasi luas.
Namun, ia juga rentan. Tanpa tokoh jelas, tuntutan bisa perlahan hilang dalam riuh informasi. Represi digital, pemutusan jaringan, atau dominasi media arus utama bisa dengan mudah mengaburkan substansi.
Di sinilah sebenarnya peran intelektual publik dibutuhkan untuk memastikan gagasan tidak hilang, untuk merawat substansi agar tidak larut dalam slogan kosong. Sayangnya, mereka justru memilih diam, membuat gerakan rakyat bergantung pada daya tahan narasi digital yang rapuh.
Damai yang membius
Di tengah situasi genting, muncul pula narasi “damai” dari sejumlah influencer besar. Mereka mengajak masyarakat pulang, menekankan pentingnya stabilitas, dan memuji aparat yang dianggap sudah “menahan diri”. Sekilas terdengar mulia, tetapi sesungguhnya ini berbahaya.
Damai yang mereka maksud bukan damai yang lahir dari keadilan, melainkan damai yang membiarkan ketidakadilan tetap berdiri. Ia mengalihkan fokus dari substansi tuntutan rakyat, mereduksi protes menjadi sekadar keramaian yang harus ditertibkan.
Protes kehilangan daya tekan, rakyat diajak merasa puas hanya karena tidak ada kerusuhan, padahal masalah struktural tetap dibiarkan.
Damai semacam ini ibarat perban yang menutupi luka tanpa membersihkannya. Luka mungkin tak terlihat, tetapi infeksi terus menjalar. Dalam jangka panjang, ia lebih berbahaya daripada kericuhan singkat, karena melestarikan ketidakadilan dengan wajah tenang.
Mandat yang dipelintir
Di titik ini kita bisa melihat dengan jelas krisis demokrasi representatif. Partai politik, yang seharusnya menjadi kanal aspirasi, justru berubah menjadi pagar yang menghalangi suara rakyat mencapai pusat kekuasaan. Pemilu hanya menghadirkan ilusi partisipasi “rakyat memilih, tetapi setelah itu ditinggalkan”.
Inilah mengapa rakyat mencari jalannya sendiri. Mereka membangun solidaritas horizontal, merumuskan gagasan bersama, dan bergerak tanpa menunggu komando partai.
Di jalanan, rakyat menyadari bahwa demokrasi tidak cukup hanya lewat kotak suara. Demokrasi sejati harus lahir dari musyawarah langsung, solidaritas organik, dan kesediaan berbagi tanggung jawab.
Menolak sunyi, menolak palsu
Protes rakyat 2025 telah menunjukkan dua wajah bangsa, wajah elit yang sibuk bermain dadu di aula kekuasaan, dan wajah rakyat yang mencoba menyusun dunia baru dari bawah. Namun, wajah yang hilang adalah wajah intelektual publik.
Diamnya ulama, akademisi, dan ketua partai adalah bentuk pengkhianatan moral. Mereka yang seharusnya menjadi kompas justru menutup mulut, seolah lupa bahwa legitimasi kekuasaan tidak hanya berasal dari hukum, tetapi juga dari kepercayaan moral.
Jika suara moral terus menghilang, negeri ini berjalan menuju kehancurannya sendiri—Kurukshetra dalam versi modern, perang tanpa pemenang di atas reruntuhan sosial dan ekonomi.
Jalan yang masih terbuka
Meski demikian, protes ini juga membuka harapan. Lahirnya intelektual organik dari ruang digital membuktikan bahwa rakyat masih punya daya. Solidaritas horizontal menunjukkan bahwa tanpa hierarki pun gerakan bisa tumbuh.
Tugas ke depan adalah menjaga agar gagasan tetap hidup, agar tuntutan tidak hilang dalam kabut propaganda.
Rakyat tidak menunggu restu penguasa, tidak pula menunggu fatwa intelektual yang nyaman di kursi kekuasaan. Mereka sedang belajar mengorganisir diri, menata kekuatan tanpa hierarki, dan membangun dunia politik baru yang lebih setara.
Sejarah memberi peringatan keras, sunyi yang tampak anggun pada akhirnya hanyalah restu bagi kezaliman. Jika para penjaga moral terus memilih diam, maka suara itu akan diambil alih oleh rakyat sendiri, dengan cara mereka, dengan bahasa mereka, dan dengan jaringan mereka.
Sebab, demokrasi sejati bukanlah ritual lima tahunan, melainkan keberanian sehari-hari untuk bersuara, membangun solidaritas, dan menolak tunduk pada dadu kekuasaan.