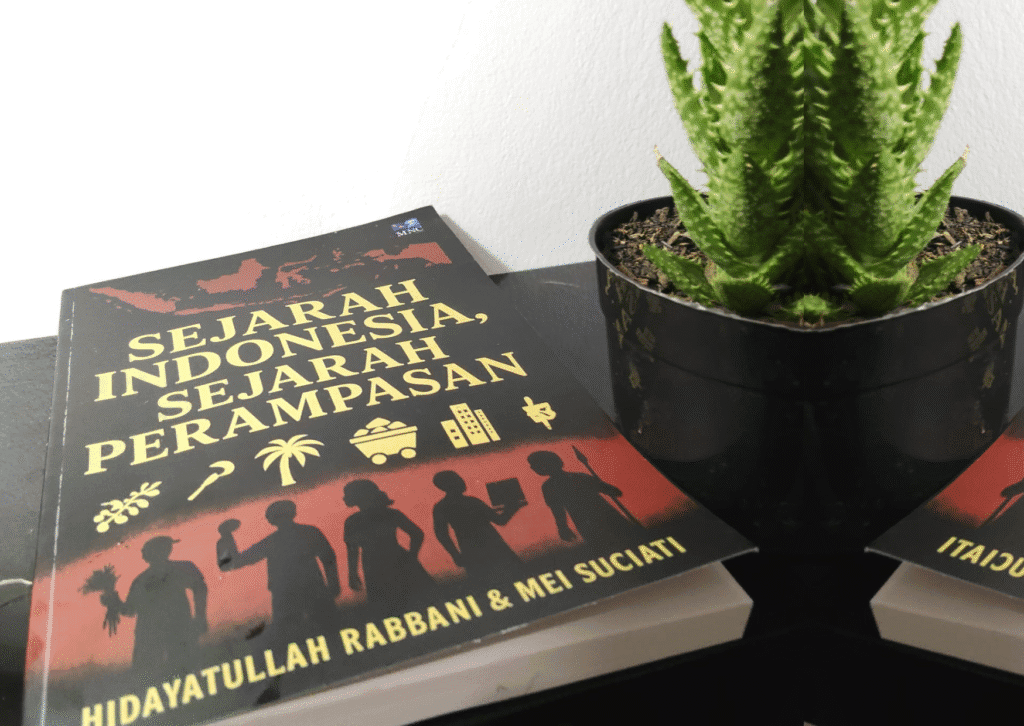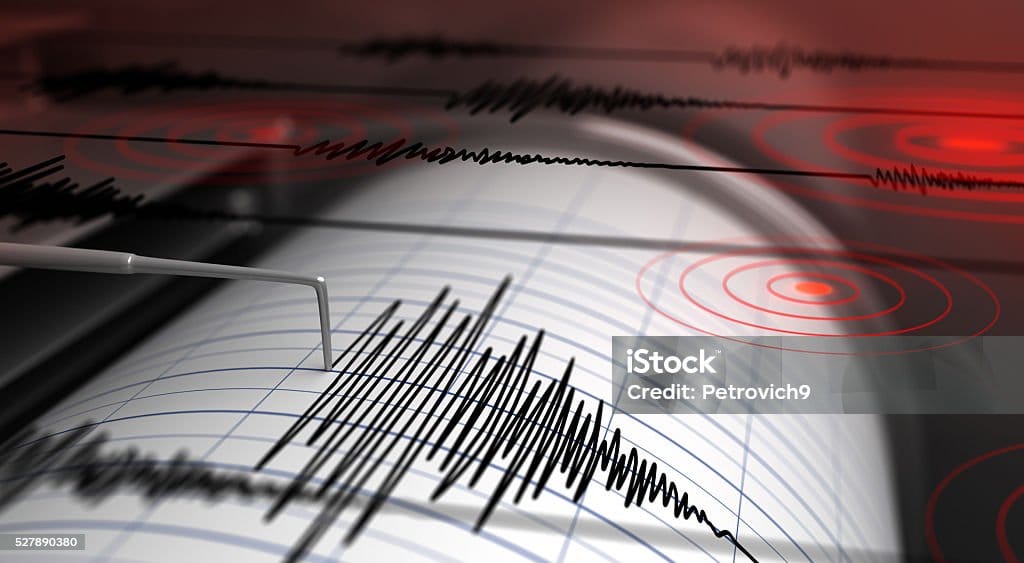Eksil barangkali satu-satunya film bertema 1965 yang cukup diterima publik dengan baik tanpa ada larangan berarti, walaupun di Samarinda sempat ada pembatalan mendadak. Namun, dari semua penayangan swadaya maupun reguler di bioskop, film ini mendapat sambutan hangat. Film ini pun ramai di media sosial seperti X (Twitter) dan membuat banyak orang penasaran menontonnya.
Jika film seperti Jagal dan Senyap besutan Joshua Oppenheimer meneropong cerita dan nasib pelaku, Eksil tampil menghadirkan suara korban yang saat peristiwa 1965 ada di luar negeri. Para korban yang awalnya kuliah atas beasiswa atau rekomendasi Sukarno terpaksa dicabut status warga negaranya karena dipaksa untuk mengutuk rezim Sukarno. Saat itu, kondisi di Indonesia sudah sangat chaos dan pembantaian terjadi di mana-mana seiring operasi Angkatan Darat.
Para mahasiswa yang kini sudah berusia senja itu tersebar di berbagai negara, seperti China, Uni Soviet, Belanda, Cheko-Slovakia, Jerman, dan Swedia. Jika para eksil dari negara lain biasanya sudah bisa hidup dan berpikir seperti negara yang mereka tempati, para Eksil Indonesia cukup berbeda. Mereka masih hidup dan berpikir dengan kebiasaan sebagai orang Indonesia. Pada tahun-tahun yang panjang, mereka terus mengikuti pemberitaan di Indonesia. Bahkan, salah satu tokoh dalam film Eksil menanam pohon pisang di rumahnya untuk terus merawat rasa sebagai orang Indonesia.
Selain itu, tak semua dari mereka terafiliasi PKI—Partai Komunis Indonesia—yang saat itu menjadi tertuduh di Jakarta dan yang dalam bahasa John Roosa menjadi dalih pembunuhan massal di berbagai daerah. Sejak peristiwa berdarah tersebut, segala hal yang berkaitan, baik langsung maupun tidak, dengan PKI dinyatakan sebagai pihak bersalah dan layak diperlakukan dengan sangat tidak layak sebagai seorang manusia.
1965 dalam Bayang-Bayang Politik Elektoral
Sejak 1998, isu 1965 beberapa kali mengalami pasang-surut. Setelah kekuasaan Soeharto sebagai simbol tertinggi Orde Baru runtuh, pembicaraan isu tersebut bisa dimulai. Di masa kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid, ada sedikit harapan untuk penyelesaian kasus kemanusiaan terbesar dalam sejarah Indonesia modern itu.
Saat itu, Gus Dur membawa gagasan untuk mencabut Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) No 25 tahun 1966 tentang Pelarangan Partai Komunis Indonesia (PKI). Bagi Gus Dur, TAP MPR ini adalah muasal dari diskriminasi yang diciptakan oleh negara terhadap orang-orang yang pernah terafiliasi maupun yang tertuduh PKI sekaligus bertentangan dengan konstitusi yang seharusnya melindungi semua warga negara.
Tidak hanya itu, Gus Dur juga menyatakan permintaan maaf kepada simpatisan PKI secara terbuka di TVRI beberapa bulan setelah ia menjabat sebagai presiden. Bahkan, permintaan maaf tersebut pernah Gus Dur sampaikan langsung ke Pramoedya Ananta Toer yang menjadi salah satu korban kebengisan Orde Baru. Selain itu, udara segar bagi para Eksil hampir terwujud saat Gus Dur mencoba mencari jalan rekonsiliasi dan para eksil kembali mendapat haknya sebagai warga negara.
Baca juga: Tak Hanya El Nino, Beras Mahal karena Rapuhnya Adaptasi Iklim Pertanian Kita
Namun, harapan itu kemudian pupus sebab ternyata orang yang diutus Gus Dur berada di sisi yang berseberangan. Utusan Gus Dur untuk menemui para Eksil itu adalah Yusril Ihza Mahendra yang saat itu menjadi menteri kehakiman dan hak asasi manusia.
Alih-alih membawa misi rekonsiliasi, Yusril hanya sekadar sosialisasi dan plesir di Eropa. Setelah tak sepakat dengan Gus Dur atas penghapusan TAP MPR No 25 tahun 1966, Yusril masih khawatir kalau komunisme masih akan terus eksis di Indonesia. Sikap anti-komunisme inilah yang membuat Yusril enggan menjalankan misi rekonsiliasi atas kasus pembantaian massal 1965, terutama memberi ruang kembali untuk para Eksil di Eropa.
Setelah harapan para Eksil itu pupus bersama ambruknya pemerintahan Gus Dur, pembicaraan isu 1965 relatif senyap dan bahkan tak ada perkembangan yang cukup signifikan. Di tahun yang sama menjelang Gus Dur lengser, pembakaran buku Pemikiran Karl Marx: Dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme karangan Franz Magnis Suseno oleh kelompok aliansi anti-komunisme semakin memperparah keadaan. Sejak itu, pembicaraan tentang rekonsiliasi secara struktural mandek.
Selain itu, antara 2015-2016 menjadi tahun terpanas perbincangan isu 1965 setelah film Senyap rilis pada akhir 2014. Pemutaran film tersebut memicu letupan anti-komunisme kembali dan berbagai pemutaran gagal dilakukan. Di Yogyakarta, pada awal 2015, beberapa pemutaran tak bisa dilakukan dan bahkan diwarnai ancaman. Namun, pada 11 Maret 2015, yang juga bertepatan dengan peristiwa Supersemar, nobar film Senyap berhasil digelar di UIN Sunan Kalijaga, walau dengan ancaman pihak kampus dan ormas-ormas reaksioner yang berkumpul di luar kampus.
Arah Politik Permaafan Kita
Saat Gus Dur memimpin negeri ini, politik permaafan atas tragedi 1965 diusahakan melalui jalur negara. Namun, walaupun Soeharto sudah lengser, anasir-anasir Orde Baru dan cara pandang yang umum atas PKI dan komunisme masih terus lestari. Selain itu, para pejabat politik enggan untuk menyelesaikan persoalan ini, antara masih percaya bahwa komunisme itu sesat atau mereka-mereka yang mengamankan posisi politiknya sendiri.
Di akar rumput, proses rekonsiliasi terus berlanjut, walau berjalan lambat. Sementara itu, janji-janji politik penyelesaian masa lalu terus diumbar tanpa bisa diharapkan. Pada 2023 lalu, Presiden Jokowi mengeluarkan kebijakan sebagai upaya penyelesaian pelanggaran HAM berat secara non-yudisial berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 17 Tahun 2022 dan kembali diperbarui melalui Keppres Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tim Pemantau Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, pada 15 Maret 2023. Upaya ini membuat Jokowi bertemu dengan beberapa eksil di berbagai tempat di Belanda dan Ceko serta menemui beberapa lokasi yang menjadi tempat korban kekerasan negara.
Namun, upaya penyelesaian non-yudisial ini hanya mengakui bahwa negara telah melakukan 12 pelanggaran HAM berat di masa lalu, termasuk tragedi berdarah pembantaian massal 1965. Menurut Mahfud MD (saat itu menjabat Menko Polhukam), negara melalui Presiden hanya mengakui terjadi pelanggaran HAM dan negara tidak akan dan tidak ada permintaan maaf. Mahfud juga menegaskan bahwa TAP MPR No. 25 1966 tentang Pelarangan Partai Komunis Indonesia masih berlaku. Tidak hanya itu, negara juga tidak ada rencana untuk mengusut siapa dalang dan pelaku atas tragedi berdarah tersebut.
Di satu sisi, langkah penyelesaian non-yudisial ini menjadi langkah maju atas berbagai kebuntuan dan keengganan politik pemangku kebijakan untuk menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM. Namun, di sisi lain, langkah ini dipertanyakan sebab tidak turut mengadili siapa yang paling bertanggung jawab atas kasus kekerasan masa lalu tersebut.
Baca juga: Kumpulan Tulisan Mengenang Ignas Kleden
Bagaimana mungkin kejahatan hanya bertumpu pada pemulihan korban, sementara pelaku tidak pernah diadili. Hal ini tidak hanya layak disebut sebagai bagian dari impunitas, melainkan juga kejahatan serupa yang dilakukan negara berpotensi kembali terulang di masa depan.
Langkah politik permaafan kita sebagai bangsa sekaligus negara belum semaju Jerman atau Afrika Selatan. Negara meminta maaf dan mengupayakan rekonsiliasi dan memberikan kompensasi kepada seluruh korban, baik materil maupun non-materil. Selain itu, perlu tugu peringatan atau museum yang menjelaskan kasus tersebut dengan jernih agar tidak terulang di masa depan.
Tanpa itu semua, pengakuan atau permintaan maaf atas kekerasan dan tragedi kemanusiaan di masa lalu hanya menjadi omong kosong belaka. Semoga negeri ini bukan negeri yang melanggengkan impunitas, negeri yang terus belajar dari sejarah, dan tak mengulang masa kelamnya.[]