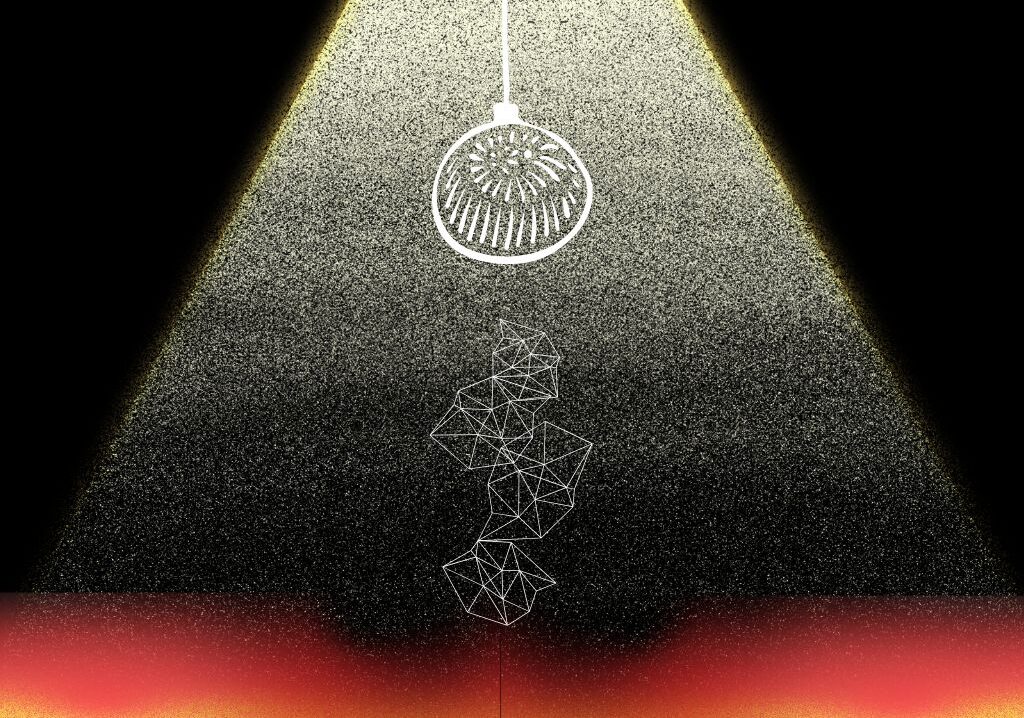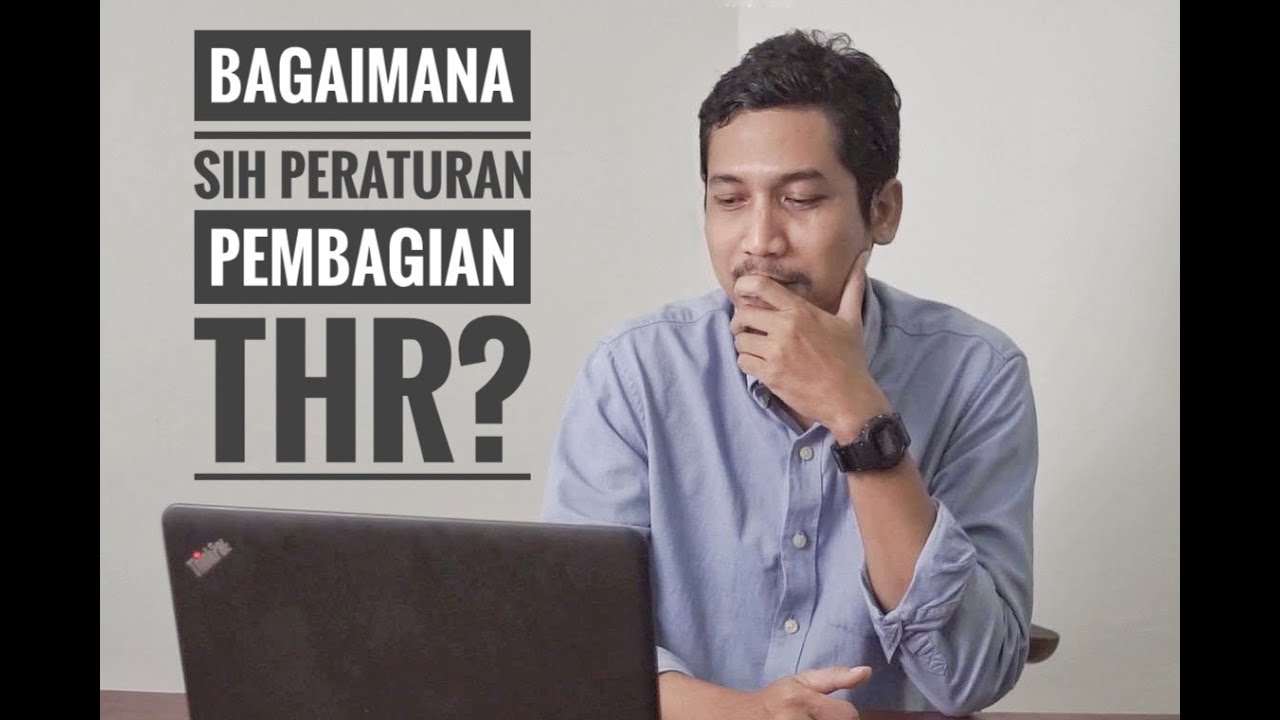Catatan redaksi: Dalam polemik sastra antara Ignas Kleden (almarhum) dan Afrizal Malna pada 1997, dua sastrawan turut memberikan komentar, yakni Budi Darma dan Nirwan Dewanto. Hal ini dibahas juga oleh Afrizal Malna dalam esai Sampah yang Berputar di Luar Rahasia (Kompas, 19 Oktober 1997).
Tulisan ini adalah hasil kliping kerabat kerja ProPublika.id, dipublikasikan ulang untuk tujuan pendidikan. Jika ada yang keberatan diterbitkannya arsip ini, kerabat kerja ProPublika.id terbuka untuk berdialog.
Polemik sastra pada 1997 ini diterbitkan ulang untuk mengenang sosiolog Ignas Kleden yang belum lama ini berpulang. Seri polemik sastra ini bisa diikuti di tautan ini: klik. Selamat membaca. Tabik!
Kembali ke Solilokui
(Arsip Kompas Minggu, 21 September 1997, halaman 21)
Oleh Budi Darma
ADA seorang penyair Amerika, Robert Frost namanya. Dia menulis banyak sajak, antara lain Stopping by Woods on a Snowy Evening. Dari sekian banyak pembicaraan mengenai sajak ini terdapat semacam “kesepakatan umum” sesama pembaca, bahwa sajak ini mengungkapkan keinginan untuk meninggal. Maka, dalam pertemuan di Universitas Iowa pada tanggal 13 April 1959, seorang pembicara menanyakan kebenaran “kesepakatan umum” ini kepada Robert Frost. Dan Robert Frost menjawab, bahwa sajak ini sama-sekali tidak ada hubungannya dengan keinginan untuk meninggal. Namun sejarah menunjukkan, bahwa “kesepakatan umum” mengenai sajak ini ternyata tetap berlaku.
Dari kasus ini kita tahu, bahwa maksud pengarang sangat mungkin berbeda dengan penangkapan pembaca. Dan kita mafhum, baik pengarang maupun pembaca sama-sama benarnya. Pengarang benar karena pengarang tahu maksud pengarang sendiri, dan pembaca benar karena pembaca merasakan adanya kunci-kunci dalam karya sastra yang menyebabkan pembaca mau tidak mau berpendapat demikian.
Perbedaan dapat terjadi, karena pembaca tidak lain adalah organisme hidup. Dalam kedudukannya sebagai organisme hidup, dimensi pembaca, karena berbagai faktor, dapat berubah. Leon Agusta pernah menyatakan, bahwa dia merasa benar-benar dapat mengakrabi novel-novel etnik Indonesia, ketika dia membacanya di Amerika. Seorang teman di Indiana juga menyatakan, dia sanggup menangkap metafora-metafora novel-novel Kafka, setelah dia mendengar salak anjing pada suatu Minggu malam. Pada saat itulah dia sadar, bahwa keesokan harinya, Senin, dia harus memasuki rutinitas kerja kantornya, bagaikan Gregor Samsa dalam novel pendek Kafka Metamorphosis.
Maka, perbedaan bisa terjadi bukan hanya antara pengarang dengan pembaca, tapi juga antara pembaca satu dengan pembaca lain. Dan, perbedaan juga bisa terjadi antara pembaca dengan dirinya sendiri. Ketika pengarang membaca kembali karyanya, mungkin dia juga menemukan sesuatu yang semula tidak disadarinya sendiri.
Dalam contoh-contoh di atas, perbedaan antara pengarang dengan pembaca terjadi secara spontan. Pemahaman pembaca benar-benar dilandasi oleh selera dan akal sehatnya. Teori, baik yang sederhana maupun yang canggih atau dicanggih-canggihkan, tidak dipergunakan. Pengarang benar-benar polos. Meskipun pemahaman pembaca didasarkan atas kunci-kunci tertentu yang menurut pendapat pembaca hadir dalam karya sastra yang dihadapinya, pembaca sama sekali tidak mengajukan argumentasi ini atau itu.
Kira-kira, begitulah sikap yang diusulkan oleh Seno Gumira Ajidarma pada saat Kompas menyelenggarakan diskusi mengenai kumpulan cerpen Anjing-anjing Menyerbu Kuburan. Biarlah cerpen dilepaskan kepada pembaca, dan biarkanlah pembaca menentukan sendiri. Spontanitas pembaca diminta, demikian pula kepolosan membaca.
Orang-orang macam Seno memang ada, demikian pula orang-orang yang menghendaki argumentasi. Dan mereka yang menghendaki argumentasi pun ada yang menginginkan argumentasi berdasarkan akal sehat, ada pula yang meminta teori. Dan orang-orang yang meminta teori tentunya mempunyai berbagai alasan. Ignas Kleden, misalnya, mempergunakan teori untuk membuktikan bahwa pendapat dia mengenai cerpen ini dan cerpen itu tidak salah.
Bagi beberapa pihak, teori juga dipergunakan untuk mencari hal-hal yang mungkin tidak dapat diketahui melalui selera dan akal sehat belaka. Lihatlah, misalnya, usaha beberapa pihak untuk lebih memahami karakter Bovari dalam novel Gustav Flaubert Madame Bovary. Maka, disimaklah kesukaan Bovary terhadap topi-topi wanita. Dia suka topi ini tapi tidak suka topi itu, dan demikian seterusnya. Dari situ, karakter Bovary yang sesungguhnya, kata mereka sendiri, dapat diungkap.
Karena manusia serba beragam, ada pula pihak lain yang mempergunakan teori tidak untuk mencari kebenaran, tapi untuk membenar-benarkan. Orang- orang semacam ini, tidak lain mempergunakan teori hanya untuk membenarkan pendapatnya sendiri, bukan untuk membuktikan apakah pendapatnya benar atau tidak. Bagaikan statistik dalam penelitian kuantitatif, kalau perlu teori juga dapat dibengkak-bengkokkan.
Bukan hanya itu. Ada pula pihak yang amat bernafsu untuk mempergunakan teori, semata agar mereka tidak dituduh ketinggalan zaman. Sejak awal tahun 1970-an, memang, teori sastra berkembang. Maka, barang siapa tidak mempergunakan teori, khususnya teori mutakhir, akan mendapat ejekan.
Namun, sebenarnya, khalayak sastra menginginkan pendapat yang berbobot, bukannya pendapat yang sebetulnya kurang bermakna namun diselindungkan dengan penggunaan teori ini dan teori itu. Goenawan Mohamad dan Emha Ainun Najib, misalnya, dalam Kongres Kesenian ke-I menyatakan, bahwa teori sering dipergunakan oleh orang-orang yang sebetulnya tidak tahu sastra. Teori, dengan demikian, kata mereka, difungsikan sebagai kedok untuk menutupi kelemahan.
Sekali lagi, perbedaan pendapat antara pengarang dan pembaca benar-benar masuk akal. Perbedaan pendapat sesama pembaca juga masuk akal, demikian pula perbedaan pendapat antara pembaca dengan dirinya sendiri. “Kesepakatan umum” mengenai sajak Stopping by Woods on a Snowy Evening, ternyata juga terpecah menjadi sekian banyak polarisasi.
Beda pendapat diikuti dengan debat juga sangat masuk akal. Debat bisa terjadi, antara lain, karena masing-masing pihak berusaha untuk mempertahankan pendapatnya. Dulu, misalnya, ada debat antara Ayip Rosidi dengan MS Hutagalung mengenai sajak Ayip Rosidi, Ular. Juga, dulu, pernah ada debat antara Ayip Rosidi dengan Umar Yunus mengenai sajak-sajak Sutarji Calzoum Bachri.
Debat untuk mencari titik-temu pendapat, atau untuk memperjelas beda pendapat, atau untuk mencari kebenaran, atau juga untuk kepentingan berdebat itu sendiri ditambah dengan kepentingan untuk saling menindas, tentu saja amat baik. Semua jenis debat ini dapat memperluas dan mempertajam wawasan khalayak yang mengikuti debat. Sementara itu kita tahu, sekian banyak debat akhirnya menjadi berkepanjangan, dan sering pula akhirnya hanya berputar-putar belaka.
Kalau sebuah perdebatan sudah berputar-putar, mungkin lelucon dalam sajak Robert Frost, The Secret Sits, bisa menjadi benar. Kata dia: We dance around in a ring and suppose, but the secret sits in the middle and knows. Kita hanya berputar-putar, sementara rahasia yang sesungguhnya ternyata duduk di tengah dan tahu bahwa kita hanyalah berputar-putar mencari rahasia.
Lalu, mengapa debat bisa berkepanjangan? Tidak lain karena masing-masing pihak memegang argumentasi sendiri-sendiri. Kalau yang satu mencuplik suatu teori dari segi ini, maka pihak lain mencuplik teori yang mungkin sama, tapi dari segi bukan ini, tapi segi itu. Kedua belah pihak benar karena baik teori maupun karya sastra pada hakikatnya adalah multidimensional. Sebuah karya sastra, dengan demikian, dapat menimbulkan sekian banyak pendapat yang berbeda. Karena itu, kritik sastra berjalan terus.
Demikianlah, debat bisa berkepanjangan. Dan demikianlah, debat, termasuk yang berkepanjangan dan yang sekadar berputar-putar tetap dapat mempertajam dan memperluas wawasan. Namun, akhirnya toh ada satu hal hakiki yang dituntut, yaitu kejernihan pikiran. Justru kejernihan pikiran inilah yang menentukan bobot suatu pendapat.
Tentu saja, kejernihan pikiran tidak selamanya dinyatakan dengan lugas. Teori yang canggih, lukisan surealis, novel absurd, dan lain-lain yang non-konvensional bisa saja merupakan pengendapan kejernihan pikiran. Pelukis abstrak yang berpikiran jernih misalnya, akan mampu menggambar sebuah lubang hidung pamannya bagaikan memotret lubang hidung itu.
Bahwa Nirwan Dewanto kemudian menuntut penulis (maksudnya pengarang) untuk mampu menguasai bahasa, itu benar. Penulis lain pun, jadi bukan hanya pengarang, sebenarnya, juga dikenai tuntutan sama. Titik beratnya sama, yaitu bahwa dalam berbahasa, kejernihan pikiran merupakan prasyarat yang sangat penting. Banyak benar memang, penggunaan kata-kata gagah dalam penulisan, yang sebenarnya tidak bermakna. Kata-kata “paradigma,” “kooptasi,” “direduksi,” “kanalisasi,” “parameter,” dan entah apa lagi, dipakai tidak lain karena pikiran penulisnya tidak jernih.
Hakikat sastra memang jungkir-balik. Dikatakan begini bisa salah bisa benar, demikian pula dikatakan begini dan bukan begitu. Dan akhirnya, setiap potong argumentasi penggunaan teori sebenarnya tidak lain merupakan dialog antara penulis terhadap dirinya sendiri, bukan terhadap mitra atau lawan debatnya.
Mengapa? Karena yang satu mencuplik bagian ini dan yang lain bagian itu, sehingga lalu lintas pemikiran tidak bisa “klop.” Mungkin, begitulah hakikat sastra: jungkir-balik, dan pembicaraan dengan diri sendiri.
*Budi Darma, pengarang.